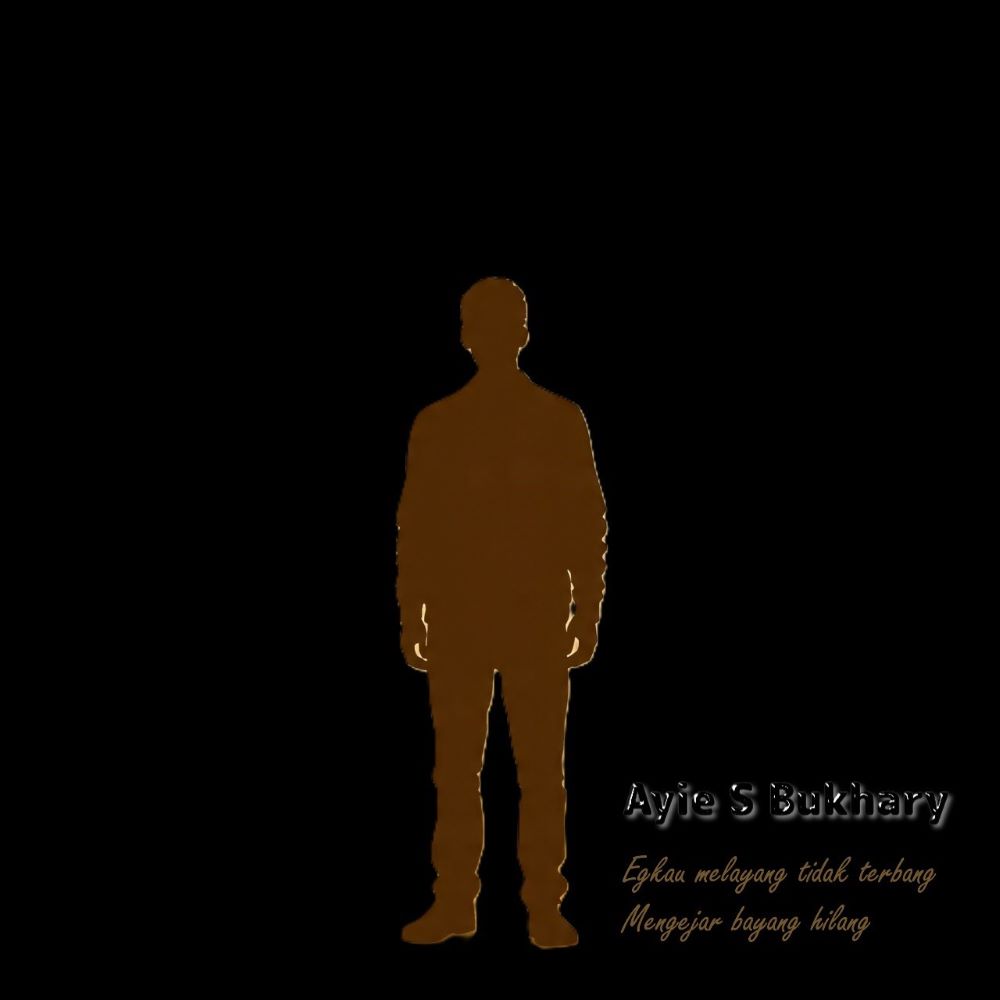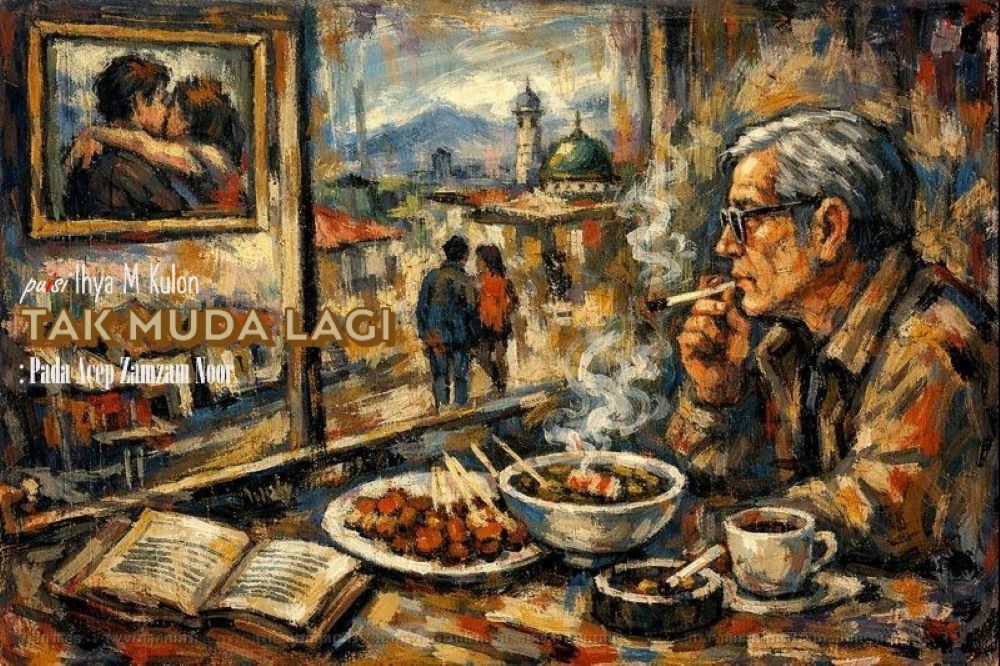Memoar Broken Strings: Kepingan Masa Muda yang Patah karya Aurelie Moeremans tidak hanya menghadirkan kisah traumatik tentang child grooming dan kekerasan seksual, tetapi juga membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat—secara sadar atau tidak—membangun mitos tentang anak perempuan yang “dewasa sebelum waktunya”. Dalam buku ini, Aurelie kerap digambarkan sebagai anak yang terlihat matang: postur tubuhnya tinggi, cara bicaranya tenang, ia mandiri, cerdas, dan profesional sejak usia sangat muda. Gambaran inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat orang-orang di sekitarnya, termasuk sang ibu, merasa cukup aman melepasnya bekerja, syuting, dan bergaul dengan lingkungan orang dewasa.
Sudut pandang ini penting untuk ditelaah, bukan untuk menyalahkan keluarga atau korban, melainkan untuk memahami bagaimana konstruksi sosial tentang “kedewasaan” anak perempuan kerap menutupi fakta psikologis bahwa kematangan fisik dan kecerdasan intelektual tidak identik dengan kematangan emosional dan psikososial. Dalam konteks inilah Broken Strings bisa dibaca sebagai kritik tak langsung terhadap budaya yang memaksa anak perempuan tumbuh terlalu cepat.
Dewasa Secara Fisik Bukan Dewasa Secara Psikologis
Psikologi perkembangan secara konsisten menegaskan bahwa remaja berada dalam fase transisi yang kompleks. Menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap identity vs. role confusion, di mana individu masih mencari jati diri dan sangat rentan terhadap pengaruh eksternal (Erikson, 1968). Sementara itu, penelitian neuropsikologi menunjukkan bahwa perkembangan otak—khususnya prefrontal cortex yang berperan dalam pengambilan keputusan, pengendalian impuls, dan penilaian risiko—baru matang sepenuhnya di usia pertengahan 20-an (Steinberg, 2014).
Dalam konteks Aurelie, meskipun ia tampak dewasa secara fisik dan mampu bekerja secara profesional, ia tetap seorang anak berusia 15 tahun ketika relasi timpang dengan pria dewasa terjadi. Namun, masyarakat kerap gagal membedakan “mampu bekerja” dengan “mampu melindungi diri secara emosional dan seksual”. Ketika anak perempuan terlihat cerdas dan mandiri, mereka sering dianggap siap, padahal secara psikologis belum.
Mitos Anak Perempuan yang “Kuat” dan “Mandiri”
Feminisme telah lama mengkritik mitos tentang perempuan—terutama anak perempuan—yang dipaksa menjadi kuat sebelum waktunya. Simone de Beauvoir menyatakan bahwa perempuan tidak dilahirkan, melainkan dibentuk oleh konstruksi sosial (Beauvoir, 1949). Dalam kasus anak perempuan yang terlihat dewasa, konstruksi ini bekerja secara paradoks: mereka dipuji karena mandiri, tetapi sekaligus dibebani tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka pikul.
Aurelie dalam Broken Strings menunjukkan bagaimana kemandiriannya justru menjadi celah. Ia dipercaya, dilepas, dan dianggap mampu mengelola dirinya sendiri di dunia yang penuh relasi kuasa. Namun, kemandirian ini tidak disertai perlindungan struktural yang memadai. Feminisme melihat kondisi ini sebagai bentuk adultification—proses di mana anak perempuan diperlakukan seolah-olah lebih dewasa dari usia sebenarnya, sehingga kebutuhan perlindungan mereka diabaikan (Epstein et al., 2017).
Sheila Marcia dan Selebritis Dunia dalam Pola yang Berulang
Fenomena serupa pernah muncul dalam perbincangan publik terkait Sheila Marcia. Di usia yang sangat muda, ia sudah terjun ke dunia hiburan, hidup mandiri, dan bergaul dengan lingkungan dewasa. Banyak komentar publik saat itu menilai bahwa Sheila “terlalu cepat dewasa” dan “terlalu bebas”. Namun, jarang yang mengajukan pertanyaan lebih mendasar: siapa yang diuntungkan ketika anak perempuan dipaksa dewasa sebelum waktunya?
Dalam banyak kasus selebriti anak, tuntutan profesionalisme dan citra “kuat” justru menutupi kerentanan mereka sebagai remaja. Psikologi perkembangan menegaskan bahwa tekanan lingkungan dewasa pada anak dapat meningkatkan risiko eksploitasi, gangguan kecemasan, dan kesulitan membangun batas personal (APA, 2022).
Salah satu narasi paling berbahaya yang muncul dalam kasus grooming adalah dalih bahwa korban “lebih dewasa dari usianya”. Dalih ini sering digunakan untuk menormalisasi relasi anak dengan orang dewasa. Dalam Broken Strings, narasi ini hadir secara implisit—baik dari lingkungan sekitar maupun dari cara pelaku membingkai relasi mereka sebagai hubungan setara.
Padahal, feminisme dan psikologi sepakat bahwa kedewasaan mental tidak menghapus ketimpangan kuasa. Usia membawa serta kuasa simbolik, pengalaman, dan otoritas yang tidak dimiliki anak. Seperti ditegaskan oleh Craven, Brown, dan Gilchrist (2006), grooming justru bekerja dengan mengeksploitasi ilusi kesetaraan ini—membuat korban merasa “dipilih” karena dianggap dewasa.
Budaya Nusantara: Anak Perempuan dan Tuntutan Cepat Tumbuh
Dalam konteks budaya Nusantara, anak perempuan sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk cepat “jadi orang”. Di banyak daerah, anak perempuan diajarkan untuk membantu ekonomi keluarga, mengurus diri sendiri, dan bersikap sopan serta dewasa sejak dini. Nilai ini memang lahir dari konteks survival, tetapi dalam dunia modern, ia bisa berubah menjadi pedang bermata dua.
Budaya malu (isin, wirang, pamali) yang kuat juga membuat anak perempuan enggan mengungkapkan ketidaknyamanan, apalagi kekerasan seksual. Ketika mereka terlihat mandiri, masyarakat cenderung berasumsi bahwa mereka “baik-baik saja”. Dalam kajian budaya, ini menunjukkan bagaimana nilai kolektif dapat menekan ekspresi kerentanan individu, terutama perempuan (Geertz, 1973).
Peristiwa Lain: Pola Global yang Sama
Fenomena “dewasa sebelum waktunya” bukan hanya terjadi di Indonesia. Kasus Britney Spears di industri hiburan Amerika, misalnya, menunjukkan bagaimana anak perempuan yang tampil dewasa secara visual dan profesional tetap mengalami kontrol ekstrem dan eksploitasi (Abidin, 2021). Begitu pula dengan kisah Millie Bobby Brown yang secara terbuka berbicara tentang pelecehan verbal dan grooming sejak usia belia.
Pola ini konsisten: anak perempuan dipuji karena dewasa, lalu dihukum ketika mereka terluka.
Dengan sudut pandang ini, Broken Strings dapat dibaca bukan hanya sebagai memoar trauma personal, tetapi sebagai cermin sosial tentang kegagalan kolektif dalam melindungi anak perempuan yang tampak “kuat”. Buku ini mengingatkan bahwa kemandirian bukan berarti kebal, dan kecerdasan bukan berarti siap menghadapi manipulasi emosional orang dewasa.
Ketika Aurelie menulis tentang jarak dengan orang tua yang semakin melebar, kita melihat bagaimana niat baik tanpa pemahaman psikologis justru dapat memperdalam isolasi. Ini bukan kesalahan individu semata, melainkan akibat dari mitos sosial tentang kedewasaan.
Mitos anak perempuan yang “dewasa sebelum waktunya” adalah narasi berbahaya yang perlu dibongkar. Broken Strings memberi kita kesempatan untuk melihat bahwa di balik postur tubuh tinggi, kecerdasan, dan kemandirian, tetap ada anak yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan ruang aman untuk tumbuh.
Membaca buku ini dari sudut pandang psikologi perkembangan, feminisme, dan budaya Nusantara membantu kita memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi karena pelaku, tetapi juga karena sistem nilai yang gagal mengenali kerentanan. Barangkali, pelajaran terpenting dari Broken Strings adalah ini: anak perempuan tidak seharusnya dipaksa dewasa hanya agar dunia merasa nyaman.
Referensi:
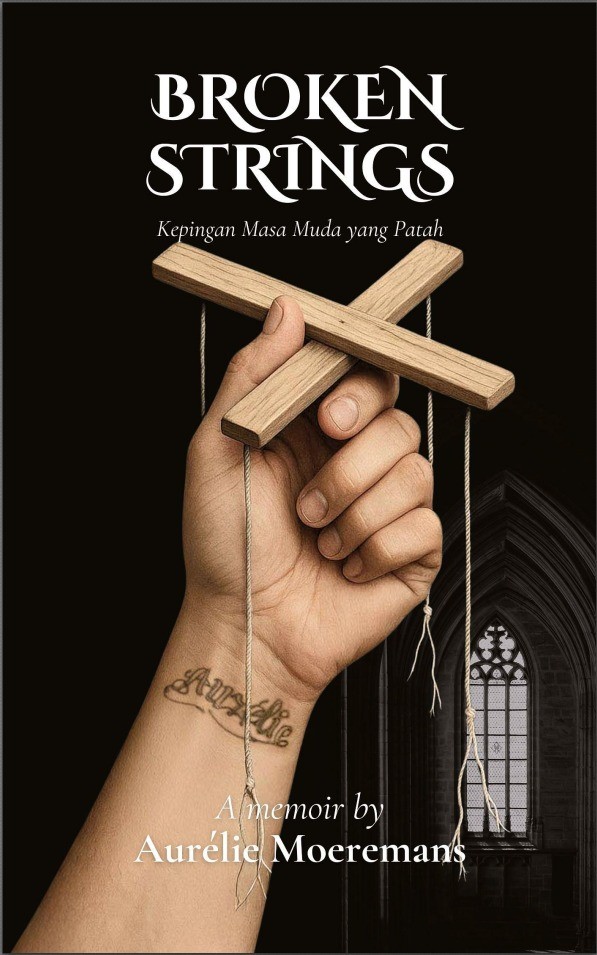
American Psychiatric Association. (2022). DSM-5-TR.
Beauvoir, S. de. (1949). The Second Sex.
Craven, S., Brown, S., & Gilchrist, E. (2006). Sexual grooming of children. Journal of Sexual Aggression.
Epstein, R. et al. (2017). Girlhood interrupted: The erasure of Black girls’ childhood. Georgetown Law Center.
Erikson, E. (1968). Identity: Youth and crisis.
Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures.
Steinberg, L. (2014). Age of Opportunity.