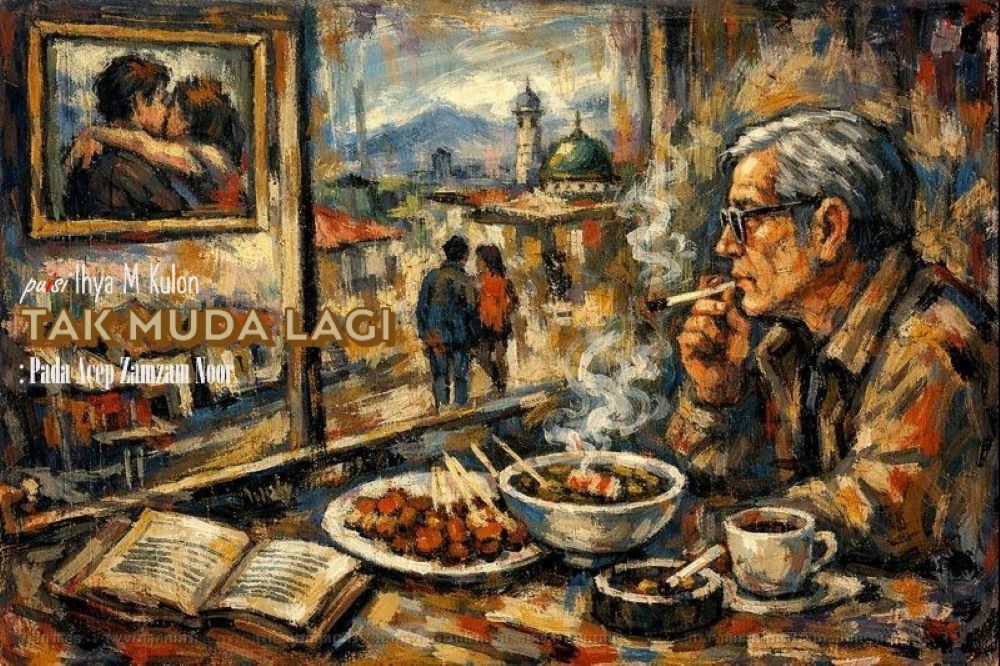Semalam kacau sekali. Pada jam-jam ketika ketakutan memeluk langit, aku melihat Subhan—bukan manusia semata, tetapi simpul hujan yang berusaha belajar menyanyi. Ia melilitkan lengannya pada pinggangku untuk beberapa momen, seolah memegang peta yang tak ingin ia baca. Orang-orang memandangi seperti burung-burung yang tahu rahasia musim; mereka mengerti maksudnya, atau pura-pura mengerti. Di sudut, sekolompok orang menari. Orang itu bukan nama, melainkan bayangan-tabuhan, tubuh-tubuh yang bergerak seperti kata-kata yang sudah usang, diiringi suara sapuan lidi yang mencumbu tanah. Lidi itu adalah jamur kecil yang mengetuk-ngetuk memori dengan ritme aneh. Ketika aku terbangun, aku membawa sisa-sisa tarian dalam kantong ingatan. Sulit melupakannya. Ada rasa yang tertinggal seperti selimut basah; enggan membangun realitas yang sesungguhnya, karena realitas tampak seperti rumah yang bocor.
Aku berusaha jujur pada diriku sendiri, namun kejujuran itu berbahasa asing dan memakai sepatu palsu. Keberanian menghilang dalam cangkang telur yang kukira aman. Aku terseok-seok dalam kebodohan yang enggan kupanggil namanya, karena menyebutnya mungkin berarti memberi ruang baginya tumbuh. Bukan sikap seorang pemberani memang; aku menjadi pengecut, benda tumpul yang menerima takdir seperti surat tanpa alamat, membiarkan malam demi malam membungkus tubuhku dengan kertas yang berbau debu. Di mana aku sekarang? Di peta yang dicetak terbalik. Hanya seorang penipu yang tersiksa, menjual ilusi kepada cermin-cermin, mencoba menyamarkan retak dengan pita perekat. Tak mampu menemukan dirinya, karena diri itu sembunyi di antara rak-rak cumi yang menulis puisi tentang laut yang lupa cara bernapas.
Seekor ular menyelusup masuk, namun bukan ular biasa: ia adalah pita film dari mimpi-mimpi usang. Ia melingkar di ambang pintu, menulis namaku dengan lidah yang seperti pena. Aku membiarkannya, bukan karena aku pemberani, melainkan karena aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya terhadap bayanganku. Aku tak punya alasan untuk membunuh atau mengusirnya; di rumah memang penuh tikus—tikus kecil dengan topi dan kalender, mereka telah merobek halaman-halaman perencanaan dan mencuri kata-kata dari kamus. Kawanan itu sudah merusak banyak hal: jendela lupa bagaimana membuka diri, kursi kehilangan cerita, dan panci mulai menulis surat panjang kepada kabut. Namun rasa bersalah menyengat seperti rempah; aku merasa bersalah pada Subhan, meski mungkin Subhan sama sekali tak memikirkan aku. Ia mungkin hanya awan yang lupa jalannya.
Aku seorang pengecut, tapi pengecut yang duduk mengamati dirinya sendiri seperti pertunjukan boneka. Apa yang kini harus kulakukan? Panduan hilang; orientasi intelektual dan naluri berselisih seperti kembar yang tidak akur. Aku menghancurkan diriku sendiri dengan ego—ego yang merupakan koleksi cermin kecil yang dipasang di dada, masing-masing memantulkan versi yang salah. Ego yang mana? Mungkin yang berkata pada pagi hari bahwa aku cukup, atau yang pada malam berbisik bahwa aku terlambat. Aku telah berusaha mengikis segala sesuatu seperti orang yang mengikis karang dengan sendok; lambat, sia-sia, tetapi penuh harap. Memohon ampun kepada sang pencipta terasa seperti mengirim sebuah poskad kepada langit; aku menulis maaf dengan tinta yang segera larut. Atau memang aku yang payah—sebuah kalimat sederhana yang terdengar seperti penutup dalam drama yang tak sempat pentas.
Di pagi berikutnya, dunia tetap memegang rahasianya. Subhan tidak menghilang, ia berubah menjadi pintu yang menganga di dinding: pintu yang hanya bisa dibuka dengan menyanyi lagu yang belum kuketahui nadanya. Ular menaruh gulungan film di atas meja, membiarkan tikus-tikus membaca adegan demi adegan hingga mereka menangis, bukan karena sedih, tetapi karena mengerti akhir cerita. Aku melihat pantulan diriku di cermin yang kini berpakaian ulang; ia tersenyum seperti orang yang baru menemukan kunci. Entah, mungkin keberanian adalah benda sederhana yang menunggu di dalam kantong jaket yang lama tak dipakai, atau mungkin itu hanya bayangan yang menahan napas, menunggu seseorang memintanya turun dari tiang lampu. Tetapi untuk pertama kali setelah malam itu, aku ingin membuka pintu—bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memanggil pulang bagian-bagian diriku yang hilang. Dan ketika aku menyanyikan nada yang rusak, pintu sedikit bergeser, cukup untuk mengizinkan cahaya menumpahkan seteguk pada lantai yang berdebu.