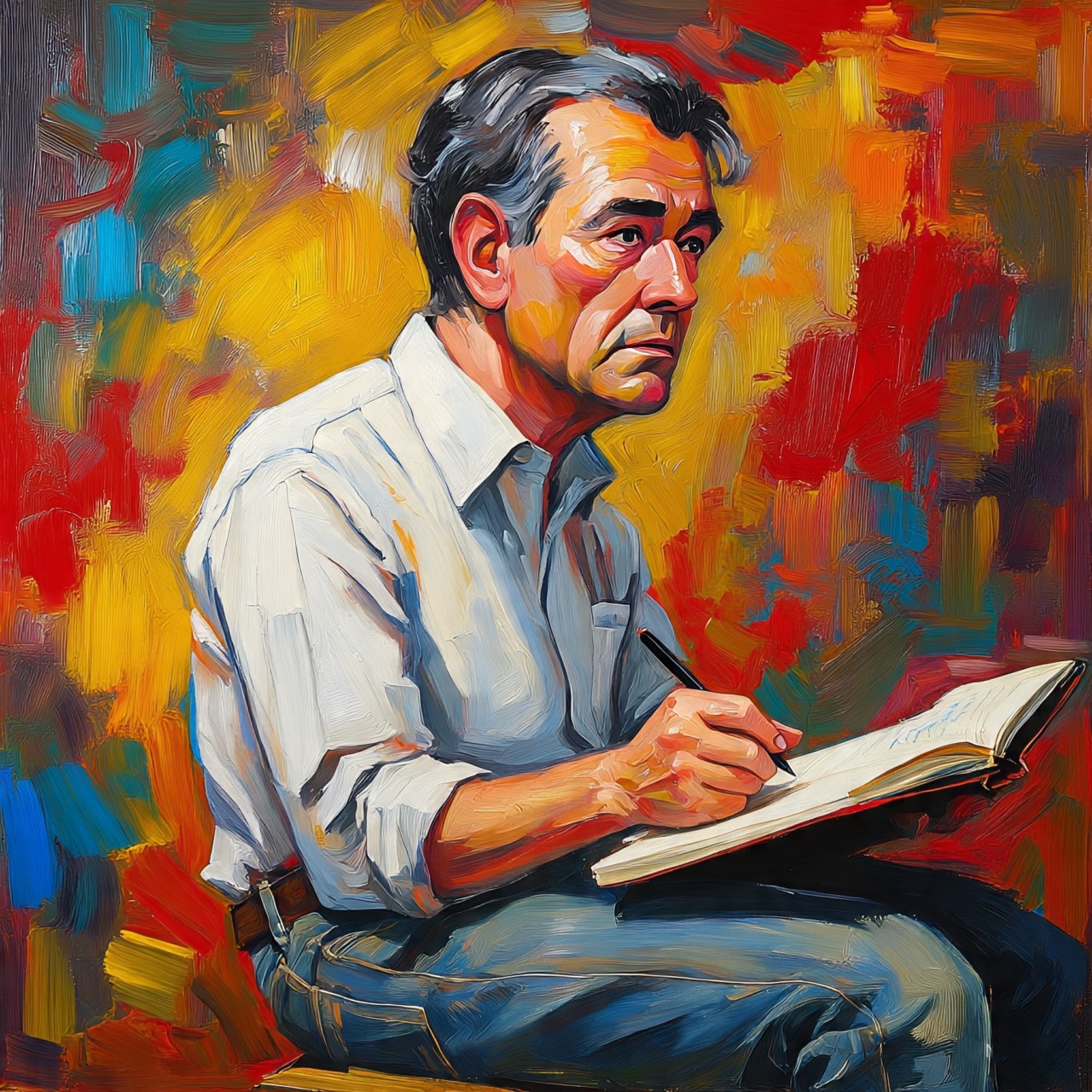Dalam kehidupan profesional, sering kali kita menemui stigma dan generalisasi yang tidak adil. Sebagai seorang jurnalis, saya pun tak lepas dari situasi semacam ini. Ada kalanya saya merasa dipukul rata hanya karena profesi yang saya jalani. Padahal, seperti profesi lainnya, dunia jurnalisme terdiri dari individu-individu yang berbeda latar belakang, karakter, nilai, dan pendekatannya masing-masing.
Sebagai misal, ada yang menganggap semua jurnalis itu mata duitan, mencari sensasi, bahkan tak jarang dituding menjual berita demi klik dan popularitas. Ada pula yang menganggap media hanya sibuk memanipulasi opini, menyebar hoaks, atau berpihak pada kepentingan tertentu. Tuduhan-tuduhan seperti itu, walau tak sepenuhnya keliru jika merujuk pada segelintir kasus, tetap saja tidak adil jika dilabelkan secara menyeluruh kepada seluruh insan pers.
Saya pribadi, dan saya yakin banyak rekan jurnalis lain, bekerja dengan integritas dan niat mulia: untuk menyampaikan informasi yang faktual, memberi suara kepada yang tak bersuara, serta berjuang agar publik tetap memiliki akses terhadap kebenaran. Tapi perjuangan itu kadang terasa sia-sia saat sebagian masyarakat, bahkan kolega dari profesi lain, menyamaratakan kita dengan segelintir oknum yang memang menyimpang dari etika jurnalistik.
Pernah satu waktu, saya mengikuti kegiatan peliputan yang melibatkan beberapa instansi pemerintah. Di sela-sela kegiatan, saya mendengar celetukan, “Wah, wartawan datang pasti minta amplop.” Saya diam, menahan gejolak emosi. Tidak semua wartawan seperti itu. Tapi dalam benak sebagian orang, label itu sudah melekat kuat. Sakit? Tentu. Tapi bukan karena harga diri saya direndahkan, melainkan karena profesi yang saya cintai dan perjuangkan dengan susah payah dianggap remeh.
Stigma ini muncul dari generalisasi. Hanya karena seseorang mengenal satu-dua oknum jurnalis yang tidak etis, lantas semua jurnalis dianggap sama. Hanya karena satu-dua media dianggap partisan atau tidak objektif, maka semua media disebut corong penguasa atau alat kepentingan bisnis. Padahal, seperti halnya profesi lain — dokter, guru, pengacara, hingga aparat — setiap profesi selalu memiliki oknum. Tapi tidak pernah kita dengar orang menyamaratakan semua dokter sebagai malpraktik, atau semua guru sebagai pemalas. Kenapa jurnalis kerap jadi kambing hitam?
Hal yang tak kalah menyedihkan adalah ketika perbandingan itu muncul dari sesama jurnalis. Seolah terjadi kompetisi diam-diam, di mana keberhasilan satu pihak dijadikan standar, lalu yang lain dianggap kurang profesional jika tidak sejalan. Ini menunjukkan bahwa tekanan untuk ‘disarimbagkeun’ tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam tubuh profesi itu sendiri. Padahal, keberagaman gaya peliputan, pendekatan, bahkan pilihan isu, semestinya menjadi kekayaan dalam dunia jurnalistik, bukan alasan untuk saling merendahkan.
Saya percaya, setiap jurnalis memiliki jalan perjuangannya masing-masing. Ada yang fokus pada liputan investigasi, ada yang berkutat pada isu kemanusiaan, ada pula yang bekerja di media lokal dan berusaha menyuarakan problem komunitasnya sendiri. Tidak semua jurnalis harus tampil di televisi nasional atau menulis headline besar. Tidak semua media harus viral atau trending. Ada jurnalis yang memilih jalan sunyi tapi tetap berdampak bagi lingkungan sekitarnya.
Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua — baik masyarakat umum maupun rekan sejawat — untuk lebih arif dalam memandang profesi ini. Jangan mudah menghakimi atau menyamaratakan. Jika ada kritik terhadap media atau jurnalis, sampaikan dengan bijak dan spesifik. Bedakan antara kritik terhadap individu dengan tuduhan terhadap profesi secara keseluruhan.
Kita pun sebagai jurnalis harus berani mawas diri. Jangan sampai kemarahan terhadap stigma malah menutupi kenyataan bahwa memang ada problem internal yang harus dibenahi. Etika jurnalistik harus tetap jadi pijakan utama. Kita harus saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menjaga marwah profesi ini. Bila kita ingin dihormati, maka kita pun harus menunjukkan sikap yang terhormat.
Akhirnya, saya ingin menegaskan: jurnalis juga manusia. Kami bukan malaikat, tapi bukan pula setan seperti yang kadang digambarkan sebagian orang. Kami bekerja di lapangan, berhadapan dengan berbagai dinamika, tekanan, bahkan ancaman. Yang kami butuhkan bukan pujian berlebihan, tapi penghargaan yang proporsional. Hargai kerja kami sebagaimana kami menghargai hak publik untuk tahu.
Jadi, jangan samakan kami hanya karena kami sama-sama disebut jurnalis. Lihatlah kami sebagai individu yang punya niat, perjuangan, dan prinsip yang tidak bisa digeneralisasi.***