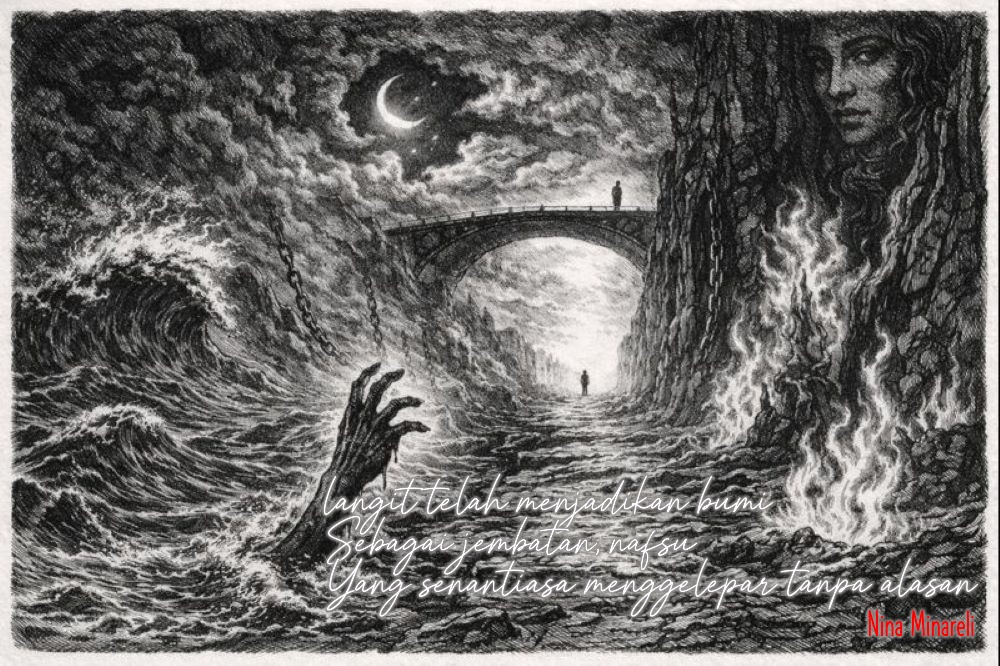Gea, melihatku tersenyum dengan mata sebening perigi, ingatanku jadi kembali ke masa lalu. Memandangmu, teringatku pada Eriza yang pernah kusakiti beberapa tahun yang lalu, 25 Januari tepatnya. Aku menghancurkan perasaanya. Angan-angan dan mimpi yang sepanjang waktu ia genggam musnah oleh sebuah ucapan perpisahan yang kulantunkan.
Ibuku tidak menyukainya. Menurutnya ia perempuan nakal yang hampir tiap hari mengunjungi rumahku, sedang aku tak ada. “Perempuan tak semestinya setiap hari datang ke rumah laki-laki,” ucap ibuku suatu ketika. Padahal menurutku ia baik. Cantik. Alis dan jentik bulu matanya seperti lengkung pelangi di fim-film kartun.
Sepasang matanya bening purnama bagai air perigi, seperti sorot matanya. Rambutnya bergelombang seperti dedaun padi yang ditiup angin pancaroba. Tangan-tangannya berbulu lembut. Setiap kali aku menggenggamnya, alur perasaanku salalu ingin berjalan menuruti kata hati. Aku menyentuhnya, lewat tanganku, lewat kata-kata yang aku sendiri tidak pernah terucapkan sebelumnya.
Tetiba aku menjadi cengeng. Air mataku akan semakin menderas jika terus mengingatnya. Kini entah di mana ia menginjakan kaki? Yang aku tahu ia telah membuatku merasa kehilangan. Aku benar-benar kehilangan arah seperti seorang pendaki di dalam hutan belantara. Begitu lama aku mencarinya. Bahkan waktupun tak sanggup menuliskan rentangan itu.
Maafkan aku Eriza! Ya, di itu waktu, aku hanya mendengar dari sepihak saja. Ibuku. Ya, hanya dari ibuku semata. Tanpa tahu pasti kedatanganmu di luar adaku. Sampai akhirnya aku tahu bahwa kedatanganmu ke rumah di luar adaku, tiada lain kau sedang punya masalah yang cukup berat. Kedua orang tuamu yang saban harinya bertengkar. Sayangnya, aku baru tahu itu paska setahun kita berpisah. Hal itu pun aku tahu bukan langsung dari mulutmu. Melainkan dari sahabatmu, Sita.
Kini, seolah semuanya sudah melewati batas akhir dari suatu babak kehidupan. Dan hari ini engkau seolah kembali hadir melalui jiwa yang lain. Dengan tubuh yang lain, yaitu kau, Gea. Alis dan bulu mata yang lembut itu ada di wajahmu, juga bibir dan pipi lembutnya. Sekalipun kau memberikan rona merah di wajahmu sebagai tanda tak setuju saat aku mengatakan itu.
“Aku. Ya, aku. Bukan orang lain. Dan bukan seseorang yang pernah kau temui,” katamu saat kita pertama kali bermalam mingguan. Kita duduk di sebuah taman kota, lantas orang-orang memandangi kita sebagai sepasang kekasih yang sedikit lusuh. Kau terlalu muda, Gea. Sedangkan usiaku jauh di atasmu. Dengan sandal jepit yang talinya hampir putus aku menjumpaimu.
Tangan-tangan lembutmu sesekali menyibakan rambutku yang menutupi wajah setelah tertiup angin. Itu yang membuat orang-orang beranggapan aneh, barang kali. “Ah, sepengetahuanku kau seusia dengan Eriza.” Batinku di itu waktu. Ya, usiamu selisih tiga bulan dengan Eriza. Kau terlahir bulan Juni, sedang Eriza terlahir pada pertengahan Maret. Aku pernah memberi kado sebuah cincin putih padanya. Cicin yang kubuat sendiri dari stainless. Akan tetapi, aku takut kau cemburu mendengar ceritanya. Aku tak mau mengingatnya lagi.
**
Awal pertemuan kita adalah sebuah ketidaksengajaan. Orang-orang sibuk mengatur dirinya sendiri. Di tengah suasana kampus. Aku menemukanmu sebagai orang asing yang mengunjungiku. Bersama teman-temanmu kau kubutuhkan. Bukan apa-apa, sudah menjadi kebiasaanmu, bukan, dimintai untuk mengisi sebuah acara hiburan? Begitu orang-orang awam berkata.
Disebuah pesta pernikahan, kau biasa berada sebagai seseorang yang dinantikan atau pada acara-acara lain seperti opening ceremonial maupun festival dan resepsi pernikahan. Saat itu aku ingin bekerja sama denganmu. Pada sebuah pertunjukan drama tradisi, aku membutuhkan para penari. Sebagai pembuka, penjeda dan penutup. Kau akan kubutuhkan bersama beberapa orang temanmu untuk menari. Kau pun datang bersama sahabat-sahabatmu.
Kau tahu, Gea, saat pertama aku melihatmu aku pernah mengatakan pada seseorang kau mirip dengan Eriza. Lantas ia mengatakan aku akan jatuh cinta padamu. Tapi aku mengelak. Aku katakan, aku tidak mau mengulang kejadian beberapa tahun silam. Di samping itu, belum lama ini aku menjalin sebuah ikatan batin dengan seseorang untuk menjadi sepasang kekasih.
Di sisi lain, aku hanya ingin mengenalmu sebagai seseorang yang pernah membantuku dalam sebuah pertunjukan drama tradisi. Aku sendiri tak tahu akan mendapat upah atau tidak dari pekerjaan itu. Aku tak peduli. Persahabatanku dengan Dandy memberiku semangat untuk mengerjakannya. Ia memintaku membantunya menyelesaikan proses ini.
“Terima kasih, saya ucapkan pada teman-teman yang bersedia membantu pertunjukan ini. Perkenalkan, saya Male” kataku menyambutmu yang duduk manis di antaara kawan-kawan manjamu. Tapi kau malah memperhatikan wajahku, bukan kata-kataku. Aku melihatnya.
“Nah. Sekarang kenalkan satu-persatu,” Dandy berkata padamu. Lantas kau beserta kawan-kawanmu pun memperkenalkan diri. Aku juga merasa heran mengapa hanya engkau yang mudah aku ingat namanya. Hanya tiga hurup barangkali. G.E.A. Sekalipun itu nama panggilanmu saja, sedang namamu yang sesungguhnya cukup panjang untuk kucatat.
**
Gea, pandai sekali kau menari. Liuk tubuhmu gemulai seperti ikan sisili di sebuah aquarium. Sedang senyum di bibirmu tak pernah terputus saat kau meliuk-liukkan tubuh itu. Matamu lirih, seperti yang pernah kukatakan. Bulu matamu, bibirmu, dan pinggulmu yang tak kuasa kuperbandingkan dengan sesuatu ataupun seseorang.
Lantas ketika malam tiba aku mengingatmu. Aku merindumu. Pukul 23.15 aku menelponmu. Tapi yang mengangkat adalah sahabatmu, Maya. Tiba-tiba rasa malu itu hinggap diwajahku. Padahal aku sedang tak disaksikan oleh siapa-siapa.
“Gea sedang di kamar mandi,” jawab Maya dengan sedikit menggoda; “Nanti dia nelepon balik,” sambung Maya. Seterusnya aku menutup kembali teleponku. Detik yang berjalan seakan berat melangkah.
Tapi pada akhirnya kau juga tahu, tidak ada yang kukatakan saat menerima teleponmu. Aku hanya menanyakan kepastian berapa orang jumlah kawan-kawanmu. Padahal kita telah tahu sebelumnya. Aneh. Semua yang ingin aku katakan berlarian entah ke mana? Mungkin ditelan jelaga, atau sama sekali tak terlihat sebab mereka bersembunyi di balik awan kelabu malam itu.
Hari pun beranjak, mengalir seperti aliran darah kita yang semakin cepat. Hingga pada suatu saat di penghujung latihan, di sebuah auditorium kita sempat berduaan dan hanya diam saja. Lalu kau berjalan ke sebuah balkon dan menatap jauh ke depan. Aku rasa pandanganmu terhalang dedaunan yang rindang menutupi wajah kolam renang. Atau itu hanya isyaratmu untuk mengajakku berduaan di sana?
Dengan gontai dan tanpa berdosa meninggalkan Dandy dan teman-teman lain yang sedang berproses di atas panggung, aku menghampirimu. Selama beberapa hari kita bertemu, baru kali ini aku bisa bersamamu. Hanya bersamamu. “Kau nampak tidak bahagia hari ini?” entah dari mana aku mendapatkan kalimat itu. Rasanya aku pantas mengucapkannya untukmu.
Kau tersenyum dibuat-buat. Tapi aku tetap tidak tahu yang ada dalam hatimu. Wajahmu melukiskan dua rasa yang berbeda, ada kesedihan yang tiba-tiba muncul lewat raut yang begitu mengukir rona wajahmu. Tapi kau diam saja. Senyum itu kembali dilemparkan ke depan, seolah kau kembali menginginkanku pada Eriza; menangkapnya kembali semua bayang kenang yang sudah terjadi.
“Gea, Tak sepantasnya wajah semanis madu itu berselimut awan kelabu,” kataku lagi seolah sedang dituntun untuk berkata oleh Kahlil Gibran. “Sedang patah hati…” jawabmu seperti bermain sandiwara. Sebelum menjawab dengan kata-kata, aku menanggapinya dengan sebuah senyuman yang hampir menjadi tawa.
“Hanya laki-laki bodoh dan berhati drakula yang membuat perempuan sepertimu menjadi luka. Andai saja aku punya sayap dan kekuatan untuk melindungimu, takkan kuperkenalkan sedikitpun padamu sesuatu yang bernama kelu itu.” Dengan kata-kata itu nyatanya aku bisa menangkap senyummu yang telah berlari di antara gedung dan pepohonan.
Kini bibirmu yang mendelima itu kembali tersenyum, ke arahku. Wajahmu seolah ingin menadah sinar mataku. Beberapa saat kau hanya terdiam dan menatapku. Senyum itu seolah ingin berubah jadi kata. Namun entah apa yang membuatnya seperti terkatung-katung. Bibirmu seperti tak mampu mengernyitkan raut yang lain.
“Ada yang salah dengan ucapanku?” tanyaku. Kau hanya menggelengkan kepala beberapa senti tanpa menggoyahkan garis tatapmu ke arah mataku. “Andai saja kau kekasihku, akan kupeluk erat kau seperti sinar matahari yang memeluk jemuran pakaian hingga mengering,” tuturmu seperti baru saja terjangkit virus metafora yang baru saja aku sebarkan.
Aku hanya tertatih dan menatapmu dalam lelap pulas. Kaupun membalasnya. Mendekat. Lalu kita pun berpelukan seperti gerhana. Ah, andai saja di itu waktu kita berpelukan di panggung realita dengan sesungguh hati, seperti para balon dewan, tentu kini kita sudah jadi pasangan resmi yang diusung ke pelaminan melati.
Sayangnya, aku hanya ingin mengenalmu sebagai seseorang yang pernah membantuku dalam sebuah pertunjukan drama tradisi. Di sisi lain, belum lama ini aku menjalin sebuah ikatan batin dengan seseorang untuk menjadi sepasang kekasih. Namun hari-hari yang membawaku ke banyak alur perjalanan, mengapa bayang dan wajahmu kian meraja dalam ingatan di sepi hariku; Gea, engkau di mana? []
Bandung, Mei 2018