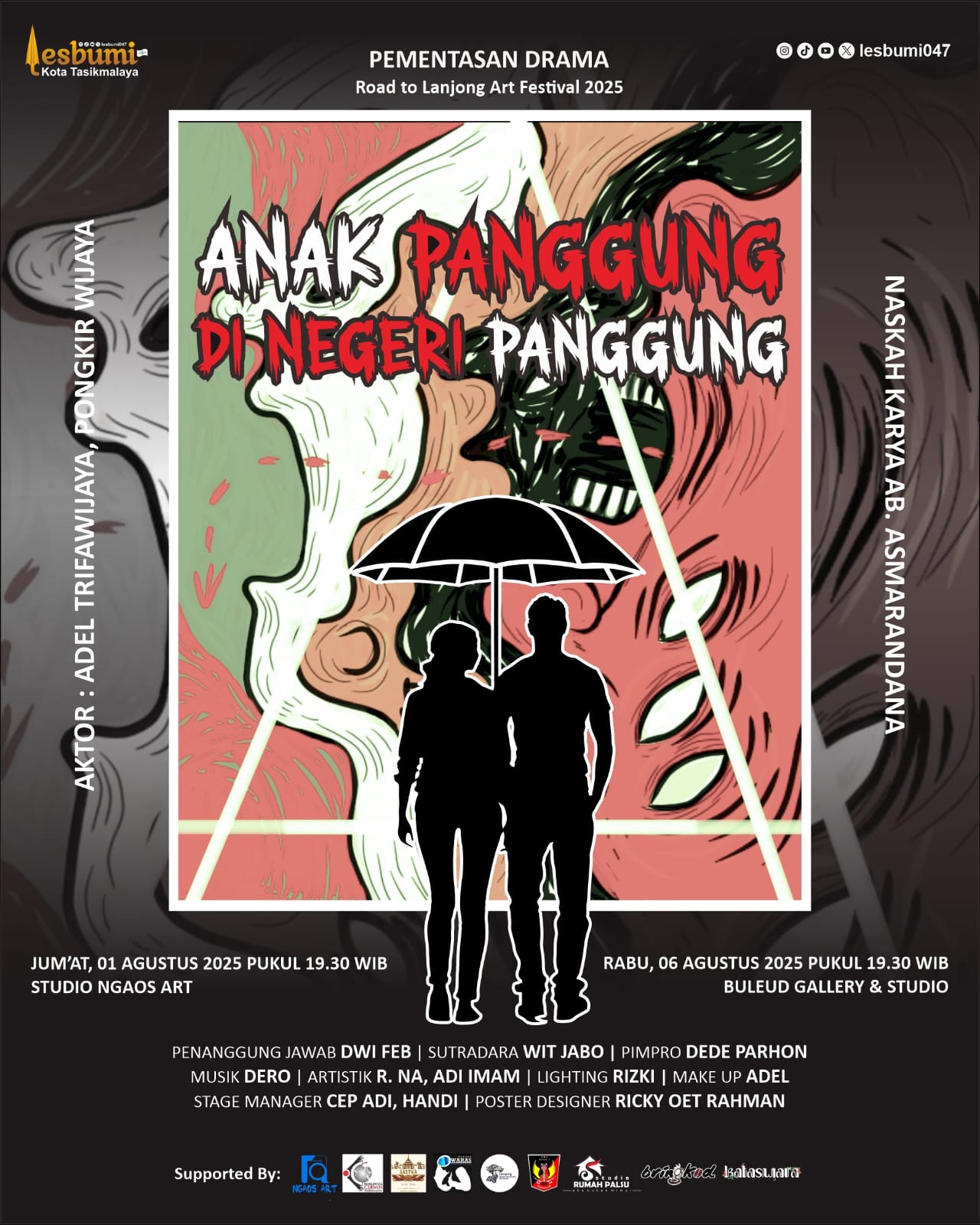Pada tanggal 13 Januari 2025, tepatnya pukul 17.55 WIB, sebuah undangan datang via WA tanpa banyak pengantar. Rika Rostika Johara dari NgaosArt mengabarkan akan ada pementasan lakon drama berjudul ACTING DI HADAPAN TUHAN, karya sekaligus sutradara Ab. Asmarandana, yang dipentaskan di Studio NgaosArt, Perum Amanda Residence, Kota Tasikmalaya pada tanggal 17 Januari 2026 pukul 19.30 WIB-Selesai. Pementasan itu bertepatan dengan perayaan tujuh tahun berdirinya NgaosArt Foundation. Tidak ada janji tontonan yang nyaman, tidak pula isyarat perayaan yang meriah. Hanya sebuah ajakan untuk hadir, duduk, dan menyaksikan sesuatu yang barangkali tidak ingin ditatap terlalu lama oleh siapa pun yang masih menyimpan hasrat untuk merasa aman di dalam keyakinannya sendiri.
Usai pementasan berlangsung, seperti yang kerap terjadi, percakapan kecil tumbuh di antara para penonton. Amang S. Hidayat menanggapi bahwa silaturahmi sering kali lebih penting daripada pertunjukan itu sendiri. Irvan Mulyadie melihat ruang reflektif semacam ini sebagai sesuatu yang lama dirindukan publik. Dari penanggap lain pun hatir, tapi saya lupa apa yang mereka omongkan. kalau tidak salah ingat perihal aromanis, termasuk saya pribadi menanggapi, pembicaraan bergerak pada soal kedalaman teks dalam konteks festival besar berskala nasional—betapa disayangkan ketika alur lakon dengan keberanian seperti ACTING DI HADAPAN TUHAN justru jarang mendapat ruang.
Musabab dari itulah saya terdorong untuk mengupas kedalaman isi, teks, dan konteks naskah ini dalam satu sisi pandang saya sendiri, dengan upaya bersikap jujur, seolah turut melakukan acting di hadapan naskah yang sedang dibaca. Bukan berarti pula konsep garap dan akting para aktor di atas panggung jelek, tidak dan tak. Alasan mendasarnya itu pembacaan lakon teks naskah drama dengan alur seperti ini sering gagal paham dalam pemetaannya di napas jejak baca—tak seperti bau dupa sepanjang pementasan yang mudah diterka dari jenis dan merk apa dupanya itu:
Naskah ACTING DI HADAPAN TUHAN tidak lahir dari kebutuhan untuk bercerita, apalagi untuk menawarkan alur yang rapi. Ia lebih menyerupai sebuah ruang terbuka yang sengaja dibiarkan retak, agar kebiasaan sosial, pendidikan, politik, dan iman bocor tanpa bisa ditambal. Teater, dalam naskah ini, tidak bekerja sebagai representasi kehidupan, melainkan sebagai tindakan pembongkaran. Sehingga yang dipertontonkan bukan peristiwa, tetapi mekanisme: bagaimana manusia belajar tampil, bagaimana kepatuhan diproduksi, dan bagaimana kejujuran perlahan digeser oleh kelulusan administratif.
Sejak awal, naskah ini sudah menolak ilusi. Kotak Pandora berupa lemari pakaian yang terus dibuka-tutup menghadirkan seragam kerja, baju sekolah, busana ibadah, dan jas kekuasaan sebagai artefak kebiasaan, bukan identitas sejati. Panel-panel itu bukan sekadar properti, melainkan arsip hidup yang menyimpan bau keputusan-keputusan kecil yang terus diulang. Tubuh aktor berdiri di sekitarnya bukan sebagai karakter psikologis, melainkan sebagai saksi dari peran-peran yang pernah mereka kenakan. Di sini, teater tidak lagi meminta penonton percaya, tetapi mengajak mereka mencium.
Struktur dialog A, B, dan C sejak awal sudah menunjukkan bahwa naskah ini tidak sedang membangun relasi sebab-akibat. Ucapan-ucapan pendek, repetitif, kadang jenaka, kadang pahit, bekerja seperti denyut kesadaran kolektif. Acting tidak diposisikan sebagai kebohongan moral, melainkan sebagai kebutuhan bertahan hidup. Wajah rajin, wajah sedih, wajah religius, wajah sibuk—semuanya diperlihatkan sebagai topeng yang sah secara sosial. Bahkan kalimat “aku baik-baik saja” diperlakukan bukan sebagai dusta personal, melainkan sebagai mantra bersama yang menjaga sistem tetap stabil.
Masuknya penonton ke dalam struktur naskah mempertegas sikap postdramatik teks ini. Penonton tidak diberi jarak aman untuk mengamati, tetapi diseret menjadi bagian dari laku. Senyum, tatapan, dan kalimat yang diucapkan bersama menjadi bentuk kerja paksa yang halus. Menonton tidak lagi pasif; ia menjadi aktivitas reflektif yang melelahkan. Dalam titik ini, naskah secara sadar membongkar konvensi teater ilusionistik dan menggantinya dengan kehadiran telanjang, di mana rasa tidak nyaman justru menjadi medium utama.
Pilihan dramaturgis tersebut menempatkan ACTING DI HADAPAN TUHAN dalam garis teater postdramatik, tanpa harus kehilangan konteks lokalnya. Bahasa yang dipakai tidak diarahkan untuk membangun karakter, tetapi untuk memperlihatkan kerusakan sistemik. Adegan demi adegan bekerja seperti fragmen kesadaran: pendidikan sebagai mesin kelulusan, hukum sebagai lapak pasal, politik sebagai drama panjang dengan aktor yang berganti kostum, dan agama sebagai panggung terakhir tempat manusia berharap masih bisa tampil meyakinkan.
Tokoh Slobodon menjadi simpul penting dalam pembacaan ini. Ia bukan figur realis, melainkan personifikasi dari ingatan kolektif tentang negara, kekuasaan, dan patriarki yang bercampur trauma. Percakapannya dengan Tien dan Islodbodon tidak dimaksudkan untuk memenangkan argumen, melainkan untuk memperlihatkan betapa pendidikan, keluarga, dan ideologi saling menjebak dalam logika yang sama: takut kehilangan kendali. Sekolah dipersoalkan bukan karena ilmunya, melainkan karena kecenderungannya mematikan pertanyaan demi laporan. Di sini, kritik pendidikan tidak jatuh menjadi slogan, tetapi hadir sebagai pengalaman tubuh yang lelah.
Adegan kelas dengan murid-murid dan guru menjadi salah satu bagian paling telanjang dari naskah ini. Dialog yang berulang tentang naik kelas, akreditasi, dan laporan menyingkap kenyataan pahit: bahwa sistem tidak lagi takut pada kebodohan, melainkan pada kesadaran. Anak-anak tidak ditindas dengan kekerasan, tetapi dengan kelulusan otomatis. Mereka tidak dibungkam dengan larangan, melainkan dengan rasa aman palsu. Makan bergizi, grafik, dan layar presentasi menjadi simbol bagaimana kepatuhan bisa disuapkan sambil tersenyum.
Secara historis, naskah ini berdiri di persimpangan antara tradisi teater kritik sosial Indonesia dan kecenderungan teater eksperimental kontemporer. Ia memiliki keberanian satire politik yang pernah hidup dalam teater-teater perlawanan, tetapi menolak bentuk agitasi langsung. Alih-alih menyerang dari luar, ACTING DI HADAPAN TUHAN menggerogoti dari dalam, dengan memperlihatkan bahwa kita semua ikut melanggengkan sistem yang kita keluhkan.
Di titik inilah potensi resistensi dan salah-baca muncul. Naskah ini mudah dituduh nihilistik, kasar, bahkan anti-agama atau anti-sekolah. Padahal, yang diserang bukan iman, pendidikan, atau negara sebagai konsep, melainkan kebiasaan berpura-pura yang menempel padanya. Ketika doa disebut sebagai naskah dan sujud sebagai panggung, yang dipersoalkan adalah kejujuran manusia, bukan keyakinannya. Tuhan justru dihadirkan sebagai ruang yang tidak bisa dibohongi, tempat seluruh teknik tampil akhirnya gugur.
Bagian penutup, ketika seluruh aktor berdiri tanpa seragam dan tanpa properti, menjadi antitesis dari seluruh pertunjukan. Tidak ada klimaks, tidak ada penyelesaian, hanya keheningan yang canggung. Inilah momen paling manusiawi dari naskah tersebut. Saat tidak ada lagi peran yang harus dijalankan, pertanyaan yang tersisa menjadi sangat sederhana dan sangat berat: siapa kita ketika tidak sedang tampil.
ACTING DI HADAPAN TUHAN tidak menawarkan jalan keluar, tidak pula menjanjikan perubahan. Ia hanya mengajukan jeda: Jeda untuk berhenti sejenak dari kebiasaan tampil rapi. Jeda untuk menyadari bahwa mungkin selama ini kita tidak sepenuhnya hidup, melainkan sekadar lulus dari satu peran ke peran berikutnya. Dan barangkali, di zaman yang terlalu gemar memberi nilai dan tepuk tangan, sebuah naskah yang berani menutup diri tanpa aplaus justru sedang bekerja paling jujur.
Demikianlah pembacaan laku akting melajo saya dalam menelanjangi teks drama ACTING DI HADAPAN TUHAN selesai sudah tanpa klimaks lanjutan, sebab ibu guru beserta anak-anak tak ikut hadir menyaksikan, hingga tak ada frasa boleh diulang yang jadi penanda, betapa sulitnya untuk tidak bisa tidak naik kelas []