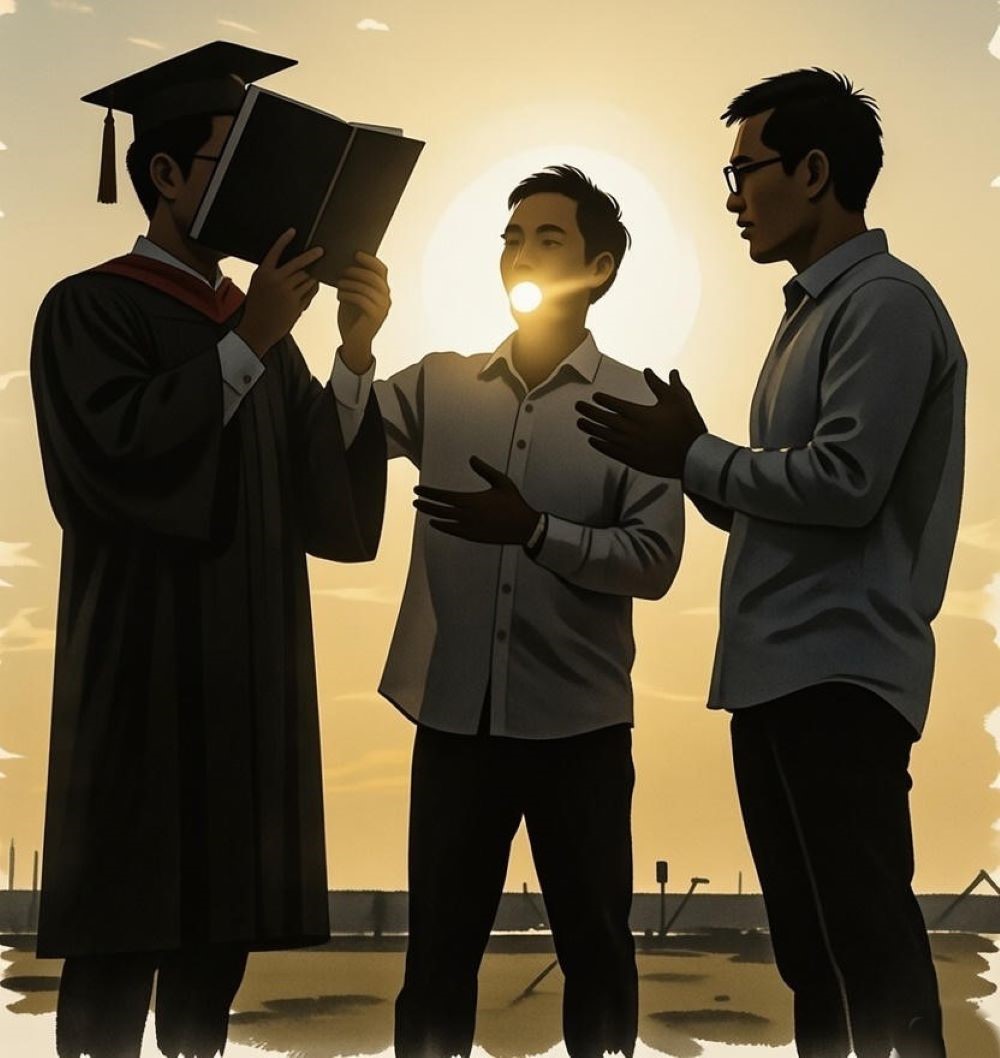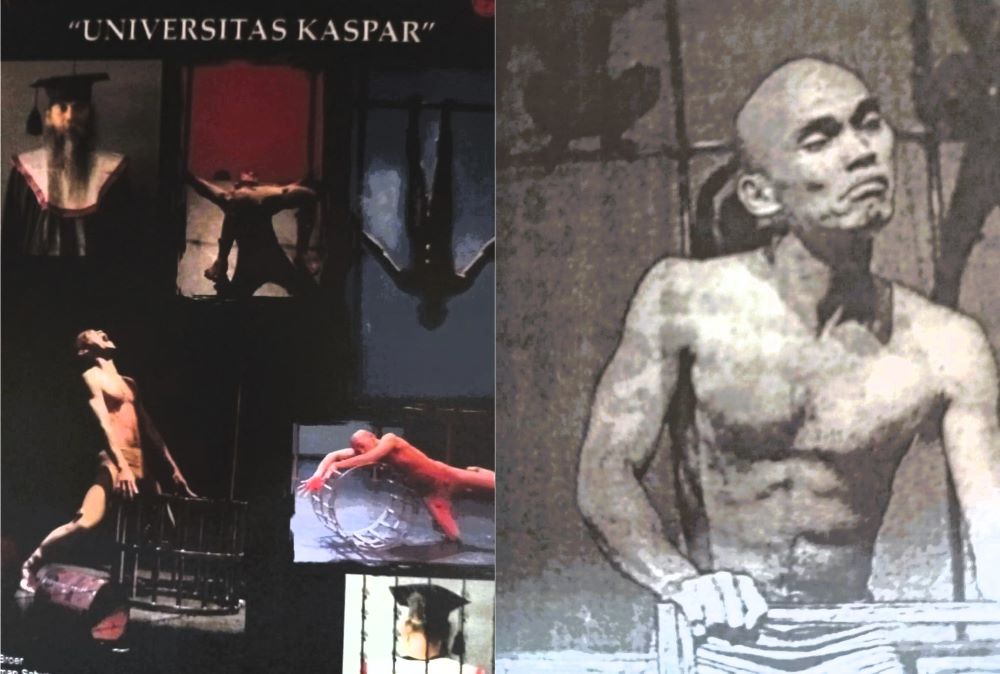Di negeri
yang berpeta hati
disebut Sumatera, kini
bumi mengerang seperti
ibu tua menahan sakit
agar anaknya tak panik,
terbalut putus asa,
diharap tenang.
Gunung batuk abu,
luap sungai, air deras
membawa rahasia hulu,
tanah retak menagih doa,
rumah-rumah berlutut
lebih rendah dari batas
kesabaran, pasrah.
Rakyat hidup prihatin,
bukan metafora, tapi realita
yang berderap lemah pelan,
mengantre di dapur umum,
menggigil di tenda plastik
yang berisik bila hujan
dan panas matahari
saat bertugas.
Anak-anak belajar mengeja kata “kehilangan” lebih dulu daripada “kemerdekaan”.
Ibu-ibu menanak nasi dengan air mata sebagai bumbu yang tak
tercantum di resep negara. Ayah-ayah menghitung hari bukan dengan kalender, tapi dengan logistik.
Namun di atas sana, di gedung ber-AC yang dinginnya lebih abadi dari empati, para pemimpin berdiri tegak dengan harga diri setinggi seribu menara.
“Kami mampu,” kata mereka,
dengan suara berat seperti dentum palu sidang.
“Kami menolak bantuan asing.”
Bukan karena bantuan itu beracun,
bukan pula karena niatnya busuk, melainkan karena satu kata
yang disetrika rapi:
kedaulatan.
Ah, kedaulatan.
Kata sakti yang sering dipakai seperti jas kebesaran di acara resmi,
namun lupa digantungkan saat hujan bencana turun tanpa undangan. Rakyat bertanya pelan, agar tak dianggap kurang ajar:
“Apakah kedaulatan
bisa mengganti selimut?”
“Apakah harga diri
bisa diminum bersama obat?”
“Apakah penolakan
bisa mengenyangkan balita?”
Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah masuk notula rapat. Terlalu sederhana daripada meja yang terlalu mahal.
NEGARA GAGAH DI CERMIN
Pemimpin kita gagah.
Gagah di podium,
gagah di spanduk,
gagah di pidato yang dipoles retorika, berkilau disorot lampu.
Ia berkata,
“Bangsa besar tidak mengemis!”
Padahal yang mengemis
bukan bangsa, melainkan perut anak-anak yang belum sempat belajar apa itu nasionalisme.
Ia berkata,
“Kami berdiri di kaki sendiri!”
Padahal kaki itu masih berbalut sepatu impor, melangkah di karpet asing, dan berfoto dengan
kamera produk luar negeri.
Ironi ini lucu,
bila tak terlalu menyakitkan.
Negara seperti lelaki tua yang
menolak tongkat demi terlihat
perkasa,.lalu jatuh dan berkata
pada tanah:
“Ini latihan.”
Padahal,
urusan sakit
di tepi jurang
kematian
….
MARTABAT DAN KEMANUSIAAN
Mari bicaca apa adanya,
tanpa pengeras suara.
Menolak bantuan asing
Tuhan bilang “bukan dosa.”
Menerima bukan cacat2 aib,
yang menjadi soal adalah
waktu dan kondisi,
tanpa kompromi.
Saat rakyat terluka,
apakah martabat negara
lebih penting daripada nyawa manusia? Bukankah kemerdekaan
lahir dari solidaritas? Bukankah sejarah mencatat bahwa bangsa ini pernah menerima uluran tangan
tanpa kehilangan jati diri?
Kemanusiaan
tidak punya paspor.
Air mata tidak perlu visa.
Dan empati, tidak pernah
mengancam kedaulatan.
Yang mengancam justru keangkuhan menyamar
selaku nasionalisme.
DIALOG DUA SISI
Rakyat:
“Pak, hujan deras, tenda bocor.”
Pemimpin:
“Sabar, ini ujian nasional.”
Rakyat:
“Pak, obat menipis.”
Pemimpin:
“Kita mandiri, jangan bergantung.”
Rakyat:
“Pak, bantuan dari luar negeri datang.”
Pemimpin (tersenyum bijak):
“Kita tolak, demi harga diri.”
Harga diri mengangguk puas,
sementara perut rakyat
berbunyi lebih keras
dari pidato kenegaraan.
NEGERI
BELAJAR
DEWASA
Wahai negeri,
kedewasaan tak berarti
menolak semua pertolongan.
Kedewasaan adalah tahu
kapan berkata tidak
dan kapan berkata
terima kasih.
Harga diri sejati
bukan terletak pada
penolakan, melainkan pada
kemampuan melindungi
yang paling lemah.
Bangsa besar bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling cepat mengulurkan tangan
kepada warganya sendiri dan bila perlu, tak malu menerima bantuan demi keselamatan bersama.
EVALUASI
Nasionalisme bukan lomba adu dada, bukan otot yang dipamerkan di cermin geopolitik.
Nasionalisme adalah
kerja sunyi:
logistik tepat waktu,
data akurat,
koordinasi jujur,
dan keputusan yang
berpihak.pada korban,
bukan aksi pencitraan.
Menolak bantuan asing
tanpa kesiapan penuh
adalah seperti menutup
payung sambil berkata,
“Aku tahan hujan demi prinsip.”
Prinsip macam apa yang basahnya
hanya dirasakan rakyat?
BELAJAR MERUNDUK
Tidak ada negara yang runtuh karena berkata terima kasih. Banyak negara runtuh karena menolak belajar dan terlalu mencintai bayangan sendiri. Rendah hati bukan tanda lemah.Ia tanda cerdas. Pemimpin yang besar bukan yang tak pernah dibantu, melainkan yang paham bahwa
kekuasaan …
bukan miliknya,
melainkan titipan
untuk melindungi
kehidupan.
Puisi pamlet ini
tak menunjuk hidung,
tak mengangkat palu hakim.
Solusinya sederhana,
pelaksanaan butuh
keberanian:
- Utamakan nyawa, bukan narasi. Dalam darurat, kemanusiaan harus berdiri di depan protokol.
- Transparansi kepada rakyat.
Jelaskan alasan, kapasitas,
dan batas kemampuan tanpa
jargon berlebihan. - Kolaborasi, bukan kompetisi.
Bantuan asing bisa diawasi,
diarahkan, dan disinergikan
tanpa kehilangan kedaulatan. - Evaluasi nasionalisme simbolik.
Ganti dengan nasionalisme kerja
nyata.Karena pada akhirnya,
negeri ini bukan milik
harga diri segelintir elit,
melainkan milik tangis
yang ingin reda, luka
yang ingin sembuh,
dan harapan yang masih percaya
bahwa pemimpin mendengar dari bawah, bukan hanya dari atas podium.
Dan bila suatu hari
sejarah bertanya …
“Di mana negara saat Sumatera
terluka?”
semoga jawabannya bukan:
“Sedang menjaga gengsi,”
melainkan:
“Sedang menyelamatkan
keberlangsungan hidup
bangsa di tanah kini,
tengah terluka.”
Dari Timur Bekasi
Kamis, 18 Des 2025
18.05