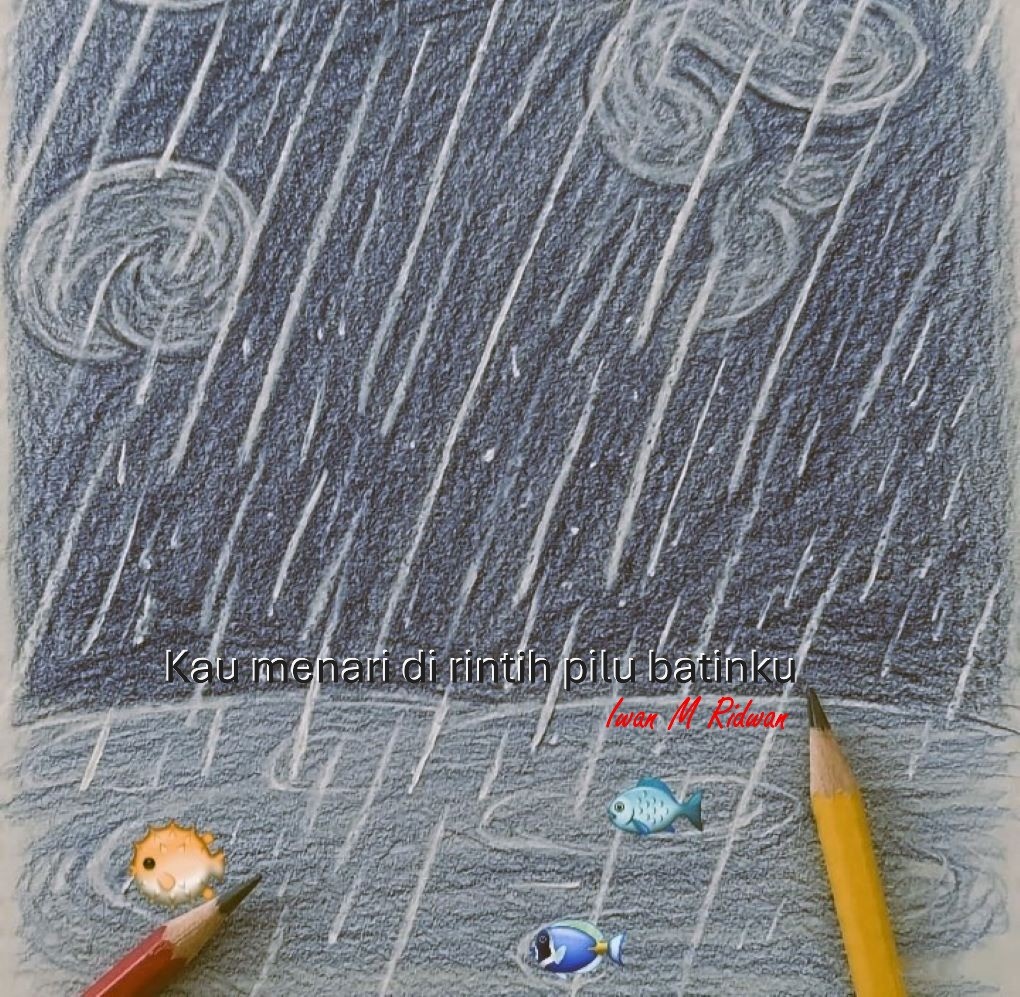Edisi : Demokrasi Kampus
Kampus menjadi benteng terakhir bagi kebebasan intelektual, ruang dimana argumen bertarung bebas dengan argumen, tanpa pengaruh kekuasaan baik internal maupun eksternal. Namun, realitanya berbalik, kampus kerap berpraktek sebagai kuasa tirani, tempat persekongkolan hegemoni dalam persaingan tidak sehat, jauh dari kemuliaan sebagai institusi pendidikan.
Demi kepentingan klik atau kelompok tertentu, demokrasi kerap dipadamkan demi siasat hegemoni memenangkan pengaruh. Yang demikian biasanya bukan dipicu intervensi eksternal, melainkan permainan oligarki turun temurun, semacam sel jaringan para loyalis untuk menguasai sumber daya kampus. Modusnya dilakukan saat pemilihan pejabat struktural dan pejabat kependidikan.
Fenomena ini bukan abu-abu, tapi terang benderang. Melalui pola terstruktur, berulang dalam mekanisme “one man one vote.” Para aktor membuat semacam konsensus dengan menjanjikan kesetaraan, mendesain kemenangan untuk sosok yang dijagokan. Diawali tebar janji, lobi intensif, membuat koalisi “ad hoc”, menyusun narasi selektif, untuk mempengaruhi persepsi pemilih untuk dimanipulasi.
Hasilnya, suara mayoritas hanya ilusi, tunduk pada rekayasa hegemoni. Pemenangnya sudah bisa diduga yaitu kandidat dalam skenario jaringan atau klik kelompok itu. Tujuannya jelas, mengamankan akses kemudahan struktural ke sumber anggaran, hibah penelitian, dana pengabdian masyarakat, sampai proyek pengadaan, dan dana institusi lain yang menggiurkan.
Masih terngiang dalam ingatan, kasus memalukan di Universitas Sebelas Maret (UNS). Pemilihan rektor berujung kekisruhan, akibat permainan hegemoni yang mengecewakan konstituen kampus. Pemilihan dipenuhi intrik dan permainan tidak sehat, dinamika suara direkayasa, sehingga menciptakan ketidakpercayaan kalangan civitas. Proses yang seharusnya deliberatif berubah menjadi arena transaksional, hasutan kelompok lebih menentukan daripada gagasan, dan visi misi kandidat. Akhirnya Dikti membatalkan rektor terpilih, dan minta proses pemilihan diulang.
Kasus serupa juga terjadi di Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar. Persoalan diduga karena majelis kampus didominasi aliansi kekerabatan sektoral. Seleksi rektor menuai kecaman karena kurang transparan, kandidat potensial gugur tanpa alasan, memicu dugaan bahwa suara dimainkan para spekulan dengan tujuan sama; mempertahankan akses dan kendali atas proyek dan anggaran. Jauh dari nilai-nilai dharma dan kerukunan umat, yang seharusnya tumbuh di kampus beragama seperti itu. Demokrasi dirancang sekedar kedok bagi praktek oligarki elitis, tanpa moral dan etiks, pelatuk hegemoni membunuh esensi demokrasi kampus.
Filosof Jerman Jürgen Habermas, dalam teori “deliberative democracy,” bilang; legitimasi keputusan harus dirancang dari deliberasi rasional setara, dimana argumen terbaik dimenangkan, bukan atas manipulasi klik. Kampus sebagai lensa moral bagi mahasiswa untuk mensimulasikan rasionalitas dalam praktek berdemokrasi. Kampus harusnya jadi ladang mereka untuk menyemai benih-benih demokrasi, bukan malah mematikan
Pengamat politik Rocky Gerung sering mengkritik pedas kampus. sebagai satu-satunya tempat yang harusnya jujur dan bebas berekspresi. Orang – orang dalam kampus boleh salah, tapi haram berbohong. Maka semua keputusan harus bertumpu pada kekuatan argumen, perdebatan. harus menjadi ajang pertarungan untuk melihat siapa yang terbaik, bukan didasari kepentingan golongan. Tanpa ruang argumentative, demokrasi kampus akan lahir prematur, bahkan cacat secara intelektual. Buruknya, hari ini ruang dialogis itu ditutup, kritik dianggap pembangkang, ide dituding menghambat inovasi akademik.
Linguist dan filsuf politik Amerika Noam Chomsky memperingatkan ancaman korporatisasi dari dalam terhadap “academic freedom”. Universitas yang dikuasai klik atau kelompok kepentingan internal, dan berisiko menjadi alat transaksi untuk memanipulasi keputusan, bukan pusat pengetahuan kritis. Fenomena ini mencerminkan kegagalan membangun kultur demokrasi pasca-reformasi. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi laboratorium demokrasi, tempat menanamkan nilai toleransi, partisipasi inklusif, dan tanggung jawab etis, berubah menjadi panggung sandiwara. Civitas akademika terjebak dalam pragmatisme dan menikmati kekuasaan bertahun-tahun.
Kampus berubah dari “civitas academica menjadi civitas politica”, penuh intrik dan permusuhan elektoral, yang pada ujungnya mengikis kohesi kolektif. Hegemoni internal dalam kelompok bukan hanya merusak institusi, tapi juga masa depan demokrasi bangsa. Sebab mahasiswa sebagai generasi penerus sedang disuguhi pentas drama sabun, jauh dari filosofi kampus sebagai tempat membangun imajinasi masa depan mereka. Kejujuran dan rasionalitas berpikir dibunuh oleh hegemoni kepentingan, bahkan sebelum lahir di kelas-kelas.
Demokrasi kampus tak boleh jadi potret kotor bagi mahasiswanya. Maka tabiat buruk itu harus enyah, perubahan harus dimulai, misalnya dari proses pemilihan pejabat kependidikan, penguatan posisi senat, dan transparansi aturan berdasar statuta. Senat harus diisi oleh figur yang benar-benar memiliki leadership, representatif dan inklusif, termasuk tidak mentolerir praktek “klik” didalamnya, bukan sebaliknya mereka yang memainkan klik itu. Jika tidak, maka kampus hanya mewariskan pendidikan kosong tanpa makna, karena jiwa intelektualnya dirampas sejak awal.