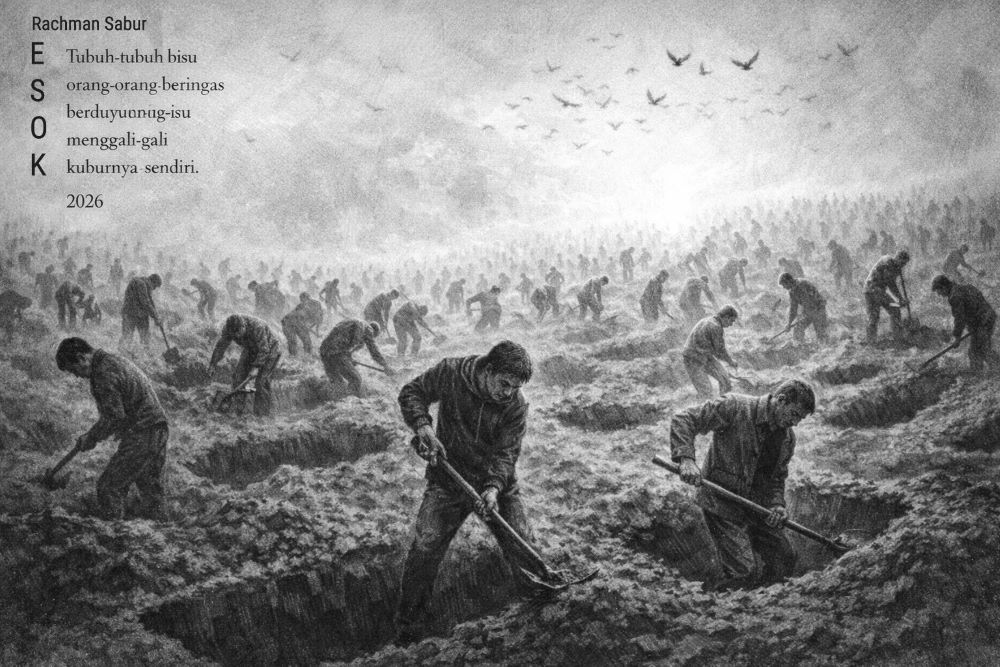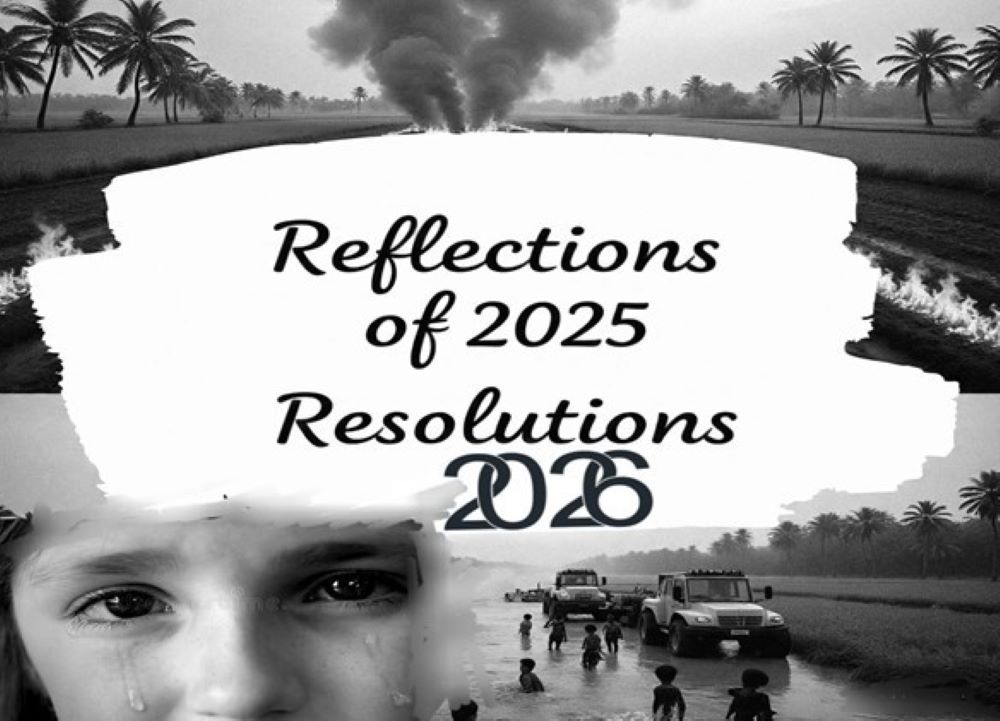Bagian 3
Bagi orang Tassipi, nama Rote bukan hadir pertama lewat peta, tapi dari kisah-kisah yang dibiarkan mengering di geladak perahu: suara orang tua di dermaga menyebutnya lirih, seolah tempat itu bukan sekadar pulau, tapi isyarat. Rote bukan hanya arah, tapi tempat laut menyimpan diam, dan manusia belajar membaca kesabaran.
Kami belajar memetakan karang lewat cahaya pagi, mengenal ikan yang muncul saat bulan diam, dan mematikan mesin saat langit menebar bunyi sirine. Tapi yang paling penting: kami belajar menyimpan kekuatan dalam diam, seperti perahu mereka yang usang, tapi selalu kembali utuh ke laut.
Kadang kami datang membawa kopra, kadang hanya kelelahan yang menempel di kulit. Mereka membuka ruang tanpa syarat, seperti pintu yang tak pernah dikunci.
Tak ada jurnal atau jejak GPS, hanya ingatan basah yang menempel di badan perahu tentang seseorang yang melempar tali saat perahu kami bocor dua mil dari tebing tak dikenali, dan kopi hangat disodorkan sebelum kami sempat menyebut nama.
Laut adalah halaman rumah tanpa pagar, tanpa denah, hanya disepakati dalam senyap oleh garis yang ditarik arwah para tetua. Maka hubungan itu ditambatkan bukan pada pelabuhan, tapi pada pengertian yang tak perlu dijelaskan: bahwa kami dari Tassipi tidak datang sebagai tamu, melainkan kembali sebagai bagian yang tak pernah hilang.
Logat kami patah-patah, wajah kami tak saling menyerupai, tapi mata kami menghadap arah angin yang serupa. Mereka berbagi ruang jemur ikan. Kami bertukar jerigen, rokok, dan cerita konyol yang lebih dipercaya dari siaran mana pun. Kami belajar membaca arah angin dari mereka. Sebaliknya, orang Rote menanyakan titik-titik menyelam yang tak terjangkau oleh radar.
Kalau ditanya siapa yang lebih dulu tiba di Pulau Pasir, tak seorang pun ingin menjawab. Di laut, yang lebih penting adalah siapa yang tak membiarkan yang lain tenggelam.
Sejenak aku melihat Asmore Reef[1] di layar ponsel. Hanya ingin tahu apakah pulau kecil itu benar-benar ada. Di peta, ia tampak seperti noda samar, bukan tempat untuk tinggal, dan terlalu kecil untuk jadi pelarian.
Tapi mereka tinggal di sana. Dalam senyap yang disembunyikan angin. Dalam napas yang tak boleh lebih keras dari ombak. Satu malam, saat lampu kapal patroli muncul dari utara, menyisir laut seperti tuduhan yang belum dilafalkan, tak seorang pun bicara. Bahkan api perapian ditutup dengan karung basah agar tak menyala terang.
Malam itu, aku menunduk lebih dalam dari pasir.
“Di sini kami tidak bersembunyi. Kami cuma tak ingin ditemukan dengan cara yang salah,” katanya.
Beberapa hari kemudian, pasir itu menjadi dermaga rahasia. Perahu berjajar seperti tulang rusuk makhluk laut yang tidur dalam diam. Tak ada suara keras. Hanya langkah yang disimpan. Lagu-lagu berubah menjadi gumam. Waktu yang tak bisa ditandai dengan kalender.
Malam-malam tertentu, sorot lampu dari utara menyapu cakrawala seperti jari yang menunjuk. Mereka tak lagi bicara, hanya saling menunjuk bibir. Karena di pulau sekecil ini, diam adalah pertahanan terakhir.
Berada di Asmore Reef bukan untuk menyelamatkan tubuh, tapi menyelamatkan pilihan hidup yang tidak diizinkan dunia ramai.***
Tassipi, 2025

Pulau Pasir dan Lelaki Laut
[1] Ashmore Reef (disebut Pulau Pasir oleh nelayan Indonesia) adalah terumbu karang yang secara administrasi masuk teritori Australia. Laporan operasi Sovereign Borders, tahun 2024 ada 120 nelayan lokal telah ditangkap di perairan Ashmore sebelum dialihkan ke pusat penahanan luar negeri di Nauru atau Darwin.