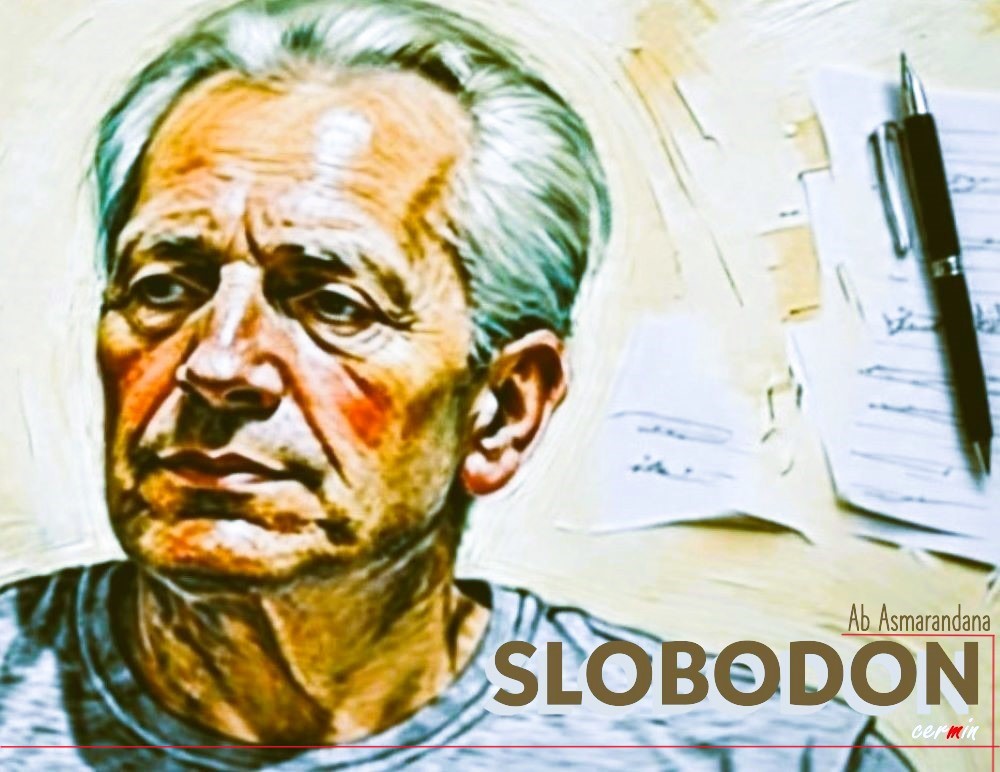Catatan Esai dari Wakorumba Selatan
Di atas piring putih dengan tepi mengilat, tiga hidangan khas tersaji seperti tiga ingatan yang duduk rapi menunggu waktunya dibuka. Dari sudut mana pun kau mulai, semuanya seperti memiliki jalannya sendiri untuk dikenang.
Kainde[1], dibungkus daun palas yang telah layu karena uap panas. Nasi merah yang menyimpan keheningan. Ia bukan nasi untuk tergesa-gesa atau untuk piring yang berisik oleh sendok dan tawa. Ia di sana, hangat, tenang, seperti seorang ibu yang menyimpan banyak cerita namun memilih diam. Ada aroma samar jejak asap dan tanah. Sebuah perpaduan antara ladang yang jauh dan dapur yang sabar. Saat dibuka, kau tahu bahwa ia dibentuk bukan hanya dengan tangan, tapi juga waktu.
Tak jauh dari situ, manu doforu[2] menanti dalam diam yang lain. Potongan ayam kampung yang dimasak dengan kunyit dan jahe itu membawa warna kuning tua seperti matahari sore yang tumpah ke lantai papan. Kuahnya tipis, hampir menghilang di dasar piring, tapi menyisakan rasa yang dalam. Setiap serat daging seperti membawa jejak langkah dari halaman ke dapur, dari tanah kering ke sumur, dari pagi-pagi ketika ayam masih liar di pekarangan rumah.
Rasa hangatnya bukan hanya dari bumbu, tapi dari kisah panjang tangan-tangan perempuan yang menumbuk, memotong, mengaduk dengan pelan. Pedasnya lembut. Dan setelahnya, kau seperti mendengar lagi suara kayu terbakar dan uap naik perlahan di bawah atap yang bolong.
Tapi dari ketiganya, kaghopa[3] adalah yang paling sunyi tapi paling banyak bicara.
Kerang kogho yang telah dibakar ulang itu tampak sederhana: gosong di tepi, diikat silang dengan tali alami, tak banyak hiasan. Tapi di dalamnya, parutan kelapa sangrai dan bumbu halus telah menjelma jadi inti dari semua perayaan: rasa gurih, sedikit manis, dan aroma laut yang tak bisa ditiru. Smoky dan umami berpadu, seperti kenangan yang tidak berisik tapi tak pernah benar-benar pergi. Ada bara yang tertinggal dalam rasanya, seperti jejak malam-malam panjang di rumah tua dekat laut.
Dagingnya berserat, sedikit liat. Ia tak mudah dimakan. Tapi ia jujur.
Kerang itu tidak berasal dari pasar. Ia ditangkap oleh tangan-tangan kecil anak-anak pesisir, saat laut sedang surut dan matahari menggantung rendah di atas Selat Tiworo. Mereka tahu tempat-tempat tersembunyi di antara bebatuan dan akar pohon bakau. Tidak ada yang diajarkan dalam buku sekolah. Semua diwariskan dari kaki ke mata, dari gerak tubuh ke arah rasa. Usia di bawah remaja, mereka sudah tahu kapan laut sedang bersahabat atau diam-diam menyimpan teguran.
Kerang itu kemudian direbus, dikorek dagingnya, dicincang halus, dicampur kelapa parut, ditumis bumbu, lalu dimasukkan kembali ke dalam tempurung. Tapi tak selesai di sana. Ia masih harus dipanggang ulang, diberi bara seperti ritual kecil agar semua rasa menyatu. Tak ada oven, tak ada suhu presisi. Hanya abu yang menghangat pelan, seperti tubuh yang tahu kapan harus cukup.
Aku menyantapnya perlahan, duduk di atas lantai kayu rumah panggung yang sebagian dindingnya masih dari bambu. Di sekitarku ada nyanyian, ada candaan. Tapi aku seperti duduk sendiri bersama ingatan, bersama laut, bersama rumah yang tidak seluruhnya kupahami tapi terasa seperti mengenal tubuhku lebih dulu.
Tiga rasa. Tiga cerita. Satu piring.

Hari itu, aku tidak hanya menyantap makanan. Aku sedang menjemput kembali sesuatu yang tak punya nama, tapi sempat hilang: perasaan bahwa bahkan di tempat yang bukan milikmu, kau bisa menemukan sesuatu yang mengerti perut dan hatimu.
Dari ketiga hidangan yang tersaji siang itu, kaghopa tampak paling tenang. Tidak mengepul seperti kainde, tidak berwarna mencolok seperti manu doforu. Ia kecil, nyaris tersembunyi di sudut piring, hanya dibalut simpul pelepah dan arang yang masih menghitam. Tapi justru di sanalah ia berbicara dalam diam yang tak memohon perhatian, tapi membuat siapa pun ingin mendekat dan membuka.
Saat tangan menyentuh kulit keras tempurungnya, ada suhu yang masih tersisa dari bara: hangat seperti telapak seseorang yang baru saja menyiapkannya. Ketika dibuka, aroma kelapa sangrai bercampur asin laut keluar pelan-pelan, menyeruak seperti napas yang dalam. Wangi air laut yang mengering di antara bebatuan. Jejak rumah asap yang jauh dari kota. Rasa yang lebih seperti cerita daripada resep.
Warnanya coklat keemasan, parutan kelapa dan cincangan kerang itu menyatu seperti tak bisa dibedakan mana laut dan darat. Teksturnya rapuh tapi padat seperti serpih karang yang menyimpan waktu. Rasanya? Gurih, smoky, ada manis yang tertahan di belakang lidah. Smoky-nya bukan seperti daging panggang, tapi seperti aroma perahu yang baru ditambatkan. Umami-nya datang belakangan, tapi bertahan paling lama.
Ia tidak dipilih. Tidak disodorkan. Tapi diam-diam, mungkin itu yang paling aku rindukan.
Dari semua yang bisa kau kenali: panasnya tempurung, wanginya asap, kilau kelapa, bunyi kecil saat kau belah adalah bahasa paling jujur. Karena hanya lewat rasa, kita bisa mengenali apa yang ingin disampaikan sesuatu yang tak pernah bisa bicara.
Dan kaghopa masih bicara banyak.
Piring tempatnya disajikan tampak mengilap, pecah belah putih, bersih tanpa cela, diangkat dari lemari kaca buram yang biasanya terkunci. Piring itu hanya keluar untuk hari besar: syukuran, pernikahan, tamu jauh. Di pesisir ini, tamu dihormati bukan dengan sambutan, tapi dengan pemilihan: piring terbaik, waktu terbaik, yang ada dibagi sampai habis. “Kami tidak punya banyak. Tapi yang kami punya, kami beri seluruhnya.”
Tapi mataku sempat tertumbuk pada satu sudut meja: sebuah piring kayu bundar, kosong, beralas daun pandan yang dianyam seperti tikar kecil. Ia tak ikut dipilih atau tak ikut disodorkan. Tapi kehadirannya seperti menggantungkan sesuatu, pelukan yang tak diucap, tanah yang tak bicara, tapi menyambutmu pulang.
Karena rasa tahu jalan pulang, bahkan ketika kata-kata tersesat.***

10 Tempat Wisata Terbaik Indonesia 2025
___________________
[1] Makanan padat dari beras merah yang ditumbuk panas, dibungkus daun palas, lalu dibakar di bara tempurung kelapa.
[2] Kuah ayam kampung dengan daun serei, jahe, dan cabai, dimasak perlahan hingga menyatu dalam kuah kuning pucat.
[3] Hidangan sederhana dari kerang kecil (kogho) yang ditangkap anak-anak pesisir saat laut surut, khususnya di Selat Tiworo.
_____________
# essai kuliner etnografi [red]