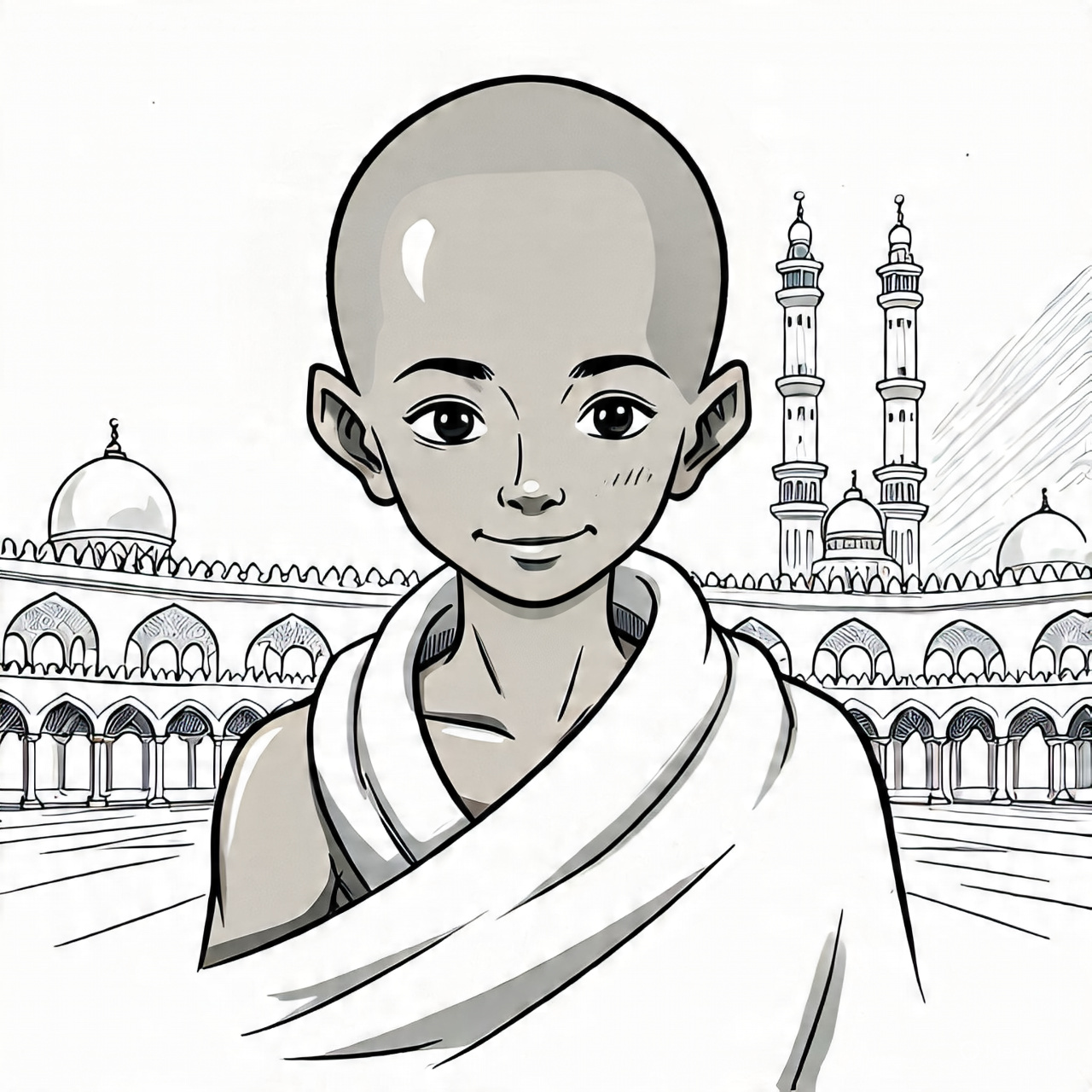Kekuasaan Tidak Cukup Legal—Ia Harus Etis
Dalam demokrasi, kekuasaan bukan hanya soal prosedur dan legalitas, tetapi juga soal moralitas. Seorang pemimpin mungkin sah secara hukum, tapi belum tentu legitimate secara etis. Inilah persoalan mendasar yang kini banyak melanda negara demokratis, termasuk Indonesia, Polandia, dan Turki.
Di Indonesia, publik menyaksikan bagaimana etika di Mahkamah Konstitusi dipertanyakan dalam sejumlah putusan penting. Di Polandia dan Turki, intervensi kekuasaan terhadap sistem peradilan bahkan mengundang kritik internasional. Tiga negara dengan latar belakang hukum yang berbeda ini memperlihatkan gejala yang sama: kekuasaan yang melampaui batas, dan lembaga hukum yang kehilangan integritas.
Etika Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat Politik
Filsafat politik mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bersumber dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan publik. Jean-Jacques Rousseau menyebutnya sebagai volonté générale atau kehendak umum. Dalam pandangan ini, pemimpin sah bukan hanya karena dipilih secara prosedural, tapi karena ia merepresentasikan nilai dan aspirasi kolektif rakyat.
Hannah Arendt bahkan menegaskan bahwa kekuasaan yang lahir dari proses kolektif masyarakat hanya dapat bertahan selama ia merefleksikan kebebasan dan partisipasi publik. Jika tidak, kekuasaan itu berubah menjadi dominasi yang membungkam ruang publik dan menyingkirkan etika.
Ketika lembaga hukum digunakan untuk membuka jalan bagi kekuasaan yang menguntungkan pihak tertentu—terutama jika disertai pelanggaran etik—maka kita menghadapi krisis moral dalam demokrasi. Demokrasi tidak hanya hidup dari suara terbanyak, tetapi juga dari kepercayaan terhadap etika publik.
Indonesia: Ketika Etika Ditinggalkan oleh Lembaga Hukum
Kita menyaksikan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial sempat membuka jalan bagi pencalonan politikus yang masih memiliki hubungan keluarga dengan penguasa. Meski secara hukum prosedurnya dinyatakan sah, masyarakat mempertanyakan moralitasnya, apalagi setelah terbukti ada pelanggaran etik berat oleh hakim konstitusi yang terlibat.
Ironisnya, meski pelanggaran etik sudah terang benderang, tidak ada sanksi hukum yang sepadan. Inilah momen di mana hukum kehilangan nilai etikanya. Hukum tetap berjalan sebagai teks prosedural, namun kehilangan daya korektif terhadap kekuasaan.
Filsuf hukum Lon L. Fuller menyebut bahwa hukum yang baik bukan hanya sah secara formal, tapi juga harus memiliki “moralitas internal” seperti kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan. Jika prinsip ini diabaikan, maka hukum hanya menjadi alat kekuasaan, bukan penjamin keadilan.
Polandia: Ketika Lembaga Yudisial Dikendalikan oleh Politik
Polandia adalah contoh nyata bagaimana partai penguasa bisa mengontrol lembaga peradilan. Sejak reformasi sistem peradilannya dimulai, partai berkuasa di Polandia menempatkan hakim-hakim yang loyal, mengubah aturan disiplin hakim, dan menekan independensi Mahkamah Konstitusi.
Akibatnya, Uni Eropa mengecam keras langkah Polandia dan bahkan menjatuhkan sanksi karena dianggap melanggar prinsip rule of law. Dalam negara demokrasi, tekanan politik terhadap hakim adalah sinyal membahayakan: hukum tidak lagi berjalan independen, melainkan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
Turki: Hukum yang Dirombak demi Stabilitas Politik
Setelah kudeta militer yang gagal pada 2016, pemerintah Turki melakukan pembersihan besar-besaran di sektor yudikatif. Ribuan hakim dan jaksa diberhentikan karena dituduh terkait dengan kelompok oposisi. Pemerintah menggantinya dengan aparat yang loyal terhadap rezim.
Langkah ini dilakukan atas nama stabilitas nasional, namun nyatanya melemahkan integritas hukum. Proses hukum tidak lagi bebas dari intervensi politik, dan sistem peradilan berubah menjadi instrumen otoritarianisme yang dilegalkan.
Persamaan Masalah: Etika yang Dikalahkan oleh Legalitas
Dari ketiga negara tersebut, kita bisa melihat pola yang sama: hukum digunakan untuk memberi legitimasi pada kekuasaan, bukan untuk membatasi atau mengawasinya. Persoalannya bukan pada teks hukum, tetapi pada pelanggaran etika dan hilangnya keberanian untuk menegakkan moralitas publik.
Fenomena ini adalah bentuk dari apa yang disebut Gustav Radbruch sebagai hukum yang sangat tidak adil, sehingga tidak layak lagi disebut hukum. Dalam konteks ini, ketika hukum kehilangan daya moralnya, ia tak lebih dari legalitas yang kosong. Indonesia mungkin belum sejauh Polandia dan Turki, tetapi jika pelanggaran etik terus diabaikan, arah itu bisa jadi tidak terelakkan.
Etika Tidak Bisa Dihapus dari Sistem Hukum
Dalam sistem hukum modern, terdapat perbedaan antara das Sein (apa yang terjadi) dan das Sollen (apa yang seharusnya). Pelanggaran etik yang terjadi di dunia nyata seringkali bertentangan dengan ideal hukum yang menjunjung integritas, keadilan, dan netralitas.
Secara epistemologis, hukum harus dibangun atas dasar rasionalitas dan objektivitas. Namun ketika sistem peradilan dikuasai oleh konflik kepentingan atau kompromi politik, maka epistemologi hukum menjadi bias dan tidak lagi dapat dipercaya sebagai sumber keadilan.
Legitimasi kekuasaan tidak bisa hanya bergantung pada prosedur. Harus ada prinsip moral yang melandasinya—karena yang sah secara hukum belum tentu adil secara sosial.
Refleksi: Demokrasi Harus Tunduk pada Etika, Bukan Sekadar Prosedur
Pemakzulan, koreksi yudisial, atau evaluasi terhadap pejabat publik bukan soal politik praktis semata. Ia adalah bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi. Negara hukum yang sehat adalah negara yang tidak hanya berjalan berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan moralitas publik.
Demokrasi bisa mati dalam sunyi jika etika dikorbankan atas nama prosedur. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, maka hukum tak lagi memiliki kekuatan—karena ia kehilangan legitimasi sosial.
Penutup: Etika Adalah Fondasi Demokrasi
Belajar dari Indonesia, Polandia, dan Turki, satu hal menjadi jelas: ketika kekuasaan tidak lagi tunduk pada etika, maka demokrasi berada di ujung tanduk. Prosedur hukum bisa dipenuhi, tetapi kepercayaan publik sulit dikembalikan.
Yang harus kita perjuangkan bukan hanya keteraturan prosedural, tetapi keberanian moral untuk menegakkan etika di tengah kekuasaan. Demokrasi yang sehat tidak lahir dari prosedur semata, tetapi dari kesadaran bahwa tidak semua yang legal itu adil.
Karena pada akhirnya, negara hukum sejati bukan hanya yang dipenuhi aturan—tetapi yang menjunjung keadilan. []