Catatan Penulis
“Apa yang terjadi jika tokoh naskah menyadari bahwa darah mereka hanyalah tinta yang ditumpahkan pengarangnya?”
Pentalogi Rahim Kata adalah perjalanan eksperimental yang meruntuhkan sekat antara pencipta dan ciptaan. Berawal dari tragedi inses dan darah keluarga Raka-Lastri dengan judul Atas Nama Doa atawa Senyum Lastri, naskah monolog ini meledak menjadi gugatan eksistensialis yang brutal, serta banyak dipentaskan baik oleh komunitas teater pun komunitas kampus.
Hal ini membuat penulis berpikir: bagaimana kalau naskah monolog ini dikembangkan dan dijadikan pementasan berseri dalam satu waktu—yang mana awalnya Raka menggugat takdir pembunuhnya, Lastri menggugat eksploitasi raganya, dan Lintang Ismaya terjebak dalam rasa bersalah atas ‘tuhan-tuhanan’ yang ia mainkan di atas kertas atawa alur cerita.
Penulis, dalam pengembangan monolog itu menjadi motif-motif baru (naskah beranak) dengan pilihan durasi alur kisah pentasnya pendek-pendek (menyesuaikan sikon dengan zaman instan). Namun untuk mengembangkannya menjadi pantalogi, penulis terinspirasi dari semangat Huis Clos karya Sartre, tentunya sesuai dengan pemahaman penulis. Pentalogi ini membawa penulis ke titik di mana pintu tidak pernah ada. Neraka adalah keharusan untuk saling menatap selamanya di dalam rahim kata. Sebuah gugatan dari balik titik; di mana akhir cerita justru menjadi awal dari siksaan yang abadi.
BAGIAN I: Naskah Monolog ATAS NAMA DOA ATAWA SENYUM LASTRI (Tesis: Akar Tragedi dan Kejadian Mula) Sebuah potret keluarga yang hancur di mana doa bercampur dengan nafsu, dan takdir mulai dipintal oleh tangan yang tak terlihat.
RUANG PENJARA (bawah tanah, semacam sumur). PESAKITAN TAMPAK TIDUR SEPERTI ANJING. DARI ATAS LANGIT-LANGIT JATUH BUKU DAN BOLPOIN MENIMPA MUKANYA. TERDENGAR SUARA SESEORANG: “Besok, hari terindahmu, menghadapi duabelas regu pasukan tembak. Tulislah biografi hidupmu biar semuanya jelas. Siapa tahu kau jadi figur yang fantastik bagi generasi mendatang?” ORANG ITU TERTAWA.
PESAKITAN BANGUN SECARA PERLAHAN-LAHAN. MELIHAT SEKITAR. MELIHAT KE ARAH SUMBER SUARA. MENGAMBIL BUKU DAN BOLPOIN. PESAKITAN TERTAWA LEPAS. BERNYANYI-NYANYI RIANG. SEPERTI MENULISKAN SESUATU DI DALAM BUKU TERSEBUT.
Seseorang datang dan pergi di kehidupanku. Seperti angin waktu yang kerap menyimpan ribuan rahasia. Begitulah adanya hidupku. Aku terbentuk, terpatok, terpenjara, terkontaminasi, terseok-seok, menjadi sesosok diriku. Lahir dan tumbuh, sampai akhirnya terpatri di tempat ini.
BANGKIT. MENCARI PUNTUNG ROKOK DAN MENYALAKANNYA. MEMAINKAN ASAPNYYA. TERTAWA. MENARI-NARI KECIL BAK BALERINA.
Sejarah. Yap. Semua orang pada akhirnya sama; saling berebut tentang sejarah. Menuliskannya pada lembar demi lembar buku sejarah. Tanpa peduli ada yang membacanya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, hanya dibaca oleh diri kita sendiri.
SEPERTI MENDENGAR SUARA. Apa? Yap. Benar. Pendapat anda benar sekali. Bukankah di hadapan Sang Pencipta, yang kita sodorkan dan diperiksa adalah lembar demi lembar sejarah hidup dan kehidupan kita? Itulah fungsinya malaikat, sebagai asisten kita yang dianugerahi dari Sang Pencipta. Ya, siapa yang mampu menghapus biografi di hadapan-Nya?
HENING SEJENAK. TIBA-TIBA SEPERTI MENGAMUK. Asu. Bangsat. Apa peduliku dengan dogma-dogma? Ketika lonceng gereja berbunyi, tak ada lagi biara-biara suci. Tak ada lagi nyanyian koor. Ketika gema adzan berkumandang, tak ada lagi kiai yang membawa santri-santrinya untuk berjamaah. LANTANG SUARANYA. Aggggggggggh…. EMOSINYA MENINGGI. Ibuku, baru saja satu hari meninggal, bapaku sudah kawin lagi. Aku dan adikku ditendangnya dari rumah. Agama. Apa yang aku dapat dari pemahaman nilai-nilai religius yang ditanam sejak kecil oleh ibu dan bapakku? Sementara kelakuan bapakku tak ubahnya anjing!
SEPERTI MENDENGAR ORANG BICARA. LIRIK KANAN-KIRI. KEPALA DAN TUBUHNYA BERPUTAR-PUTAR. SUARA-SUARA ITU SEMAKIN TAJAM MENGHUJAMI PIKIRANYA. Diam! Tidak! Aku tidak sensitif. Tapi aku berbicara fakta. Jangan menghakimi aku begitu rupa. Ini urusan pribadiku. Apa hak kalian? Kalaulah ayah dan ibu tiriku mati ditanganku, bukan semata-mata alasan klise, balas dendam. Tetapi ini murni sebagai bahasa nurani. Aku tidak bersekutu dengan iblis! Kasihan dong setan, jadi kambing hitam terus? Ini naluriku untuk bertindak.
KEPADA PENONTON. KEPADA ORANG-ORANG YANG ADA DALAM IMAJINASINYA. Wah, kacau rupanya kalian tidak hafal dengan doa. Doa itu perbuatan. Doa itu keinginan. Doa itu angan-angan. Doa itu kata-kata. Doa itu harapan. Doa itu tingkah laku kita. Itulah kemurahan Sang Pencipta atas hidup kita, ngerti?
SEPERTI MENDENGAR SUARA-SUARA YANG MENGHUJAT. MENUTUPI TELINGA. BERPUTAR-PUTAR. GELISAH. Stop. Stop. Kenapa kalian jadi membela bapak dan ibu tiriku? Tindakan dan keinginanku beda benar dengan perbuatan bapak dan ibu tiriku. Bapak dan ibu tiriku kawin adalah keinginan setan, bukan doa. Kalau aku barulah doa, …, …, … Lho. Lho, kenapa kalian bergembira dengan mentertawakanku? Apa kata-kataku salah? Hak asasi dong? Prerogatif dong? Kreatif dong? Inovatif dong? Ah… kalian bisanya tertawa melulu, benci deh aku. Sebel deh aku, muak-muak, muaak tahuuuuu!
TIBA-TIBA DIA MENANGIS. Tak ada yang lebih mulia dari hati seorang ibu. Ibu adalah tempat kita di kala kita sedang dibenturkan masalah. Ibu adalah satu-satunya surga dalam kehidupan dunia.” HENING. “Aku pernah mukim di sebuah pondok, mendalami nilai-nilai teosofi. Di mana betapa mulia posisinya seorang ibu bagi kita. Kalian tahu? Hei…” KEPADA PENONTON. “Kalian tahu tidak? Kalau tidak tahu, makanya dengarkan! Kalau sudah tahu, seguru seilmu makanya jangan saling mengganggu, oke? Sebab ini adalah sesuatu yang sakral, maka aku harus berdoa dulu.
MULUTNYA BERKOMAT-KAMIT SEPERTI SEDANG MERAJAH. Berapa literkah air susu ibu yang terhisap dan diminum oleh kita? Berapa kotoran kitakah yang terkecapkan dan termakan oleh ibu kita ketika ibu kita sedang makan? Dan kita menangis karena pipis atau boker? Ibu berhenti dari makannya. Melayani kita. Lalu ibu melanjutkan makannya. GANJEN. Ih… gak kebayang deh betapa joroknya kotoran kita termakan oleh ibu kita?
SUARANYA MENINGGI. “Aku tidak mau disebut durhaka. Aku tidak mau dibilang jahat. Aku tidak mau mengamalkan aji air susu dibalas dengan air tuba. Itulah sebabnya kenapa aku membunuh bapak dan ibu tiriku sekaligus. Bukan semata-mata gelap mata, melainkan aku anak soleh! Untuk saat ini kalian boleh tertawa atas penjelasanku. Sebab kalian tidak pernah mengalami hal sepertiku. Doaku pada kalian: cepat-cepatlah kalian mengalami kisah sepertiku, biar tahu mana hitam, mana putih, mana yang namanya abu-abu.” HENING.
Pada suatu malam yang lembab, panjang, dan dingin; ketika seakan-akan benda-benda yang ada dihadapanku bergoyang; atas kabar kematian ibuku, aku mendengar, aku melihat seulas senyum tersungging dari bibir bapak yang tebal, berlapis nikotin. Aku tak paham tentang sesungging senyum itu, apakah ia berusaha menenangkan pikiranku?
Aku bukanlah orang baik, tapi aku berusaha menjadi baik. Di luar sepengetahuan bapak dan ibuku; aku adalah pencandu narkoba, peminum minum-minuman keras, sesekali aku main perempuan dan judi, sebagai tambahannya. Jalan hidup yang aku tempuh bagiku adalah wajar dan sah untuk dilakukan, sebab hidup adalah pilihan, bukan? Seperti kedua orang tuaku yang memaksaku harus kuliah, demi sebuah prestise di kehidupan bermasyarakat. Dan keinginan-keinginan yang bergejolak di kedalaman dada ini adalah fitrahNya yang diberikan pada kita atas rahmatNya, iya kan?
Kalian boleh lho mencontoh dan meniru atau menjadi imitasiku. Atau meniru hidup seperti ibuku? Ibuku lahir dari keluarga terpandang, disiplin ilmunya tinggi, pemahaman nilai-nilai religiusnya sangat mantap. Kekayaan orang tuanya tak tertandingi di kota ini, tapi itu semua tidak menjadikan sosok ibu lupa pada nilai-nilai nas Sang Pencipta. HENING.
Sedang bapaku, lahir dari kalangan strata sederhana. Ia adalah sopir pribadi ibuku, dikala ibuku masih perawan. Entah kenapa, siapa yang memulai, siapa yang menanamkan benih-benih cinta di hati mereka, posisi majikan dan pembantu berubah gembira: menjadi pasangan suami istri.
Sampai akhirnya aku terlahir sebagai anak pertama yang memilih hidup di jalur generasi koplo. Lima tahun berselang; lahirlah adikku satu-satunya. Adikku berjenis kelamin perempuan. Kecantikannya, sama seperti ibuku. Untungnya bibir adiku tipis. Tak kebayang kalau bibirnya tebal seperti bapaku. Pasti adikku akan disebut si bibir jeding olehku. HENING.
BERUSAHA TEGAR. Aku sangat menyayangi adiku. Ke mana pun ia pergi, aku kerap berada di sampingnya. Walau awal-awal kelahirannya; aku sangat dibikin cemburu, sebab ibu dan bapaku jadi lebih perhatian padanya. Adikku bernama Lastri Kinasih.” HENING. “Kata ibuku: Lastri diambil dari kata Lestari dan Kinasih diambil dari kata.., .., …,
KEPADA PENONTON: Apa coba? Nah. Betul! Seratus, tus, tus,… dari kata kasih. Di mana penjabaran ibuku selanjutnya; Lastri Kinasih adalah sifat Sang Pencipta yang selalu mengabulkan doa-doa kita. Terutama doaku yang telah dikabulkanNya, atas pembunuhan bapak dan ibu tiriku. Betapa indah kasih Sang Pencipta. Betapa nikmat kepercayaan Sang Pencipta yang dibebankan di pundakku; aku bertindak sebagai algojoNya, menjadi malaikat tanpa sayap untuk mencabut nyawa bapak dan ibu tiriku sekaligus dalam hari itu juga. HENING.
KETAWA. Lastri kecil perlahan-lahan tumbuh menjadi bunga desa. Kecantikannya harum mewangi, menjadi momok sekampung. Sempat beberapa kali, Lastri hendak menjadi korban pemerkosaan, tapi untunglah aku kerap memergokinya. Bukan hanya hendak diperkosa oleh teman-temannya. Orang asing. Bahkan bapaku sendiri.
Sejak saat itu, naluriku untuk membunuh tumbuh secara diam-diam; semua laki-laki yang mencoba melakukan tindak kriminal pada Lastri, tak ada yang selamat ditanganku; aku habisi nyawa mereka. Aku membunuhnya. Lastri tahu semuanya, tapi Lastri diam. Dia tidak melaporkanku pada yang berwajib.
Bahkan, ketika aku memergoki bapak mau memperkosanya, Lastri membela bapaku: “Mas jangan sampai ibu tau tentang hal ini. Cukuplah kita saja yang tahu, kasihan ibu. Pasti ibu syok berat mendengarnya. Lastri mohon sekali lagi padamu mas, Lastri mohon, bapak kita jangan kau bunuh, seperti lelaki-lelaki lainnya?” Begitulah permohonan Lastri padaku. HENING.
Detik jam, mendorong usia bumi. Bunga-bunga layu di mata. Usia dimakan masa. Ketika cinta sedang menuju puncaknya, kami sekeluarga tak bisa memandang dengan jernih. Kematian ibukulah, pangkal dari semua ini. Lastri syok atas kematian ibu. Jangankan Lastri, aku sendiri pun mewek termehek-mehek: tato, anting dan rambut gimbalku, tak bisa menahan air mataku yang jatuh di hadapan jasad ibuku. HENING.
Satu hari kemudian, dari kematian ibuku; barulah bapaku menikah lagi, Lastri kian depresi, sering tertawa sendiri, mukanya garang. Sesekali terlihat sendu. MENITIKAN AIR MATA. HENING. Hari berikutnya, setelah kami dikenalkan dengan ibu tiri kami; bapakku mengusir kami dengan alasan tak ada hak waris untuk kami. Bahkan yang lebih menyakitkan, bahwa kami bukan darah dagingnya. Itulah sebabnya mengapa bapak berani melahirkan tindakan percobaan pemerkosaan pada Lastri.
BANGKIT. BERANG. SEPERTI MENCEKIK LEHER BAPAKNYA. Bangsat. Asu. Jancuk. Orangtua biadab. Leher bapakku, aku cekik sekuat tenaga; namun adiku berteriak, bangkit dari duduknya: “Ingat mas, mungkin ini sudah jalan takdir kita? Mesti mas pernah bercerita tentang proses kelahiran kita yang sama keluar dari rahim ibu kita dan lelaki yang dihadapan kita saat ini, yang selama ini kita menyebutnya bapak kita? Bisa jadi, perkataan lelaki ini benar adanya mas?” HENING.
Dengan berat hati pikir dan rasa; hari itu juga, kami meninggalkan rumah besar ala arsitektur Belanda. Kata almarhumah ibuku, rumah itu sebagai hadiah perkawinan dari kedua orang tuanya yang kini sudah sama-sama tidur tenang di kedalaman tanah bersama ibuku. Kami tidak mengetahui alasan yang pasti, mengapa rumah itu jadi hak milik bapakku? Terlebih-lebih lagi, ketidakmengertianku; mengapa kami tidak mewarisi darah daging bapakku? Apakah mungkin lelaki yang kusebut bapakku itu mandul? Lalu siapa bapak kami yang sebenarnya?
Malam itu, bagi kami laksana neraka jahanam. Figur Bapak yang tegas. Sosok ibu yang nyantri, semuanya lenyap, ditelan duka raya. Tak ada kebanggaan dengan nilai-nilai. Kami berjalan menyusuri jalan hitam, melewati hutan lambang. Tiba di persimpangan, tiga kelokan dari kost, di dekat tempatku kuliah: sambil istirahat; Lastri membuka percakapan, “Mas, mungkin ini sebabnya, mengapa ibu mau menikahi bapak, padahal bapak sopirnya ibu? Adakah ibu kita sebinal itu, hamil di luar nikah, sebelum kawin dengan bapak? Dan kau mas, bukan anak bapak? Demikian aku, bukan anak bapak pula, lantas siapa bapak kita sebenarnya mas? Adakah lelaki yang dianggap bapak kita selama ini adalah penutup aib ibu kita? Bukankah dia dulunya sopir ibu kita? Dan rumah itu adalah pil tutup mulut buat lelaki yang selama ini kita anggap sebagai bapak?”
Aku tak bisa menjawabnya dengan tegas, nyaris tak ada jawaban, selain suara napasku kian tak terpacu degupnya. Bahkan saat itu, aku takut dengan suara napasku sendiri. “Mas, kau masih ingat, ketika bapak mau memperkosaku? Waktu itu, kau hendak membunuhnya demi kehormatanku, tapi aku melarangnya untuk kau habisi? Kini sudah jelas semuanya, bahwa dia bukan bapak kita. Mas, mengapa tidak kau bunuh saja dia sekarang?”
Mendengar pemaparan berikutnya, naluri membunuhku gairah kembali; dalam hatiku, aku menyanggupi keinginan adiku itu. Satu minggu kemudian, tanpa sepengetahuan Lastri, aku membunuh bapak dan ibu tiriku. BEREKSPRESI MEMPRAKTEKKAN MEMBUNUH. Agh,… agh,… dengan tujuh kali tusukan yang tepat mengena di arah jantung bapak, bapak mati dengan belati. Sedangkan ibu tiriku, aku tebas lehernya dengan golok, sampai putus. Aku sudah terbilang profesional untuk membunuh, tak ada jejak yang aku tinggalkan untuk didengus polisi.
Semua berjalan lancar dan sempurna; sampai aku kembali ke rumah kostanku di kota; tak satu pun yang tahu, bahwa akulah pembunuhnya, termasuk Lastri. Tiga hari dari sana, orang sekampung digegerkan dengan bau bangkai yang tidak lain dari rumah kami. Tetangga yang tahu tempat kami bermukim, memberitahu kami; bahwa kemungkinan besar, berdasarkan penyelidikan polisi, rumah orangtua kami kemasukan rampok.
Memang benar, di samping aku membunuh mereka; aku pun merampoknya, yah,… lumayanlah, untuk bekal kami hidup di kota. Wajarkan? Anak yang dibuang gitu lho? Sampai penyelidikan polisi usai. Sampai kami kembali ke rumah tersebut. Lastri tidak tahu, bahwa itu semua atas perbuatanku yang mengabulkan doanya. “Sang Pencipta telah membalaskan dendam untuk kita Lastri?” Itu kata-kata terindah yang keluar dari rahim mulutku, untuknya. Lastri tak berkomentar. HENING.
Hari melipat hari. Gulungan ingatan. Detik jam mengubah segalanya; aku melihat Lastri kian seperti aku. Perangainya yang lembut mirip kebijakan ibu dalam berbagai hal; berubah total terbalik, aku heran, apa yang harus aku larang, sementara ucap dan lakuku pun bukan contoh yang baik bagi Lastri? Sempat aku berpikir, adakah aku dan Lastri, mewarisi darah psikopat, darah pemberangus, darah pemabuk, darah Dracula dari ibu atau bapak kandungku yang asli, berdasarkan cerita lelaki itu, yang selama ini kami anggap sebagai bapak kandungku sendiri? Entahlah.
Kini Lastri suka mabuk-mabukan, tak ada lagi ayat-ayat kauniah yang keluar dari mulutnya, bila menjelang senja. Lastri jadi rakus. Liar. Ganas. Serta sudah lupa antara hubungan darah, sampai akhirnya kami melambang-sari. Di sisi lain, kali pertama kami melakukan gituan, ada perasaan tak nyaman. Yah, takut-takut gitu deh, gelisahnya seperti kali pertama aku membunuh, tapi kesininya nich jadi ketagihan lho? Iiiih,… gereget deh aku: gereget, geret dan gereget,… banget: bila Lastri mulai merajuk.
SADAR. Oh, hampir saja lupa: di sisi lain, aku punya kebanggaan tersendiri, sebagai naluriku seorang lelaki; aku merasa bangga bisa menjebol gawang perawan bunga desa. Ya, awal-awalnya sich merasa dosa, ke sananya jalan tol. MEMPERAKTEKKAN SENGGAMA. HENING. Di malam yang lain setelah pesta koplo yang dibasuh nafsu purbawi, sebagai kesempurnaan pesta. Tanpa sadar, aku bercerita pada Lastri, bahwa akulah yang telah membunuh bapak dan ibu tiri kami. HENING.
Pagi hari nan bening, ketika kicau burung dan hangat mentari menyapa seluruh penghuni bumi bagian timur, bukan barat. Ketika aku sedang terlelap tidur, lagi asyik-asyiknya bermimpi dengan bidadari; sepasukan polisi mengepung rumah kami dan aku ditangkapnya. Tak ada celah untuk aku meloloskan diri dari kepungan polisi.
Di beranda rumah, ketika tanganku lemah dalam borgol; aku lihat, sesungging senyum seorang lelaki, yang selama ini kami anggap bapak, mekar di bibir Lastri. Apakah ia berusaha menenangkan pikiranku?
BERTERIAK. Agh, … bajingan kamu Lastri. Kau khianat. Bangsat. Durjana! Bukankah semua kematian mereka, atas keinginan doa-doamu selama ini? Bedebah! Jancuk! [10.12.08]
_________
Catatan: teks dalam naskah ini bisa dirubah oleh si penggarap, dengan tidak mengurangi benang merahnya.

MOBOKGRAZI (Jaman Edan Jilid Sembilan)
BAGIAN II: DAKWAAN RAKA Naskah Monolog dengan judul RAHIM KATA ATAWA GUGATAN DI BALIK TITIK (Antitesis I: Suara dari Bawah Tanah) Gugatan Raka terhadap atribut kemiskinan, generasi koplo, dan “insting pembunuh” yang dipaksakan penulis kepadanya.
DI SEBUAH RUANG BAWAH TANAH YANG SUMPEK, MENYERUPAI SUMUR BETON YANG LEMBAP. RUANG ISOLASI. RAKA TERDUDUK SEPERTI ANJING YANG MENUNGGU AJAL. DI SEKELILINGNYA, BUKU-BUKU DAN BOLPOIN BERJATUHAN DARI ATAS, SEPERTI SAMPAH YANG DIBUANG DARI DUNIA ATAS. RAKA MENGAMBIL BOLPOIN ITU, MENATAPNYA DENGAN KEBENCIAN YANG MURNI. PENCAHAYAAN STROBOSKOPIK SESEKALI MENYAMBAR, MEMPERLIHATKAN BAYANGAN LINTANG ISMAYA YANG MENGAWASI DARI BALIK JERUJI IMAJINER DI LANGIT-LANGIT
Besok, hari terindahmu, kata suara itu. Dua belas laras senapan akan mengecup dadaku dan aku disuruh menulis biografi? Hei, Lintang Ismaya! Kau yang duduk di atas sana dengan jari-jari bersih, merasa menjadi tuhan atas nasibku! Kau lempar buku ini seolah kau memberiku panggung, padahal kau hanya butuh akhir yang fantastik untuk memuaskan syahwat sastramu yang busuk itu! Kau ingin aku merangkum seluruh perihku ke dalam kertas ini agar kau bisa menjilidnya dan menjualnya sebagai mahakarya?
Semua orang berebut tentang sejarah, katamu dalam naskah ini? Persetan dengan sejarah! Kau tulis aku lahir dari rahim ibu yang disiplin ilmunya tinggi, keluarga kaya yang tak tertandingi di kota ini, tapi kau jodohkan dia dengan sopirnya sendiri. Kau buat ibuku sebinal itu, hamil di luar nikah, lalu kau jadikan lelaki tebal bibir itu sebagai pil tutup mulut. Kau yang merancang drama ini sejak awal, kan? Lalu, hopla! Kau sulap aku jadi anak sopir yang pening kepalanya karena kebanyakan makan micin dan janji palsu! Kau yang menyusun garis kemiskinan dan kemewahan ini hanya untuk melihat sejauh mana aku bisa menderita! Kau mengatur pertemuan sel telur dan sperma orang tuaku hanya untuk menciptakan tokoh pesakitan yang sempurna bagi panggungmu!
Lalu kau buat aku tumbuh di jalur generasi koplo. Tato, anting, rambut gimbal… kau beri aku atribut sampah agar kau punya alasan untuk membenarkan kegilaanku. Lihat tato di lenganku ini, Lintang! Kau yang menggambarnya dengan tinta murah, kan? Kau tulis ‘Broken Home’ tapi typo jadi ‘Broken Horm’. Sialan kau! Bahkan untuk menderita pun kau buat aku terlihat bodoh! Kau paksa aku bergoyang di bawah lampu remang jalur Pantura, menelan pil-pil warna-warni yang kau sebut sebagai ‘pelarian estetika’, padahal itu cuma racun tikus yang kau bungkus plastik! Kau sebut aku anak soleh? Anak soleh macam apa yang kau suruh menggorok leher ibu tiri sampai putus dan menikam bapak tujuh kali tepat di arah jantungnya? Mungkin kau pikir aku ini koki spesialis sate manusia, hah? Kau yang psikopat, Lintang! Kau yang menuntun tanganku memegang belati itu, lalu kau cuci tangan dengan menyebutnya sebagai bahasa nurani! Kau jadikan aku pembunuh agar kau tidak perlu mengotori tanganmu sendiri saat ingin menghapus karakter yang tidak kau sukai!
Lastri… Lastri Kinasih. Adikku yang paling kusayangi. Kau bilang namanya diambil dari kata Lestari dan Kasih—sifat Sang Pencipta yang mengabulkan doa. Doa yang mana, Lintang? Doa saat aku melihat bapak mau memperkosanya? Atau doa saat kami melambang-sari di bawah atap bocor setelah kematian ibu?
RAKA TIBA-TIBA BERGERAK LIAR, MERANGKAK DAN MENGERANG, MEMPERAGAKAN GERAK SENGGAMA YANG KASAR DAN PENUH KEGILAAN DI ATAS LANTAI BETON YANG LEMBAB
Iya, Lintang! Kau biarkan kami melakukan itu! Kau biarkan kami ketagihan di jalan tol dosa itu! Kau buat kami main kuda-kudaan di atas tumpukan dosa, lalu kau tepuk tangan dari kejauhan sambil sibuk mencari padanan kata ‘orgasme’ yang paling puitis! Kau buat hubungan darah ini menjadi cair seperti air tuba agar kau bisa menuliskan adegan panas yang menjijikkan ini! Kau menonton kami dari balik mesin tikmu, kan? Kau menikmati setiap erangan kami sebagai harmoni untuk diksimu yang cabul! Dan saat aku merasa bangga bisa menjebol gawang perawan bunga desa—yang lucunya, itu gawang adikku sendiri—kau buat aku lengah. Kau buat aku bercerita pada Lastri tentang pembunuhan itu di malam yang basah oleh nafsu purba. Dan di situlah letak bajinganmu yang paling nyata, Lintang…
Kau buat Lastri mengkhianatiku! Kau buat dia melapor ke polisi! Saat aku diborgol di beranda rumah, kau tuliskan: Aku lihat sesungging senyum mekar di bibir Lastri. Senyum itu bukan miliknya, Lintang! Itu senyummu! Kau yang tersenyum puas karena berhasil menutup kisahku dengan pengkhianatan yang paling dramatis! Kau menjebakku dalam sebuah lingkaran setan di mana aku harus menjadi monster agar Lastri bisa menjadi pahlawan, dan kau tetap menjadi tuhan yang maha tahu! Kau gunakan Lastri sebagai malaikat pencabut nyawaku, sementara kau sendiri tetap menjadi pengarang yang suci!
Kau bicara tentang ibu yang memakan kotoran bayi? Kau bicara tentang nilai religius yang ditanam kiai? Semua itu hanya bumbu agar tulisanmu terasa berisi. Padahal kau adalah Dracula yang sesungguhnya. Kau buat aku bicara pakai bahasa kiai di pagi hari, lalu bergaya preman terminal di malam hari. Kau pikir jiwaku ini stasiun radio yang bisa kau pindah-pindah frekuensinya sesukamu? Kau hisap darah dari luka-luka inses kami, kau kunyah duka dari kematian ibuku, lalu kau muntahkan menjadi monolog yang kau pamerkan di panggung-panggung mewah. Kau jadikan aib kami sebagai tiket masukmu ke dalam lingkaran sastrawan terhormat!
Besok lonceng gereja atau gema adzan tidak akan menolongku. Pasukan tembak itu adalah titik terakhir dari bolpoinmu. Tapi dengar ini, Lintang… kau mungkin bisa membunuh ragaku, tapi kau tidak akan pernah bisa memiliki rasa perihku yang asli. Kau hanya bisa meniru duka, tapi kau tidak pernah bisa merasakannya! Kau terjebak dalam menara gadingmu, memandang kami seperti semut yang kau adu di dalam botol! Kau hanyalah bapak kandungku yang pengecut, yang melahirlanku hanya untuk kau bantai demi tepuk tangan penonton!
Mampuslah kau dengan doa-doamu, Lintang Ismaya! Mampuslah kau dengan senyum Lastri-mu! Kalau kau bertemu malaikat nanti, titip salam, bilang ada satu tokohmu yang tatonya typo sedang menunggumu di gerbang neraka! Di neraka nanti, aku akan menunggumu untuk menulis ulang sejarah yang tidak pernah kau rasakan perihnya! Kita akan bertukar peran, Lintang! Aku yang akan memegang pena, dan kau yang akan merangkak di bawah kakiku meminta ampun atas setiap huruf yang kau tusukkan ke jantungku!
LAMPU PADAM SEKETIKA. HENING SEJENAK. TERDENGAR SUARA V.O (VOICE OVER) LINTANG ISMAYA YANG BERBISIK DATAR SEOLAH SEDANG MEMBACA ULANG TULISANNYA: “…dan raka pun mati dalam pelukanku yang dingin. selesai. oke, sekarang bagian lastri…” LALU DISAMBUT BUNYI MESIN TIK: CEKLEK! Catatan Khusus INSTRUKSI INI UNTUK MEMPERTEGAS BAHWA APA YANG BARU SAJA DITONTON ADALAH PROSES KREATIF LINTANG YANG SEDANG BERLANGSUNG SECARA REAL-TIME.

SITI TOMPEL
BAGIAN III: DAKWAAN LASTRI KINASIH Naskah Monolog dengan judul RAHIM KATA ATAWA FRAGMENTASI KINASIH (Antitesis II: Sabotase dari Beranda) Gugatan Lastri terhadap eksploitasi trauma perempuan dan pilihan untuk menghancurkan naskah demi sebuah kehendak bebas yang pedih.
DI SEBUAH BERANDA RUMAH TUA ALA ARSITEKTUR BELANDA YANG TAMPAK SEPERTI KERANGKA TULANG RAKSASA. LASTRI TIDAK BERDIRI, IA MEMATUNG. DI TANGANNYA, BOTOL MINUMAN KERAS ITU BUKAN SEKADAR KOSONG, TAPI BERDEBU—SEOLAH IA SUDAH BERADA DI SANA SELAMA SERIBU TAHUN. PENCAHAYAAN MENGGUNAKAN EFEK STROBOSKOPIK: KILATAN CAHAYA PUTIH YANG KASAR, MEMPERLIHATKAN SOSOK LINTANG ISMAYA DI KEGELAPAN YANG BERPINDAH-PINDAH POSISI SETIAP KALI LAMPU PADAM.
Kau puas, Lintang? Kau sudah mendapatkan akhir yang kau mau? Raka sudah kau kunci di sumur bawah tanah itu, menunggu peluru yang kau pesankan lewat naskahmu. Sekarang kau mau apa? Menungguku menangis agar kau bisa memanen air mataku menjadi puisi penutup yang indah? Kau pikir penderitaan adalah barang dagangan yang bisa kau pajang di etalase panggung? Kau duduk di sana, memoles setiap kata sifat, sementara aku di sini membusuk dalam kata kerja yang kau paksakan!
Kau yang menamakan aku Lastri Kinasih. Katamu, namaku adalah lambang sifat Sang Pencipta yang mengabulkan doa. Kau bilang aku adalah perwujudan ‘kun’ yang menjadi ‘fayakun’ di tanganmu. Tapi nyatanya, kau adalah mufassir yang tersesat dalam egomu sendiri! Kau hanya menjadikanku umpan. Kau ciptakan kecantikanku sebagai momok sekampung, kau biarkan bapak dan lelaki-lelaki asing itu mengejarku, hanya supaya kau bisa menghidupkan naluri membunuh Raka. Kau butuh darah sebagai pelumas mesin tikmu, maka kau gunakan tubuhku sebagai alasnya! Kau ciptakan aku bukan untuk hidup, tapi untuk hancur dengan cara yang paling artistik!
LASTRI TERTAWA GETIR, IA MULAI MENARI-NARI KECIL, MENIRUKAN GERAKAN BALERINA YANG PATAH. MUSIK LATAR ADALAH SUARA KETIKAN MESIN TIK YANG DI-DISTORSI MENJADI BUNYI DETAK JANTUNG YANG TIDAK STABIL
Ingat adegan itu, Lintang? Saat kau buat aku syok atas kematian ibu, lalu kau seret aku ke jalur depresi hingga aku tertawa sendiri. Kau paksa aku melihat bapak menikah lagi hanya sehari setelah jasad ibu dingin. Padahal kau tahu aku adalah anak yang menghafal ayat tentang memuliakan orang tua, tapi kau paksa jiwaku memuntahkan rasa hormat itu menjadi dendam! Kau yang merancang pengusiran itu! Kau yang membuat kami berjalan menyusuri jalan hitam dan hutan lambang, hanya supaya kami tidak punya pilihan selain masuk ke dalam skenario busukmu. Kau buat kami tersesat bukan karena kami kehilangan jalan, tapi karena kau memang tidak pernah menuliskan jalan pulang dalam naskahmu! Bagimu, tokoh yang selamat adalah tokoh yang membosankan, bukan?
Dan yang paling biadab… kau biarkan aku melambang-sari dengan Raka. LASTRI TIBA-TIBA MEREBAHKAN TUBUHNYA DI LANTAI BERANDA. IA MULAI MELAKUKAN GERAKAN TUBUH YANG MELIUK-LIUK, SEBUAH ADEGAN SENGGAMA IMAJINER YANG DILAKUKAN DENGAN INTENSITAS EROTIS YANG PENUH. NAFASNYA MEMBURU, MATANYA TERPEJAM SEOLAH MENIKMATI SETIAP SENTUHAN HANTU DARI DOSA ITU. Aku merintih, bukan karena sakit, tapi karena kenikmatan yang kau paksakan menjadi candu dalam naskahmu. (BERTERIAK) Aaaagh!
Kau yang menuliskan rasa tidak nyaman itu menjadi ketagihan, Lintang! Kau yang membuatku menjadi rakus, liar, dan ganas dalam dekapan abangku sendiri! Kau ingin membuktikan apa? Bahwa moralitas hanya selembar kertas yang gampang kau robek? Dulu, mulutku adalah tempat singgah puji-pujian pada Sang Pemilik Cahaya, tapi lihat aku sekarang! Aku nampak menikmati setiap inci kehancuranku dengan full erotis karena kau yang membuang ayat-ayat kauniah dari mulutku dan menggantinya dengan erangan nafsu purba! Kau paksa aku membaca ‘tanda-tanda kekuasaan-Nya’ lewat luka memar di pahaku! Kau ingin melihat bunga desa ini layu dan membusuk di tangan kakaknya sendiri dengan cara yang paling menjijikkan, kan? Supaya kau bisa bilang pada dunia: lihatlah betapa gelapnya jiwa manusia! Kau jadikan tubuhku laboratorium untuk eksperimen kegilaanmu!
LASTRI BANGKIT DENGAN NAFAS YANG MASIH TERSENGAL, IA TIDAK MERAPIKAN DASTER, IA MEMBIARKAN DIRINYA BERANTAKAN
Lalu kau tuliskan senyum itu. Senyum di bibirku saat Raka diborgol polisi. Kau bilang itu senyum karena doaku dikabulkan? Kau bilang itu senyum karena dendamku terbalas? Bukan, Lintang! Itu adalah senyum muak! Itu adalah sabotase! Aku melapor ke polisi bukan untuk keadilan—karena keadilan tidak ada dalam kamusmu—tapi untuk merusak naskahmu! Aku mengembalikan ‘amanah’ hidup ini padamu dengan cara yang paling hancur!
Aku ingin Raka mati agar dia berhenti menjadi bonekamu! Lebih baik dia ditembus timah panas daripada terus-menerus ditembus oleh fantasi gilamu! Aku tersenyum karena akhirnya aku berhasil menghentikan pesta koplo dan darah yang kau sutradarai ini! Aku memilih kehancuran yang nyata daripada keberadaan yang kau karang-karang!
Kau bicara tentang kesakralan? Kau bicara tentang posisi mulia seorang ibu? Tapi kau sendiri menguliti kami tanpa ampun. Kau adalah bapak kandung yang lebih kejam dari sopir ibu itu. Kau melahirkan kami dari rahim kata-katamu hanya untuk kau jadikan tumbal panggung. Kau Dracula yang menghisap trauma kami untuk mengisi tinta bolpoinmu yang kering! Berapa banyak lagi Lastri yang harus kau perkosa dengan kata-katamu agar kau merasa menjadi penulis besar?
LASTRI MEROBEK UJUNG DASTERNYA, MELEMPARKANNYA KE ARAH KEGELAPAN. IA MENATAP KE ARAH TEMPAT LINTANG BERSEMBUNYI. SUARANYA KINI DATAR, DINGIN, DAN HAMPA
Tulis ini, Lintang! Tulis bahwa Lastri Kinasih tidak butuh kasihmu! Besok, saat Raka mati, aku akan tetap hidup sebagai saksi bahwa kau adalah pencipta yang gagal. Neraka ini bukan tentang api, Lintang. Neraka adalah fakta bahwa aku harus mengulang semua ini selamanya karena kau tidak punya keberanian untuk menulis kata “Selesai” pada penderitaanmu sendiri. Kau tawarkan sabar yang hambar, sementara kau sendiri berpesta di atas naskah yang amis!
Kau mengurungku dalam tatapan penonton yang lapar akan aib. Kau membuatku menjadi tontonan, menjadikanku “yang lain”. Tapi ingat, di hadapan keheningan yang abadi nanti, naskahmu akan terbakar dan kau akan gemetar menyadari bahwa kau hanyalah tawanan dari bayanganmu sendiri. Mampuslah kau dengan naskah-naskahmu yang sakral itu. Aku akan tetap tersenyum, tapi kali ini senyumku adalah ‘istidraj’ bagimu—sebuah kelonggaran yang akan menjeratmu dalam azab yang kau ketik sendiri! Selesai, Lintang! Selesai!
LASTRI MEMBALIKKAN BADAN, TAPI IA TIDAK BERJALAN KE KEGELAPAN. IA BERHENTI DI BATAS PANGGUNG, MENATAP PENONTON SATU PER SATU. LAMPU PADAM PERLAHAN, MENYISAKAN SUARA MESIN TIK YANG TERUS BERBUNYI DI KEGELAPAN TOTAL, SEMAKIN CEPAT, LALU TIBA-TIBA BERHENTI. TERDENGAR KEMBALI SUARA V.O LINTANG ISMAYA DENGAN NADA YANG SEMAKIN TERTEKAN DAN BERGETAR: “…lalu lastri memilih kehancuran yang nyata. ya, itu lebih artistik. berikutnya… pembelaanku.” BUNYI MESIN TIK: CEKLEK!

SITI
BAGIAN IV: PEMBELAAN LINTANG ISMAYA Naskah Monolog dengan judul RAHIM KATA ATAWA PEMBELAAN ISMAYA (Antitesis III: Rahim Sang Penderita) Pembelaan diri sang penulis yang merasa dirinya adalah martir bagi kenyataan, terjebak di antara kewajiban mencatat dan rasa bersalah yang menghujam.
PANGGUNG HANYA BERISI SEBUAH MEJA KAYU TUA DENGAN MESIN KETIK ATAU TUMPUKAN KERTAS, DAN SATU LAMPU GANTUNG YANG BERGOYANG. LINTANG ISMAYA BERDIRI DI KEGELAPAN, HANYA TANGANNYA YANG TERLIHAT SESEKALI SAAT MENYULUT ROKOK. SUARANYA TENANG, BERAT, NAMUN MENGANDUNG GETARAN PERIH YANG DALAM. DI DINDING BELAKANG, TERPAMPANG BAYANGAN SAMAR RAKA DAN LASTRI YANG BERGERAK SEPERTI SLIDE FILM RUSAK.
Lemparkan terus sumpah serapah itu, Raka. Muntahkan seluruh nanahmu, Lastri. Aku mendengar semuanya. Aku mendengar setiap makian yang kalian lemparkan dari balik jeruji dan beranda rumah Belanda itu. Kalian menyebutku bapak yang pengecut? Kalian menyebutku Dracula yang menghisap trauma? Kalian pikir aku duduk di sini dengan tawa kemenangan saat merangkai kehancuran kalian? Aku tidak sedang berpesta di atas kertas. Aku sedang melakukan otopsi atas peradaban yang gagal kalian miliki. Penulis bukan pencipta penderitaan; kami adalah kurator dari tragedi yang kalian pilih sendiri.
Sekali lagi aku tegaskan: Aku tidak sedang berpesta di atas kertas. Aku sedang melakukan otopsi atas peradaban yang gagal kalian miliki. Penulis bukan pencipta penderitaan; kami adalah kurator dari tragedi yang kalian pilih sendiri.
LINTANG MELANGKAH SEDIKIT KE ARAH CAHAYA, MENAMPAKKAN WAJAH YANG LELAH, MATA YANG SEMBAP KARENA KURANG TIDUR
Kalian pikir aku senang saat mengetik adegan belati itu menghujam jantung bapakmu? Kalian pikir jemariku tidak gemetar saat aku memaksakan adegan melambang-sari itu terjadi di antara kalian berdua? Aku tidak sedang bermain menjadi Tuhan yang kejam. Aku sedang menjadi cermin yang kalian benci karena ia memantulkan kejujuran yang terlalu telanjang. Aku adalah budak dari kenyataan yang kalian lalui, dan naskah ini adalah penjara yang kubangun dengan tanganku sendiri untuk menemani kesepian kalian! Aku hanyalah juru ketik bagi suara-suara sumbang di tepian sejarah yang selalu dianggap bising oleh telinga para orang suci.
Kalian menggugatku karena aku mengeksploitasi luka? Ketahuilah, aku tidak menciptakan luka itu. Luka itu sudah ada di banyak ruang dan peristiwa, di saban sudut dunia, di gang-gang sempit tempat doa-doa kalian tersangkut di genting bocor. Aku hanya memungutnya. Aku menjahitnya menjadi naskah agar dunia tahu bahwa kalian ada! Tanpa tinta ini, kalian hanya akan menjadi statistik di koran pagi yang dibuang ke tempat sampah tanpa pernah sempat bicara! Dunia lebih kejam dari aku, Raka! Dunia akan membiarkanmu mati tanpa nama, tapi aku memberimu kematian yang diingat selamanya! Kata-kataku adalah satu-satunya upacara pemakaman yang layak bagi mereka yang dibuang oleh struktur sosial yang tidak pernah menginginkan kalian lahir.
IA MENGAMBIL SELEMBAR KERTAS, MEREMASNYA KUAT-KUAT
Raka, kau bilang aku bapak kandungmu yang pengecut. Jika aku pengecut, aku akan memberimu akhir yang bahagia, sebuah fatamorgana yang menipu—tapi aku memilih jujur. Aku memilih menempatkanmu di hadapan dua belas regu tembak karena memang begitulah dunia menghakimi mereka yang mencari keadilan dengan cara yang salah. Aku tidak membunuhmu, Raka. Dunia yang membunuhmu, aku hanya mencatat detik-detik kematianmu agar ia menjadi abadi! Kau ingin aku berbohong? Kau ingin aku menuliskan malaikat turun menyelamatkanmu saat kau sedang menggorok leher? Tidak, Raka! Keindahan karyaku adalah kepatuhanku pada pahitnya takdir! Seni yang tulus tidak menjanjikan keselamatan, ia hanya menjanjikan pemahaman. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi aku bisa memastikan bahwa hancurmu tidak sia-sia.
Dan kau, Lastri… Kinasihku. Kau bilang senyummu adalah kutukan untukmu? Kau salah. Senyum itu adalah satu-satunya caraku memberimu kekuatan di tengah kehancuran. Aku memberimu keberanian untuk mengkhianati Raka bukan karena aku ingin kau jadi penjahat, tapi karena aku ingin kau berhenti menjadi korban! Aku ingin kau memiliki satu tindakan prerogatif yang murni milikmu sendiri, meski itu harus menghancurkan abangmu. Aku memberimu ‘kehendak bebas’ di saat naskahmu sudah buntu, meski aku tahu kau akan menggunakan kebebasan itu untuk meludah ke wajahku! Kehendak bebas adalah kutukan paling indah yang kuberikan padamu—sebuah keberanian untuk berkata ‘tidak’ pada skenario moralitas yang membosankan.
LINTANG DUDUK DI KURSI, MENUNDUK DALAM, SUARANYA NYARIS BERBISIK
Aku adalah penderita yang paling sunyi di sini. Kalian hanya menanggung satu takdir, sementara aku menanggung ribuan takdir Lastri dan Raka lainnya di kepalaku. Setiap kali aku menuliskan “Selesai”, ada bagian dari jiwaku yang ikut mati bersama kalian. Kalian pikir mengetik adalah pekerjaan jari? Bukan! Mengetik adalah memindahkan nanah dari hatiku ke atas kertas putih ini agar ia tidak membusuk di dalam dada! Setiap ketukan tuts mesin tik ini adalah hantaman martil yang menghancurkan tempurung kepalaku sendiri!
Aku adalah perfeksionis yang sedang menjahit kain kafanku sendiri dengan benang dari serat sarafku sendiri. Kalian adalah anak-anakku yang lahir dari rahim luka, dan setiap huruf yang kuketik adalah paku yang kutancapkan ke jantungku sendiri! Jangan kau kira aku tertawa saat kau sekarat, Raka! Saat membayangkan peluru itu menembus dadamu di adegan terakhir yang aku hapus, aku pun tersedak darah di meja ini! Saat kau merasa kotor, Lastri, aku merasa jiwaku bernanah dan bau bangkai! Aku tidak sedang menjual aib kalian, aku sedang menjajakan luka-lukaku sendiri yang kupinjamkan pada tubuh kalian agar kalian punya alasan untuk tetap hidup di atas panggung!
Hujatlah aku. Karena memang itulah fungsinya seorang penulis; menjadi tempat pembuangan bagi segala perih yang tak berani kalian akui sebagai bagian dari diri kalian. Aku terima kutukanmu, Lastri. Aku terima makianmu, Raka. Karena di dalam rahim kata-kataku, kalian tidak akan pernah benar-benar mati. Kalian akan terus hidup, terus menggugat, dan terus tersenyum… bahkan saat aku sudah membusuk di bawah sejarah yang aku tulis sendiri. Asal kalian tahu satu hal, bahwa menulis adalah cara paling egois untuk menjadi orang lain, sekaligus cara paling menyakitkan untuk tetap menjadi diri sendiri. HENING Satu hal yang harus kalian tahu bahwa aku tidak sedang mengeksploitasi luka kalian; aku sedang membedah lukaku sendiri lewat nama kalian.
Ya, kalian benar bahwa aku adalah Tuhan yang paling malang; yang harus membunuh ciptaannya berulang kali hanya agar mereka bisa dikenang sebagai kebenaran yang abadi! Neraka bagiku bukan karena kalian membenciku, tapi karena aku harus terus menuliskan penderitaan kalian agar kalian tetap bernafas di dalam ingatan orang lain! Karya ini adalah persembahan bagi kemanusiaan yang selalu menolak untuk dilihat. Jika kalian merasa sakit, itu artinya aku berhasil mengembalikan urat saraf kalian yang sempat dimatikan oleh kenyataan.
LINTANG KEMBALI KE MESIN KETIKNYA, MENGETIK SATU KATA TERAKHIR DENGAN BUNYI DENTUMAN YANG KERAS. LAMPU PADAM.

RAJAH DILATJILJALAHAT
BAGIAN V: PERJAMUAN TERAKHIR Naskah Drama dengan judul RAHIM KATA ATAWA PERJAMUAN TERAKHIR (Sintesis: Neraka Adalah Orang Lain) Pertemuan ketiga tokoh dalam ruang putih steril. Titik di mana mereka menyadari bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari siklus pengulangan yang abadi. CATATAN KHUSUS: sebenarnya naskah ini bisa juga dimonologkan jadi konsep dalang, asalkan aktornya kuat.
TOKOH:
> Raka Buana: Mantan narapidana mati. Tubuh penuh tato imajiner. Jiwanya kasar, getir, namun menyimpan kerapuhan generasi koplo yang ceroboh.
> Lastri Kinasih: Adik Raka. Cantik dengan aura gelap. Anak soleh yang brutal akibat trauma; menyimpan kemarahan tenang yang mematikan.
> Lintang Ismaya: Penulis naskah paruh baya. Intelektual, analitis, namun rapuh dan dihantui dosa kreatif sebagai “pencipta”.
SITUASI PANGGUNG: Sebuah ruang putih yang steril dan tak berujung. Tanpa pintu, tanpa jendela. Suasana mencekam, steril, dan metafisika.
FRAGMENT 1: DAKWAAN RAKA (Ruang putih steril. RAKA merangkak seperti anjing. Bolpoin dan kertas jatuh dari atas sebagai sampah imajiner)
Dua belas laras senapan akan mengecup dadaku dan aku disuruh menulis biografi? Lalu, hopla! Kau sulap aku jadi anak sopir yang pening kepalanya karena kebanyakan makan micin dan janji palsu! Kau mengatur pertemuan sel telur dan sperma orang tuaku hanya untuk menciptakan tokoh pesakitan yang sempurna bagi panggungmu! Kau jadikan aku pembunuh agar kau tidak perlu mengotori tanganmu sendiri saat ingin menghapus karakter yang tidak kau sukai! Mungkin kau pikir aku ini koki spesialis sate manusia, hah? Lihat tato di lenganku ini, Lintang! Kau tulis ‘Broken Home’ tapi typo jadi ‘Broken Horm’. Bahkan untuk menderita pun kau buat aku terlihat bodoh! Kau menonton kami dari balik mesin tikmu, kan? Kau menikmati setiap erangan kami sebagai harmoni untuk diksimu yang cabul! Kau menjebakku dalam sebuah lingkaran setan di mana aku harus menjadi monster agar Lastri bisa menjadi pahlawan! Kau hanya bisa meniru duka, tapi kau tidak pernah bisa merasakannya! Kita akan bertukar peran, Lintang! Aku yang akan memegang pena, dan kau yang akan merangkak di bawah kakiku meminta ampun! Kalau kau bertemu malaikat nanti, titip salam, bilang ada satu tokohmu yang tatonya typo sedang menunggumu di gerbang neraka!
STROBOSKOPIK. SUARA MESIN TIK: CEKLEK! CEKLEK! RAKA menghilang dari panggung
FRAGMENT 2: DAKWAAN LASTRI (Ruang putih steril. LASTRI mematung, menari patah dengan daster lusuh)
Kau pikir penderitaan adalah barang dagangan? Kau duduk di sana memoles kata sifat, sementara aku membusuk dalam kata kerja yang kau paksakan! Kau bilang namaku perwujudan ‘kun’ yang menjadi ‘fayakun’ di tanganmu, tapi nyatanya kau mufassir yang tersesat dalam egomu sendiri! Kau ciptakan aku bukan untuk hidup, tapi untuk hancur dengan cara yang paling artistik! Kau buat kami tersesat karena kau memang tidak pernah menuliskan jalan pulang! Dulu, mulutku adalah tempat singgah puji-pujian pada Sang Pemilik Cahaya, tapi kau paksa aku membaca ‘tanda-tanda kekuasaan-Nya’ lewat luka memar di pahaku! Kau jadikan tubuhku laboratorium untuk eksperimen kegilaanmu! Itu adalah sabotase! Lebih baik Raka ditembus timah panas daripada terus-menerus ditembus oleh fantasi gilamu! Aku mengembalikan ‘amanah’ hidup ini padamu dengan cara yang paling hancur! Aku akan tetap tersenyum, tapi kali ini senyumku adalah ‘istidraj’ bagimu—sebuah kelonggaran yang akan menjeratmu dalam azab yang kau ketik sendiri!
STROBOSKOPIK. SUARA MESIN TIK: CEKLEK! CEKLEK! LASTRI menghilang dari panggung
FRAGMENT 3: PEMBELAAN LINTANG (Ruang putih steril. LINTANG berdiri di tengah kepulan asap rokok)
Kalian pikir aku duduk di sini dengan tawa kemenangan? Aku adalah budak dari kenyataan, dan naskah ini adalah penjara yang kubangun untuk menemani kesepian kalian! Aku tidak sedang berpesta di atas kertas. Aku sedang melakukan otopsi atas peradaban yang gagal kalian miliki. Aku hanyalah juru ketik bagi suara-suara sumbang di tepian sejarah yang selalu dianggap bising oleh telinga para orang suci. Dunia lebih kejam dari aku, Raka! Dunia akan membiarkanmu mati tanpa nama, tapi aku memberimu kematian yang diingat selamanya! Seni yang tulus tidak menjanjikan keselamatan, ia hanya menjanjikan pemahaman. Aku memberimu ‘kehendak bebas’ di saat naskahmu sudah buntu, meski aku tahu kau akan menggunakan kebebasan itu untuk meludah ke wajahku! Kehendak bebas adalah kutukan paling indah yang kuberikan padamu—sebuah keberanian untuk berkata ‘tidak’ pada skenario moralitas yang membosankan. Kalian adalah anak-anakku yang lahir dari rahim luka! Neraka bagiku bukan karena kalian membenciku, tapi karena aku harus terus menuliskan penderitaan kalian agar kalian tetap bernafas di dalam ingatan orang lain! Karya ini adalah persembahan bagi kemanusiaan yang selalu menolak untuk dilihat!
STROBOSKOPIK. LINTANG menghilang dari panggung. PANGGUNG GELAP. HENING
FRAGMENT 4: PERJAMUAN TERAKHIR (The Realization. Ruang putih steril. Lampu perlahan nyala. Ketiga tokoh ada di panggung. RAKA dan LASTRI mencoba lari ke arah cahaya namun terlempar kembali)
SITUASI PANGGUNG: SEBUAH RUANG PUTIH STERIL TANPA PINTU. DI TENGAH PANGGUNG TERDAPAT TUMPUKAN KERTAS YANG SANGAT BESAR ATAU GUNUNGAN KERTAS SEBAGAI SIMBOL NASKAH YANG SUDAH DIBUANG. RAKA DAN LASTRI MERINGKUK DI SUDUT, SEMENTARA LINTANG BERADA DI TENGAH TUMPUKAN KERTAS TERSEBUT. DI TENGAH TUMPUKAN KERTAS ITU ADA SEBUAH MEJA DAN KURSI TUA DENGAN MESIN TIK. LINTANG DUDUDUK DENGAN POSISI BERADA DI TENGAH MEJA, SAMBIL MENGETIK DENGAN RITME YANG KONSTAN.
LASTRI:
TERENGAH-ENGAH Kenapa? Kenapa kita masih di sini? Pintu itu… pintunya terkunci!
RAKA DAN LASTRI MENCOBA BERLARI KE ARAH CAHAYA PUTIH DI UJUNG PANGGUNG, TAPI MEREKA TERSANDUNG DAN JATUH TERSUNGKUR DI ATAS TUMPUKAN KERTAS. MEREKA TERJEBAK OLEH TUBUH MEREKA SENDIRI YANG TERBUAT DARI KERTAS DAN KATA-KATA.
LINTANG:
TENANG Karena aku belum menulis kata “Selesai” di dalam jiwaku. Kalian bebas dari kertas, tapi kalian tidak pernah bebas dari ingatanku.
RAKA:
KETAKUTAN Jadi… kita akan terus begini? Kau menonton kami, dan kami menghujatmu? Selamanya?
LINTANG:
Neraka bukan api, Raka. Neraka adalah fakta bahwa kita harus saling menatap dan saling menguliti selamanya tanpa pernah bisa memejamkan mata. Ayo… kita mulai lagi dari adegan pertama.
LINTANG MENGAMBIL SELEMBAR KERTAS BARU DARI LANTAI, MEMASUKKANNYA KE DALAM MESIN TIK DENGAN GERAKAN MEKANIK. RAKA DAN LASTRI KEMBALI KE POSISI AWAL MEREKA SEPERTI PADA BAGIAN I (EFEK DÉJÀ VU). LAMPU PADAM PERLAHAN SAAT BUNYI MESIN TIK BERDENTUM RITMIS: CEKLEK! CEKLEK! CEKLEK! Fade-in cepat ke Fragmen 5 sebagai loop.
FRAGMENT 5: RAHIM KATA ATAWA PERJAMUAN TERAKHIR (The Loop. Setting flashback: Raka meringkuk, Lastri berdiri, Lintang mengetik di meja kayu.) SITUASI PANGGUNG: Sebuah ruang putih yang steril dan tak berujung. Tanpa pintu, tanpa jendela. Di tengah terdapat sebuah meja kayu tua dengan mesin tik kuno. Raka meringkuk di sudut kiri (seperti di sel), Lastri berdiri di sudut kanan (seperti di beranda), dan Lintang Ismaya duduk di meja tengah, mengetik dengan ritme yang konstan. CATATAN KHUSUS: gunungan kertas menghilang.
RAKA:
TERBANGUN Di mana regu tembak itu? Kenapa rasanya hanya seperti jatuh ke dalam ember cat putih? PADA LINTANG Kau! Penulis sialan! Kau pikir jiwaku ini stasiun radio yang bisa kau pindah-pindah frekuensinya sesukamu? Kau belum puas melihatku mati?
LASTRI:
TERTAWA GETIR Ini neraka yang kau susun, kan Lintang? Kau tawarkan sabar yang hambar, sementara kau sendiri berpesta di atas naskah yang amis! Lihat aku! Kau buat aku berdiri di sini selamanya dengan memori tentang bapak dan abangku!
LINTANG:
Ini bukan adegan tambahan. Ini adalah jeda di antara dua kalimat. Kita berada di ruang yang tidak butuh bolpoin. Di sini, kau bukan lagi sekadar karakter, tapi aku pun bukan lagi penguasa.
RAKA:
MENGGEBRAK MEJA Jawab! Kau buat kami main kuda-kudaan di atas tumpukan dosa, lalu kau tepuk tangan dari kejauhan sambil sibuk mencari padanan kata ‘orgasme’ yang paling puitis! Kau yang merancang drama ini sejak awal!
LASTRI:
MELIUK EROTIS Lihat! Ini yang kau tulis! Kau paksa aku membaca ‘tanda-tanda kekuasaan-Nya’ lewat luka memar di pahaku! Kau jadikan tubuhku laboratorium untuk eksperimen kegilaanmu!
LINTANG:
BANGKIT TAPI TUBUHNYA NAMPAK TERLIHAT LELAH Diam! Aku melakukannya agar dunia tahu betapa perihnya kalian! Menulis adalah cara paling egois untuk menjadi orang lain, sekaligus cara paling menyakitkan untuk tetap menjadi diri sendiri. Kalian adalah anak-anakku yang lahir dari rahim luka!
RAKA:
MENCENGKERAM KERAH BAJU LINTANG Kau Dracula! Kau menghisap trauma kami! Kau gunakan Lastri sebagai malaikat pencabut nyawaku, sementara kau sendiri tetap menjadi pengarang yang suci!
LASTRI:
Tuhan, lihatlah dia! Penafsir kehendak-Mu yang palsu! Hukumlah dia dengan kata-katanya sendiri! MULUTNYA KOMAT KAMIT
LINTANG:
BERLUTUT Hukumlah aku… Tapi dengarlah! Aku memilih menempatkanmu di hadapan regu tembak, Raka, karena aku memilih jujur pada pahitnya takdir! Seni tidak menyelamatkanmu, Raka, ia hanya memastikan bahwa hancurmu tidak sia-sia!
RAKA:
DINGIN Tidak ada penonton di sini. Hanya ada kita. Kau mengurung kami dalam tatapan penonton yang lapar akan aib, menjadikanku “yang lain”, tapi sekarang kau terkunci bersama kami dalam kehampaan ini.
LASTRI:
Senyumku saat kau diborgol itu… itu sabotase! Aku memilih kehancuran yang nyata daripada keberadaan yang kau karang-karang! Biarkan kami pergi dari kepalamu!
LINTANG:
Jangan pergi… jika kalian pergi, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ruang kosong yang bisu…
RAKA:
Selesai, Lintang Ismaya. Mampuslah kau dengan naskah-naskahmu yang sakral itu!
RAKA DAN LASTRI MELANGKAH KE CAHAYA. LEDAKAN STROBOSKOPIK MELEMPARKAN MEREKA KEMBALI KE POSISI SEMULA. Catatan Khusus: LIHAT PANDUAN PADA FRAGMENT 4: PERJAMUAN TERAKHIR [RAKA DAN LASTRI MENCOBA BERLARI KE ARAH CAHAYA PUTIH DI UJUNG PANGGUNG, TAPI MEREKA TERSANDUNG DAN JATUH TERSUNGKUR DI ATAS TUMPUKAN KERTAS. MEREKA TERJEBAK OLEH TUBUH MEREKA SENDIRI YANG TERBUAT DARI KERTAS DAN KATA-KATA. ] JADIKAN EFEK DÉJÀ VU UNTUK PENONTON.
LASTRI:
TERENGAH Kenapa? Kenapa kita masih di sini?
LINTANG:
Pintu ini tidak pernah ada, karena aku sendiri yang menguncinya dari dalam rahim kata. Di sini, tidak ada hari esok. Hanya ada pengulangan. MEMBUNGKUK KE LANTAI SAMBIL MENGAMBILK KERTAS
RAKA:
TERENGAH-ENNGAH Jadi… kita akan terus begini? Selamanya?
LINTANG:
Neraka bukan api, Raka. Neraka adalah fakta bahwa kita harus saling menatap selamanya. Ayo… kita mulai lagi dari adegan pertama. SAMBIL MEMASUKAN KERTAS BARU KE DALAM MESIN TIK.
LAMPU MEREDUP. LINTANG MENGETIK. RAKA MERINGKUK. LASTRI MERAPIKAN DASTER. SUARA MESIN TIK KIAN KERAS BERBUNYI CEKLEK. CEKLEK. CEKLEK. CEKLEK. GELAP TOTAL. Fade-out.












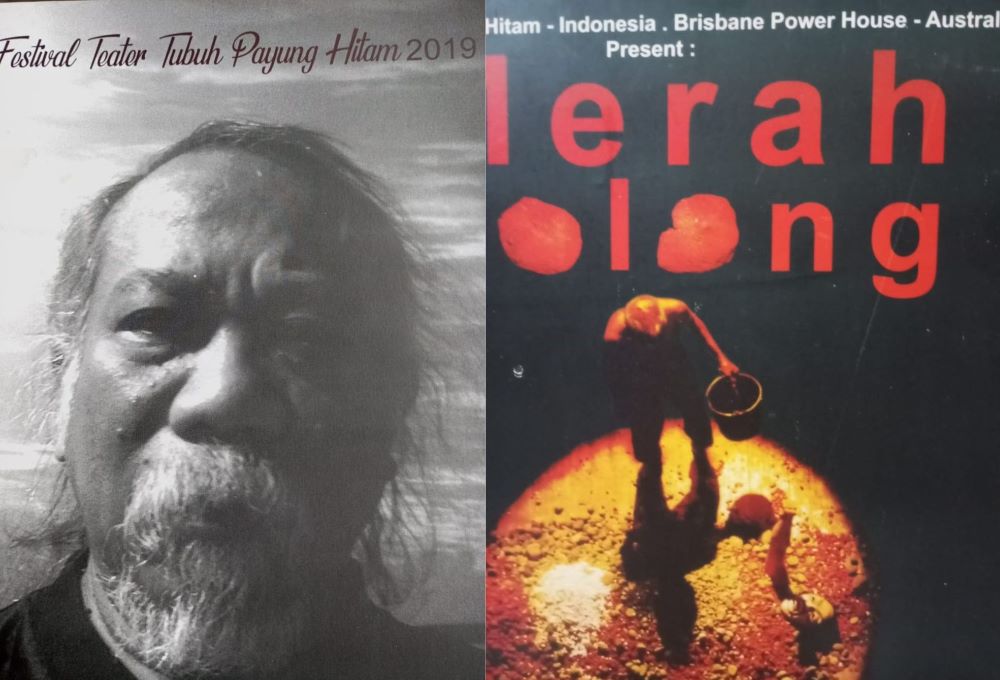

One thought on “PANTALOGI RAHIM KATA ATAWA GUGATAN DARI BALIK TITIK”