DOM Dan Orang Mati karya & sutradara Rachman Sabur. dok. TPH.
Pertama kali saya menyaksikan pementasan teater Payung Hitam ini terjadi pada Agustus 1997 di Teater Arena Taman Budaya Solo. Waktu itu mereka pentaskan karya terbaru sutradara Rachman Sabur, “Merah Bolong Putih Doblong Hitam”. Setiap malam ruang teater penuh, dan setiap malam para penonton seperti menahan nafas jadinya menyaksikan pementasan teater tanpa kata tapi kaya dengan gerak tubuh, bunyi dan lambang. Dan ternyata bukan hanya di Solo banyak orang tertarik untuk menonton dan terkesiap, serta terangsang pikirannya sesudah menyaksikannya. Ternyata teater Payung Hitam kemudian diundang pentas “Merah Bolong” di tempat-tempat lain, seperti di Teater Utan Kayu, Jakarta, di Festival Seni Surabaya, di Selasar Sunaryo, Bandung.

Habis menonton pementasan “Merah Bolong”, saya juga jadi sadar bahwa teater Payung Hitam mulai dikenal di antara kalangan cendikiawan, mahasiswa, Seniman, budayawan, dan pengamat teater Nasional terutama lewat karya penulis Austria Peter Handle, ” Kaspar”, yang pertama-tama mereka pentaskan di Bandung, Solo, dan Surabaya, di antara tahun 1994 dan 1996.Pertunjukan-pertunjukan “Kaspar” Payung Hitam dilaporkan di berbagai media massa, baik nasional maupun di daerah-daerah tempat pertunjukan itu diadakan. Dan ternyata banyak komentar menilai bahwa pementasan Payung Hitam yang satu ini mampu menyampaikan beberapa persoalan dari kehidupan nyata Indonesia secara jitu. Yang menarik, pementasan itu bukan tergolong realistis, malah dianggap dan dinilai sangat eksperimental. Anehnya teater yang eksperimental jarang dapat perhatian dan sambutan umum seluas ini. Barangkali, “Mini Kata” Rendra pada akhir tahun enam puluhan merupakan satu-satunya contoh yang kuat dalam hal ini. Tentu saja beberapa karya Putu Wijaya, Teater Sae, dan Teater Kubur pernah disoroti beberapa media massa juga, walaupun tidak dengan jumlah berita, intensitas, dan gema”KASPAR” Payung Hitam ini.
Keberhasilan teater Payung Hitam dalam merebut perhatian media massa dan banyak di antara kaum cendikiawan, seniman, dan mahasiswa, harus dilihat sebagai kemampuan Rachman Sabur dan kawan-kawan nya untuk meramu sebuah teater yang bisa menari dengan lincah di antara ketegangan berbagai wacana. Dengan mencari sebuah keseimbangan gerak (yang takarannya selalu berubah menurut keadaan praktek seni dan kehidupan masyarakat pada saat setiap pementasan), di antara pesan yang jelas dan bentuk yang penuh nilai seni atau puitis (betapa gelap unsur-unsur puitis itu) yang mengandung kemungkinan banyak tafsiran, di antara persoalan sosial mutakhir dan kehadiran sosok manusia belum tentu sebagai kepribadian individu yang terperinci, tetapi yang jelas, sebagai seorang manusia yang ada kehadiran jasmani, yang menderita sendiri, di antara bentuk teater yang berisi unsur budaya/seni tradisional dan yang tak terlalu peduli dengan semua itu, asal bentuknya kreatif, eksperimental dan segar. Dengan tarian yang gesit, bergerak dari satu pementasan ke pementasan yang lain, yang masing-masing menitik-beratkan ramuan unsur-unsur ini yang berbeda. Teater Payung Hitam selama tahun-tahun 90-an mampu mencetak beberapa pertunjukan yang sangat mengena perasaan dan pikiran para penonton. Dalam arti ini, pertunjukan-pertunjukan seperti “Kaspar” (1994-1996), “Merah Bolong Putih Doblong Hitam” (1997), dan mungkin perlu ditambah, “Kata Kita Mati” (1998) dan “Tiang 1/2 Tiang” (1999), amat cocok dilihat sebagai pertunjukan teater yang tepat bagi zaman Akhir Orde Baru dan awal “Reformasi”.
Untuk memahami jati diri Payung Hitam dengan segala keberhasilannya, kita mestinya ingat beberapa hal. Teater Nasional dilahirkan sebagai salah satu sarana untuk menyadarkan dan mengerahkan para anak bangsa supaya ikut berjuang mewujudkan negara merdeka yang modern. Ada yang merasa bahwa perinci-perinci masalah politik dan semangat keteguhan hati dalam berjuang mengatasi ketimpangan kekuasaan merupakan bahan yang harus diangkat dalam teater untuk menyuluti semangat dan menyadarkan para penonton. Yang jelas, Rachman Sabur, Tony Broer, dan anggota-anggota Payung Hitam yang lain termasuk tradisi ini dalam arti, selalu sangat prihatin atas keadaan masyarakat Indonesia dan mau memberi sumbangan dalam bentuk teater yang dapat menyampaikan pengamatan dan kecemasan mereka.
Teater Payung Hitam, disamping sudah mementaskan karya-karya para perintis teater Nasional yang eksperimental pada zaman Orde Baru, seperti : Putu Wijaya, Arifin C Noer, dan Saini KM, kelompok teater Payung Hitam juga sering mementaskan karya-karya modernis dan absurdis dari Eropa : WB Yeats, T.S. Elliot, Ionesco, Genet,Pinter, A. Camus, Beckett, Chekov, Guerdon, Aristophanes.
Pada akhir-akhir tahun 80-an dan awal tahun-tahun 90-an itu semua mulai berubah. Dalam teater suatu arus eksperimental baru mulai terasa, meskipun tidak menolak unsur tradisi dalam eksperimen sudah mencurigakan manfaatnya unsur-unsur tradisi itu, sebagian karena “budaya” dan “kepribadian” yang khas Indonesia begitu dikoar-koarkan oleh para ideolog Orde Baru.
Di Jakarta arus teater ini dipelopori Teater Sae dan Teater Kubur kelompok teater searus dengan Sae dan Kubur lebih mementingkan bentuk “instalasi gagasan” istilah Afrizal Malna. Kelompok-kelompok ini bermunculan, berdampingan dengan babak baru gerakan mahasiswa yang cenderung kerjasama dengan petani, buruh dan kaum tertindas pada umumnya.
Kaspar
Pada bulan Juni 1994, majalah Tempo, Detik, dan Editor dibredel Orde Baru. Pertunjukan ” Kaspar” yang pertama kali dilangsungkan awal bulan September 1994, jelas dimaksudkan untuk mengungkapkan perasaan sakit hati yang dialami Rachman Sabur dan kawan-kawannya pada saat pembredelan. Ternyata harapan Payung Hitam terhadap naskah Peter Handke itu sangat tepat untuk mendapat sambutan luar biasa dari khalayak penonton teater Nasional Indonesia pada saat itu. Berangkat dari naskah asli Handke yang secara abstrak dan lucu melukiskan tema universal. Bagaimana kita menjadi manusia dengan potongan khas yang ditentukan lewat proses belajar menguasai peraturan-peraturan pemakaian bahasa, teater Payung Hitam membuktikan diri mampu untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang sangat kontekstual bagi Indonesia pada titik sejarah waktu soal ” apa yang bisa dibicarakan, dan oleh siapa”, menjadi bahan wacana umum yang hangat. Dalam hal ini bakat Rachman Sabur untuk main di perbatasan, di antara pengajuan soal nyata secara langsung dan sebuah kerangka estetis yang mengandalkan pemberian kesan tanpa menjelaskan secara terang-terangan, sangat menonjol. Dari segi gaya/bentuk, “Kaspar” Payung Hitam masih memperlihatkan kaitan dengan arus teater eksperimental tahun-tahun 70-an : tata panggung yang digarap Tisna Sanjaya tidak menggambarkan keadaan realistis melainkan dirancang untuk memberi kesan dan mengisyaratkan sebuah keadaan psikologis dan emosionil yang ditandai dunia benda sampah-sebuah panggung yang remang-remang dan terpenuhi dengan kaleng-kaleng kosong, tong besi, carik-carik kertas. Di tengah panggung berdiri sebuah kerangkeng besi dan sebatang tiang dengan pengeras suara di atasnya, dan dari atas turun ke bawah, boneka-boneka besar yang dibuat dari kaleng sehingga mirip dengan robot-robot. Musik yang diciptakan Harry Roesli menambah corak tersendiri dengan bunyi-bunyi elektronik yang menggemaskan bunyi industrial dan meningkatkan ketegangan seperti dalam film horror. Jadi sebuah suasana simbolis/ekspresionis yang dihadirkan lewat tata panggung dan musik.

Tetapi berbeda dengan teater 1970-1980-an, tidak ada unsur-unsur pertunjukan tradisional yang masuk didalam pementasan “Kaspar”.Hal ini jadi makin menonjol pada saat Payung Hitam, sebagai wakil propinsi Jawa Barat, di Festival Nasional Teater di Bandung, yang menurut Putu Wijaya, dimaksudkan ” membuat pemetaan teater Indonesia yang lebih mengakar pada budaya Indonesia”.
Dengan penampilan yang mengabaikan sifat teater yang rupanya diharapkan oleh para penyelenggara dari Direktorat Kesenian Ditjen Kebudayaan Depdikbud itu, Payung Hitam bersatu dengan kelompok-kelompok Garda Depan lain tahun-tahun 90-an yang tidak merasa budaya tradisional harus menjadi bagian penting dari identitas teater Indonesia mutakhir. Pementasan “Kaspar” Juga memperlihatkan ciri lain dari kecenderungan baru teater Nasional tahun-tahun 90-an.
Disini salah satu ciri lagi dari teater arus baru itu jelas kelihatan. Tubuh Tony Broer itu mampu menghadirkan dengan permainan tubuh akrobatis yang penuh jerih payah dan kesakitan serta humor, representasi jasmaniah dan perjuangan rohani seorang manusia yang menggumuli bahasa dan peraturan resmi untuk mencari identitas yang tidak menindas dan tidak berbohong.
“Aku ingin menjelma seperti orang yang telah pernah ada” ucap Kaspar. Teks pertunjukan “Kaspar” sangat sadar akan bentuk dirinya yang mengandalkan pula permainan dan ekspresi fisik yang luar biasa ini, sehingga pada suatu saat “suara resmi” (Corong pengeras suara) dibikin memperingatkan Kaspar.
Waktu belajar berbahasa, Kaspar sempat menemukan beberapa kepala berita di antara carik-carik kertas yang menunjukkan kekhasan keadaan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Nasution, Permadi, Bambang, dan Aditjondro, semua sanya disebutkan namanya, serta instansi, seperti ABRI dan peristiwa perayaan Ulang Tahun ke 50 republik Indonesia. Ada banyak pernyataan “larangan” diucapkan oleh corong kekuasaan. Ada kalimat Kaspar tentang “kebebasan berpendapat yang selalu ” dicurigai”.Waktu membacakan kepingan-kepingan berita dari koran-koran, Kaspar menyinggung “hak asasi manusia” dan pada akhirnya Kaspar bertanya : “Indonesia milik siapa? ” Teks universal tentang persoalan identitas dalam hubungan dengan bahasa jadi lebih khas, sehingga merubah jadi gambaran pemberontakan manusia Indonesia lewat wacana umum Orde Baru dan pemberontakan sebagian orang Indonesia terhadap sistem itu.
Merah Bolong Putih Doblong Hitam
Berbeda pementasan “Merah Bolong Putih Doblong Hitam” yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1997.Kira-kira setahun setelah peristiwa “Sabtu Kelabu” di markas Nasional PDI di Menteng, Jakarta dan beberapa bulan sesudah pemilu 1997.Memang ada kaitan erat di antara dua pementasan ini, sebab menjelang pementasan “Merah Bolong”, Rachman Sabur pernah mengatakan, bahasa Indonesia sudah diperalat sedemikian rupa oleh para penguasa sehingga pemaknaan kata sudah dirubah dan kata-kata sulit dipercaya lagi. Ada mata rantai tematik di antara ” Kaspar” dan “Merah Bolong”, juga harus diakui bahwa ada perbedaan dasar, yaitu kalau bahasa verbal menjadi problematik dan fokus dalam ” Kaspar’, dalam “Merah Bolong”, bahasa kata dihilangkan sama sekali. Sebabnya barangkali bisa digali dari satu lagi pernyataan Rachman Sabur, sekitar saat pementasan ” Merah BolongBolong” berucap : “membicarakan persoalan tentang politik Indonesia kadang menjadi mual dan sakit”
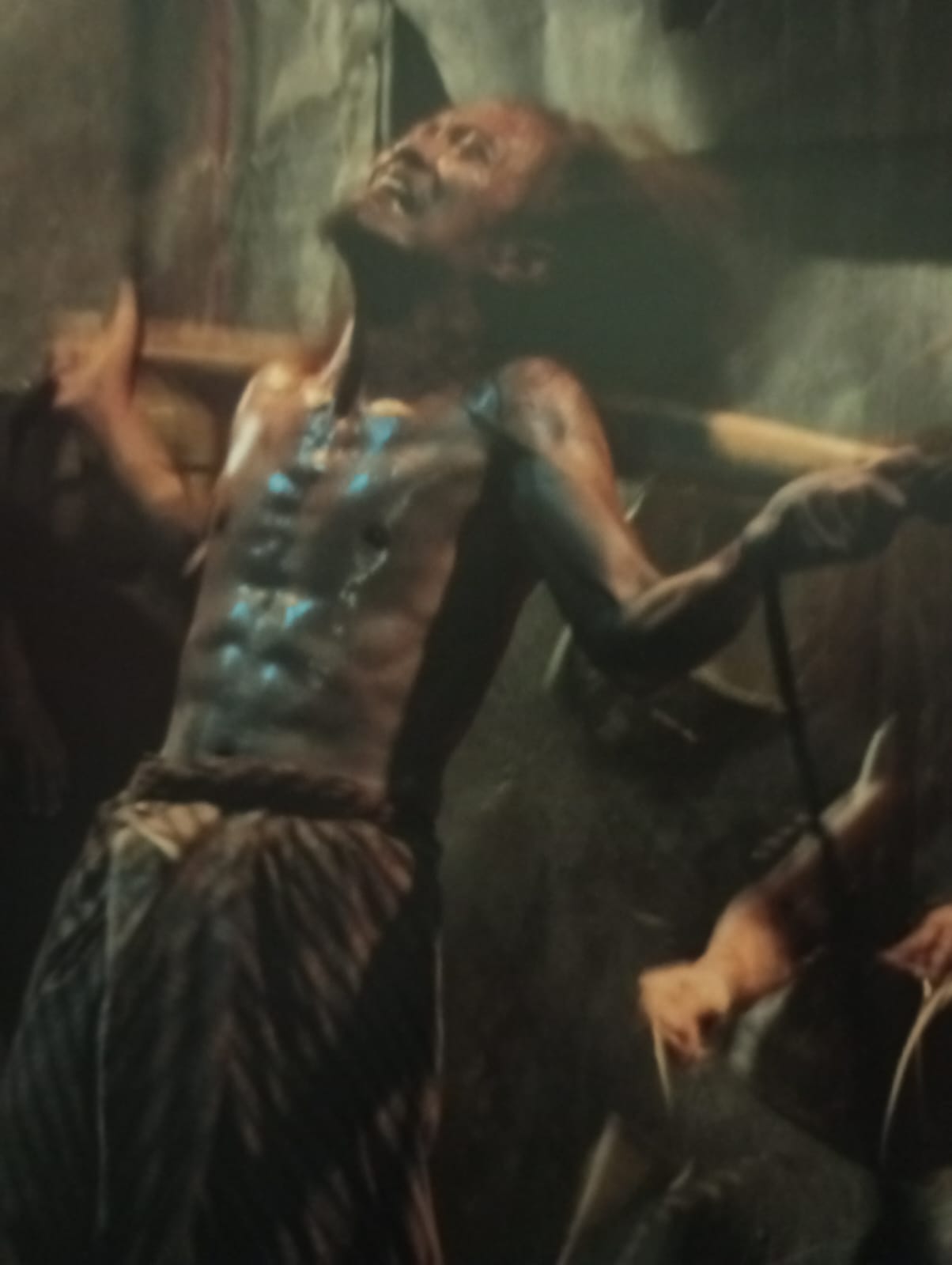
“Merah Bolong” memang seperti sebuah jerit kesakitan.
Dalam pementasan itu, sekelompok sosok manusia bertopeng dan bercelana pendek keluar membawa ember dan selama satu jam lebih, manusia-manusia itu berusaha menumpukkan baru merah dan putih. Mereka bergerak seperti robot-robot.. Dihujani batu krikil, dan diancam oleh batu-batu yang bergelantungan dan diayunkan pemain-pemain sendiri. Ada banyak gerak tubuh, ada unsur tarian. Ada bunyi-bunyi anak baru. Semua terdiri dari keluh-desah nafas para pemain dan bunyi-bunyi batu berjatuhan ke atas lantai, di atas tubuh para pemain. Suara-suara berisik, bising di dalam ember-ember yang dibawa-bawa para pemain. Kata-kata tidak ada. Pementasan tanpa banyak kata memang sudah pernah diciptakan oleh Rendra dengan “Mini Kata” nya pada tahun 60-an dan. Juga oleh Putu Wijaya tahun 70-an”Lho”, “Nol”, ” Entah”), oleh Teater Kubur dengan “Sirkus Anjing” Tetapi Payung Hitam sampai ke gaya begitu dengan jalan tersendiri. Bentuk “Merah Bolong” Pertama kali dikembangkan dalam pementasan Payung Hitam. “Metateater” (1991) yang merupakan hasil kerjasama antara Payung Hitam dengan Harry Roesli dan Seniman, penata panggung Herry Dim. Pementasan “Metateater” Itu juga mengandung adegan dimana seniman-seniman, seperti Maman Noor dan Rahma yani melukis di atas panggung. Dari pengalaman kerjasama Instalasi multimedia ini, Rachman Sabur sempat belajar banyak tentang kemungkinan tata panggung, musik, dan tubuh yang kemudian dikembangkan untuk pementasan-pementasan eksperimental Payung Hitam kemudian.
Didasarkan atas sejumlah resensi pementasan “Mini Kata” Bengkel Teater dari akhir tahun 60-an dan juga dari beberapa foto yang diambil saat Bengkel Rendra pentas ulang “Mini Kata” di Solo menjelang akhir tahun-tahun 90-an, ada beberapa perbedaan yang patut dicatat. Pertunjukan “Merah Bolong” Payung Hitam kelihatan jauh lebih kaya dalam pemakaian properti-properti dan eksplorasi tubuh pemain yang lebih maksimal. Ini dipengaruhi pementasan “Metateater” dan berhasil memperkaya kemungkinan lambang dan asosiasi bagi para penonton. Juga ada beberapa lambang yang dimajukan yang rupanya lebih khas dan spesifik referensinya. Misalnya warna batu krikil yang merah, putih dan hitam.
Meskipun demikian, kenyataan bahwa tidak ada bahasa kata atau alur cerita, dan bahwa referensi sebagian besar adegan-adegan dan properti-properti bersifat umum, masih memungkinkan aneka ragam penafsiran atas isi pementasan ini. Sebagai buktinya, wartawan-wartawan dari berbagai majalah dan koran-koran menafsirkan ‘Merah Bolong” dengan berbagai macam tafsir.
Salah satu properti yang menonjol, disamping batu adalah topeng-topeng yang dikenakan para pemain. Dengan kehadiran topeng yang mewujudkan ekspresi penderitaan, kecemasan, kengerisn dan kesakitan, pola permainan para aktor tidak dimaksudkan mempergelarkan kepribadian dinamis yang berkembang. Melainkan dampak dari pilihan topeng, justru untuk menciptakan manusia sebagai “jenis’ yang beku dalam keadaan tertentu. Keadaan yang menyiksa dan menyebabkan penderitaan. Pertunjukan ” Merah Bolong’ mungkin pada derajat yang melebihi Kaspar. “Merah Bolong” tergantung pada perwujudan penderitaan jasmaniah. Para pemain di padang batu yang kering dan. mandul, tempat banyak ancaman fisik dan rohani. Dengan pekerjaan “Sisyphus”.
Pertunjukan “Merah Bolong Putih Doblong Hitam” kita bisa dapat kesan yang memperkuat batu, dengan harus menginjak batu tajam, dengan dihujani batu krikil stau ditabrak batu ayunan, para pemain berada di sebuah medan hidup yang keras dan penuh bahaya. Identifikasi para penonton dengan keadaan pemain+pemain yang dikembangkan lewat semua adegan ini, tetapi terutama pada saat batu-batu yang bergelantungan mulai diayunkan tidak jauh dari tempat penonton duduk. Payung Hitam berusaha menciptakan suatu identifikasi umum, tipikal, sebagai solidaritas dalam keadaan yang menindih dan menyesak. Namun, soal hubungan kelompok dan individu juga disinggung dalam beberapa adegan. Ambil saja contoh adegan dimana Tony Broer dihujani batu krikil dan menggeletak di lantai, sedang para pemain yang lain waswas, ragu-ragu, dan kecemasan mendekati korban kekerasan itu. Atau dekat akhir pementasan ini waktu seorang pemain menangis sambil ikut membantu menguburkan sosok yang dimainkan Tony Broer. Ada kesan solidaritas, dan akhirnya membangun solidaritas dari adegan-adegan semacam ini.
Batu-batu besar yang bergelantungan yang juga membingkai semuanya dalam pementasan ini penderitaan manusia. Tembang alok sunda dan adegan penguburan pada akhir pementasan dimana batu krikil merah-putih menutupi mayat salah satu sosok manusia yang masih sempat mengepalkan tangannya ke atas seperti tidak mau kalah.
Rachman Sabur kecewa dengan adanya berbagai peristiwa politik busuk praktis di Indonesia. Pertunjukan “Merah Bolong” memperlihatkan sebuah hasrat untuk tidak tinggal diam.
Pementasan Zaman Reformasi
Seperti biasa, Payung Hitam bergerak dengan tubuhnya, menari di antara estetika yang menuntut bahwa kesenian seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam uraian dunia politik dengan karyanya, dan keinginan untuk berdialog tentang hal-hal yang sulit diingkari dan pasti terasa hampir semua warga Indonesia, mereka tetap mencari keseimbangan estetis di antara pesan yang sejelas-jelasnya dan kerangka multi-tafsir. Kalau “Merah Bolong” Condong ke sudut multi-tafsir. Karya-karya Payung Hitam pasca Orde Baru menoleh ke sudut yang lain.
Misalnya, dalam “Kata Kita Mati” (1998), ada lambang-lambang seperti kursi, podium(diatas roda), pidato yang berbusa-busa dan gambar raksasa Soeharto ditembok yang diruntuhkan pada akhirnya hanya untuk menyingkapkan sebuah tembok baru dengan gambar yang sama. Semua ini tidak terlalu sulit ditebak artinya. Kekayaan komposisi set dan properti di atas panggung serta konsep dasar yang kuat dan pengadeganan yang cemerlang membuat pementasan ini memukau. Dari “Merah Bolong” yang “sepi kata” sampai “Kata Kita Mati” yang menenggelamkan para penonton dalam sebuah banjir kata retorika, Teater Payung Hitam tetap menjelajahi beberapa kemungkinan memperluas khazanah bentuk pertunjukan teater yang bisa menantang para penonton untuk melihat beberapa kebenaran tentang keadaan di sekeliling diri mereka.
Apalagi dengan pementasan “Tiang 1/2 Tiang” (1999) yang kembali ke pola “sepi kata”, tetapi tetap menyajikan citra-citra yang tak terlupakan : salah seorang setengah telanjang yang diikat lehernya tergeletak tanpa data di bawah keramaian segerombolan manusia yang pukulkan cabang dengan keras sambil membawa bendera-bendera berwarna-warni di punggung-punggung mereka, papan-papan dilukiskan dengan sosok seragam tentara yang masing-masing ada lobang wajah dari mana menonjol muka pemain yang minum dengan haus dari sebuah bola akuarium yang penuh dengan cairan merah, atau dua orang yang bersepatu lars dan bertopi helm militer sambil pegang pistol dan jalan berbaris mengangksng gambar-gambar mayat ;ada orang yang diikat kepada salib bambu ; ada anak laki-laki kecil yang telanjang, dan yang habis menari-nari dengan boneka tanpa kepala yang berhasil merah dan bercelana putih, tertinggal kesepian di depan panggung sambil meniup-niup seruling dengan nada sumbang.
Simbolisasi disini jadi sangat jelas, tetapi dampaknya terhadap para penonton di Makassar Arts Forum pada September 1999 sungguh luar biasa! Penjajaran adegan tentara dan Pemilu dengan kesan kerasnya disamping adegan anak telanjang yang sepi dan penuh nada sumbang sulingnya, membuat semua penonton tahan nafas. Habis pementasan, emosi meledak saat para penonton serentak berdiri sambil tepuk tangan dan bersorak-sorai dengan sangat terharu. Pada saat itu, dengan kebebasan berekspresi yang sudah lebih luas, campuran adegan dengan citra-citra nya yang ditampilkan sangat menyentuh hati khalayak. Gambaran seterang itu tentang topik-topik yang begitu sulit dibayangkan sebelum 1998.
Dengan “Tiang 1/2 Tiang” eksperimen-eksperimen Payung Hitam dalam perwujudannya persoalan mutakhir masyarakat Indonesia masih tetap berjalan*





