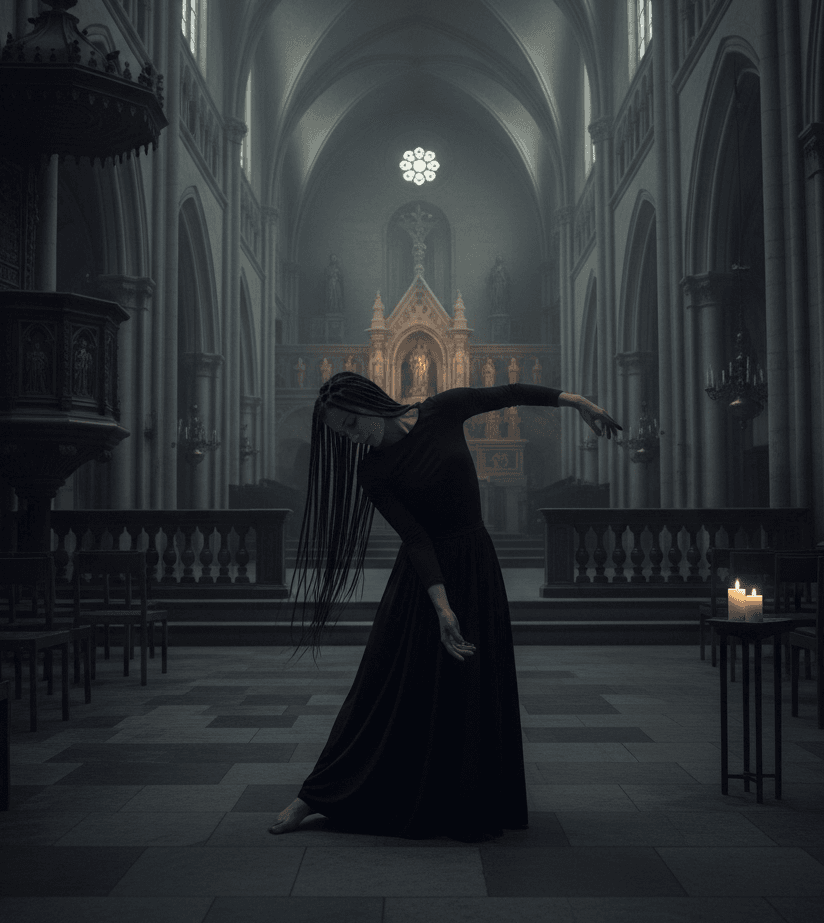Di Antara Mainan Berserakan dan Hujan Rintik : Sebuah catatan intim tentang seorang ibu yang menyeimbangkan peran sebagai guru, pengasuh, dan pemandu spiritual, sambil tetap hadir sepenuh hati di setiap momen.
Pagi ini rumah terasa sunyi, kecuali suara Agastya yang mengomel karena sarapannya tidak sesuai selera, sementara Adiba menempel di dinding beranda dengan rambut acak-acakan dan mata setengah tertutup kantuk. Aku tersenyum sendiri, menyuapi mereka sambil menepuk perutku yang mulai membesar, merasakan tendangan kecil yang mengingatkanku bahwa kehamilan keempat ini, meski sudah familiar, tetap terasa seperti yang pertama—penuh kejutan, penuh perhatian, dan penuh rasa.
Aku teringat Muhamad Hanif Wiradikarta, anak ketiga yang hanya singgah sebentar di hidup kami, dua bulan dalam kandungan. Kehilangannya meninggalkan ruang yang tak tergantikan, tapi juga mengajarkanku sesuatu yang tak ternilai: bahwa setiap detik yang tersisa bersama mereka yang ada harus dihargai sepenuh hati. Kini, setiap tawa, setiap pelukan terasa lebih hidup, lebih bernyawa, seolah mengisi ruang kosong yang pernah ada.
Di sekolah, kelas bergelora dengan suara siswa yang bercampur menjadi satu arus, memantul di dinding, menimbulkan riuh yang khas. Aku mengajar sambil sesekali menoleh ke jendela, membayangkan Agastya sedang bermain sepeda di taman belakang kompleks. Kadang aku merasa terbagi, seolah ada bagian tubuhku di sekolah dan bagian lain di rumah, tapi aku percaya, perhatian yang tulus akan sampai, meski aku tidak selalu hadir secara fisik.
Mengajar memberi energi tersendiri; ada kepuasan lembut saat melihat mata mereka berbinar, ketika sebuah pertanyaan muncul dan rasa ingin tahu mereka tumbuh perlahan. Aku tersadar, peran seorang ibu dan guru tidak terlalu berbeda: keduanya menuntut kesabaran, cinta, dan komitmen—tanpa pamrih, tanpa penilaian dunia. Kehadiran mungkin tidak selalu terlihat, tapi selalu terasa, di hati mereka, di mataku sendiri, dan di ruang hening yang ada di antara kami.
Pulang ke rumah, menjelang sore: mainan berserakan menyambutku, tumpukan kecil dari dunia anak-anak yang penuh imajinasi. Anak-anak berlari memelukku, suami tersenyum dari saung bonsai depan rumah, dan aku duduk sejenak, menutup mata, merasakan perut yang mulai berat. Kehadiran di rumah bukan tentang melakukan semuanya sendiri, tapi hadir sepenuh hati—dalam tawa, kata, dan pelukan—sehingga rumah terasa hidup dan hangat.
Di sela-sela rutinitas, kadang suami dan aku berbeda pendapat—tentang jadwal, tugas rumah, atau cara menyiapkan sesuatu. Pertengkaran kecil itu tidak pernah lama, tapi selalu diikuti dengan tawa atau pelukan. Aku menyadari, anak-anak melihat itu, dan mereka belajar sesuatu yang penting: bahwa cinta tidak berarti selalu setuju, tapi berarti tetap saling menghargai, menegur dengan lembut, dan menuntun satu sama lain. Pertengkaran yang bijak justru membuat rumah lebih hangat, karena menunjukkan bagaimana perbedaan bisa diatasi dengan sabar dan rasa hormat, dan anak-anak menyerap pelajaran itu tanpa disadari.
Hujan rintik menetes di luar jendela, menciptakan suasana hangat dan basah sekaligus. Agastya dan Adiba tertawa, bermain dengan jas hujan mini mereka, sementara aku tersenyum, mengangguk, dan membiarkan mereka menikmati momen itu mengalir dengan apa adanya. Saat menyiapkan sarapan, aku merenung; kehilangan di masa lalu memberi perspektif yang jelas: setiap detik adalah kesempatan untuk hadir, merasakan, dan mencintai, meski sederhana dan tak selalu sempurna.
Sambil mengoreksi tugas di sekolah, aku menatap jendela yang masih basah oleh hujan. Beberapa siswa tampak lelah, beberapa antusias. Aku tersenyum sendiri. Menjadi guru adalah tanggung jawab, tapi juga kesempatan untuk merenung tentang kehidupan—tentang bagaimana menyeimbangkan peran, bagaimana mengasihi tanpa rasa bersalah, dan bagaimana hadir, meski dunia menuntut perhatian penuh.
Tak terasa, maghrib pun tiba. Aku dan anak-anak pergi ke mushola untuk mengajar ngaji anak-anak kompleks. Suasana sederhana itu hangat; aku melihat wajah-wajah kecil menatapku dengan antusias, suara mereka melantunkan ayat-ayat yang menenangkan hati. Terkadang, Agastya duduk di sudut pintu kamar dengan ayahnya, belajar ngaji dengan penuh konsentrasi. Aku dan Adiba duduk di ruang keluarga bermain bersama. Bada isya, rumah kembali ramai. Anak-anak meminta dibacakan cerita, suami menyiapkan teh, dan aku menyiapkan perlengkapan sekolah untuk besok. Aku duduk sebentar, menarik napas panjang, merasakan perut yang berat, dan tersenyum. Kehadiran bukan tentang melakukan semua hal, tapi tentang hadir sepenuh hati dalam setiap momen yang bisa kulalui.
Sebelum tidur, aku menutup diary. Hari ini penuh dan melelahkan, tapi hatiku ringan. Keseimbangan bukan tentang menyelesaikan semuanya, tapi tentang mampu hadir sepenuh hati di setiap detik. Menjadi ibu adalah perjalanan panjang yang mengajarkanku tentang cinta, kesabaran, dan kebahagiaan sederhana. Aku menarik selimut, menutup mata, dan bersyukur. Besok akan ada hari baru, dan aku siap untuk mencintai, hadir, dan belajar lagi.
Pagi berikutnya, aku membuka jendela dan mendengar hujan rintik-rintik, meski ini bukan musim hujan. Suasana basah dan segar mengingatkanku pada siklus hidup: kehilangan, harapan, dan kebahagiaan kecil yang selalu muncul di sela rutinitas. Aku menulis ini bukan untuk membuktikan apa pun, tapi untuk menangkap detik yang mungkin terlupa. Menjadi ibu bukan tentang sempurna, tapi tentang belajar menyeimbangkan, hadir, dan mencintai setiap hari. [kamis malam 23.45 WIB, 11 Desember, 2025]