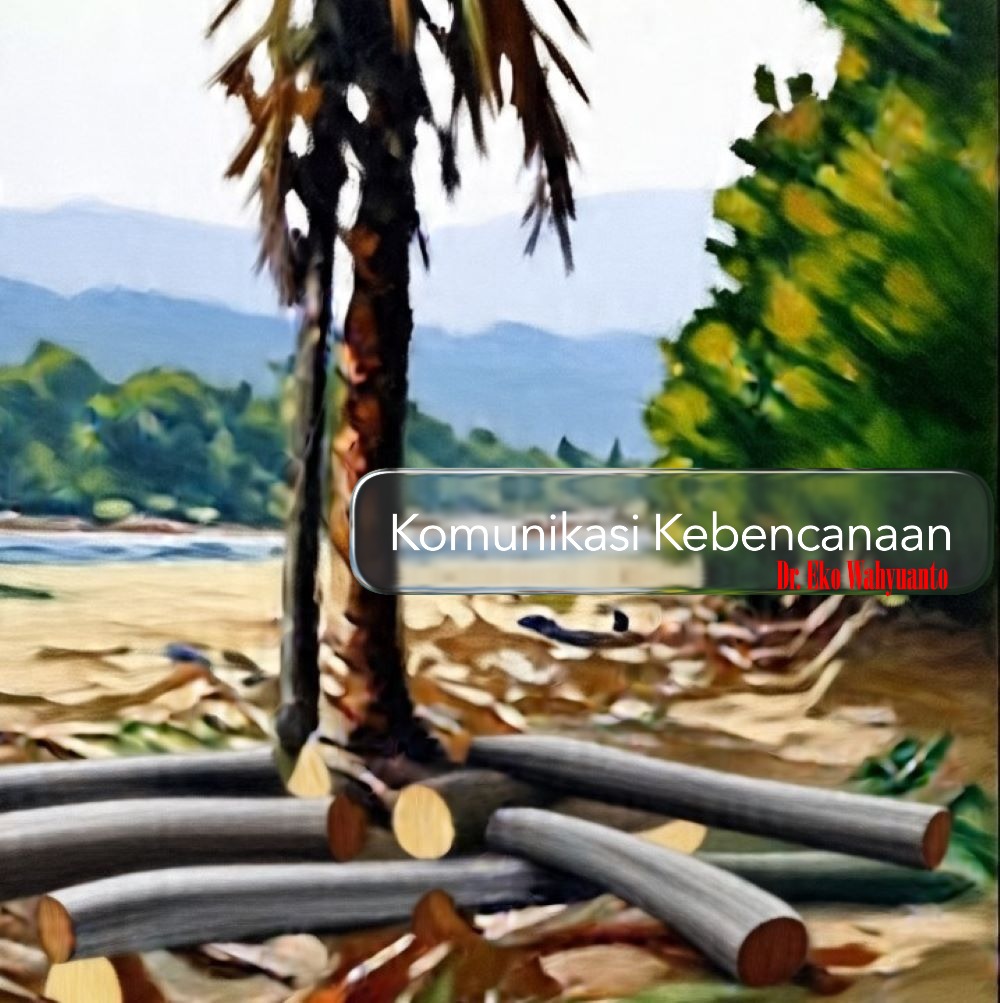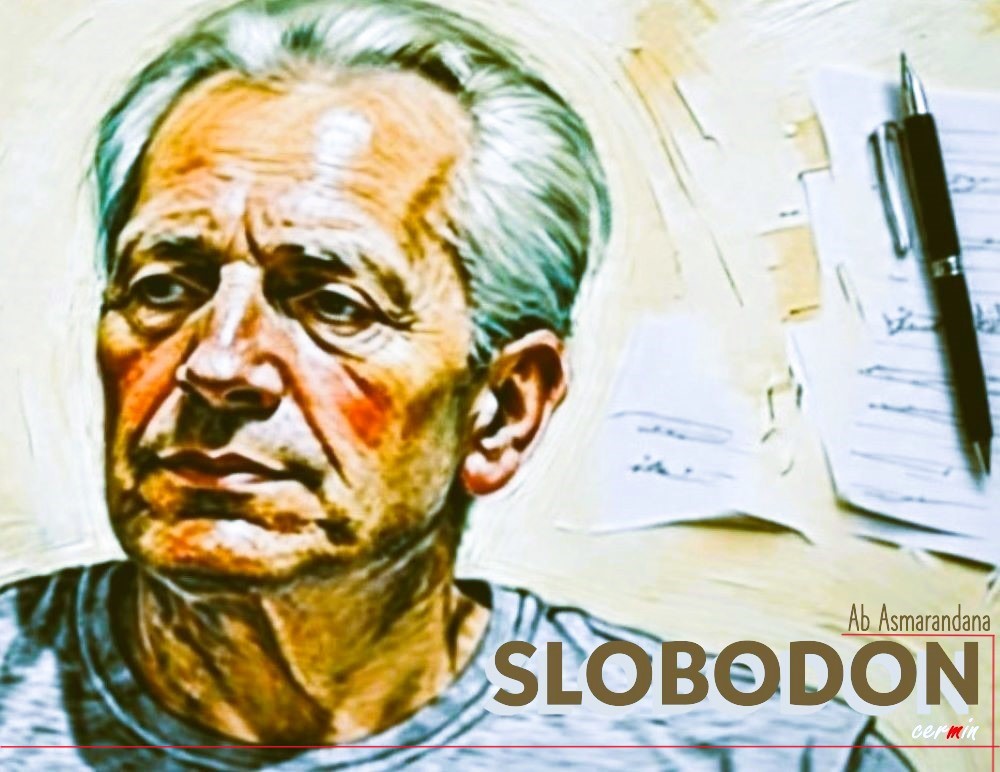Dalam krisis kebencanaan kita kerap menyaksikan para tim penanganan mencoba membangun narasi lantang. Seolah-olah mereka yang paling paham dan siap dalam misi penyelamatan dan mitigasi. Apa yang terlihat di permukaan acapkali seperti sedang menyembunyikan pesan yang sesungguhnya. Mereka berbicara sebagai tim yang menangani krisis, tapi tak memahami hal paling mendasar dari komunikasi krisis. Ini kegagalan filosofis dalam memahami esensi dan tanggung jawab publik. Seperti kata filsuf Jerman Immanuel Kant, bahwa kebenaran adalah kewajiban moral yang secara universal, bukan alat untuk memoles citra. Di sinilah kita perlu bertanya mengapa begitu banyak krisis berakhir dengan kekacauan yang lebih besar, bukan karena krisis itu sendiri, tapi karena komunikasi yang gagal.
Prinsip dasar sosiologi komunikasi krisis
Satu hal yang harus diperhatikan adakah “Don’t blame anyone for anything.” Jangan salahkan siapa pun untuk apa pun. Ini adalah aturan emas yang bermakna tajam dalam kesederhanaannya, tapi sering dilanggar atas ketidak pahaman. Dalam krisis, seperti bencana alam atau skandal korporasi, dorongan untuk mencari kambing hitam selalu kuat. Politisi menyalahkan birokrasi, oposisi menghujat pemerintahan yang sedang berkuasa, perusahaan menyalahkan karyawan, atau atau korporasi menyalahkan Sumber Daya Manusia nya. Menyalahkan hanya memperburuk polarisasi, mengalihkan fokus dari jauh dari solusi ke konflik. Aristotelian menyatakan kebajikan adalah keseimbangan, bukan ekstrem. Berapa banyak krisis di Indonesia, dari banjir Aceh hingga kasus korupsi, yang memburuk karena saling tuding. Alih-alih menyatukan, komunikasi semacam ini memecah belah, meninggalkan korban dalam situasi ketidakpastian.
Jangan berspekulasi di depan publik tentang fakta yang belum diketahui. Ini prinsip penting yang sering diabaikan demi sensasi media sosial. Bayangkan tim penanganan krisis yang buru-buru mengumumkan “kemungkinan” penyebab tanpa bukti, seperti spekulasi awal tentang penyebab kecelakaan pesawat atau pandemi. Dapat menciptakan narasi palsu yang menyebar seperti virus, mengikis kepercayaan publik. Dari perspektif “post-truth”, ketika fakta digantikan oleh opini, maka totaliterisme informasi lahir. Persoalannya, apakah kita sebagai masyarakat sudah terlalu terbiasa dengan rumor, sehingga tim krisis merasa aman berspekulasi? Di era digital, spekulasi bukan hanya kesalahan, tapi senjata yang dapat menghancurkan reputasi dan nyawa manusia
Koordinasi semua lini
Dalam kasus penangan bencana koordinasi lintas lini akan membantu korban. Koordinasi adalah inti dari tanggung jawab kolektif, tapi seringkali terabaikan dalam birokrasi yang kaku. Dalam konteks ini menyatukan sumber daya, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, dengan menanggalkan ego institusi masing-masing, sebab bagaimanapun yang mendapat kredit adalah korban. Ini mengingatkan pada konsep “social contract” Rousseau, bahwa negara ada untuk melindungi warganya, bukan untuk saling berebut panggung kekuasaan. Membiarkan korban berarti pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan. Bayangkan jika koordinasi dilakukan dengan benar, bantuan tiba tepat waktu, trauma korban berkurang, dan masyarakat bangkit lebih kuat.
Informasi yang transparan dan jujur
Katakan kebenaran secara terbuka, jujur, dan lengkap. Ini prinsip sosiologis paling mendasar di antara semuanya, karena kebenaran adalah fondasi demokrasi. Namun, dalam prakteknya kita kerap melihat tim kebencanaan menyembunyikan fakta demi “menjaga stabilitas.” Analitisnya, ketidakjujuran menciptakan vakum informasi yang diisi oleh konspirasi. Lihat saja kasus global seperti Chernobyl atau lokal seperti lumpur Lapindo—kebohongan awal memperpanjang penderitaan. Secara lugas, katakan apa adanya: berapa korban, apa penyebab, apa langkah selanjutnya. Reflektifnya, ini memaksa kita merenungkan diri: apakah kita sebagai pemimpin takut kebenaran karena itu mengungkap kelemahan kita? Seperti kata Socrates, “Hidup yang tak direfleksikan tak layak dijalani”—komunikasi krisis yang jujur adalah refleksi atas integritas kita.
Komunikasi terbuka dan manusiawi
Jika tim penanganan krisis melakukan kesalahan, harus minta maaf. Ini adalah puncak dari kerendahan hati, tapi jarang dilakukan dengan tulus. Secara moral, permintaan maaf bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan dalam memanusiakan manusia. Permintaan maaf yang cepat akan mengurangi tuntutan hukum dan membangun kembali kepercayaan, seperti yang dilakukan Toyota dalam me recall mobil karena ada kesalahan produksi. Dalam konsep “forgiveness” dalam kata “maaf” adalah jembatan menuju rekonsiliasi. Kita melihat berapa banyak pejabat yang enggan minta maaf karena takut kehilangan muka? Ini mencerminkan budaya feodal yang masih melekat, di mana kekuasaan di atas empati.
Secara keseluruhan, kegagalan memahami dasar-dasar sosiologi bukan sekadar kelalaian, tapi gejala lebih dalam dari masyarakat yang kehilangan arah moral. Tajamnya, tim penanganan krisis sering lebih sibuk dengan pencitraan daripada penyelamatan. Analitis dan sistematis, setiap prinsip ini saling terkait: tanpa koordinasi, kebenaran tak terungkap; tanpa maaf, spekulasi berlanjut apakah kita siap menjadi masyarakat yang dewasa, di mana krisis bukan akhir, tapi peluang untuk tumbuh? Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam siklus kegagalan, meninggalkan korban sebagai saksi bisu atas ketidakmampuan kita. Krisis datang dan pergi, tapi komunikasi yang buruk meninggalkan bekas abadi. Saatnya merefleksikan dan bertindak, sebelum krisis berikutnya menelan kita semua.