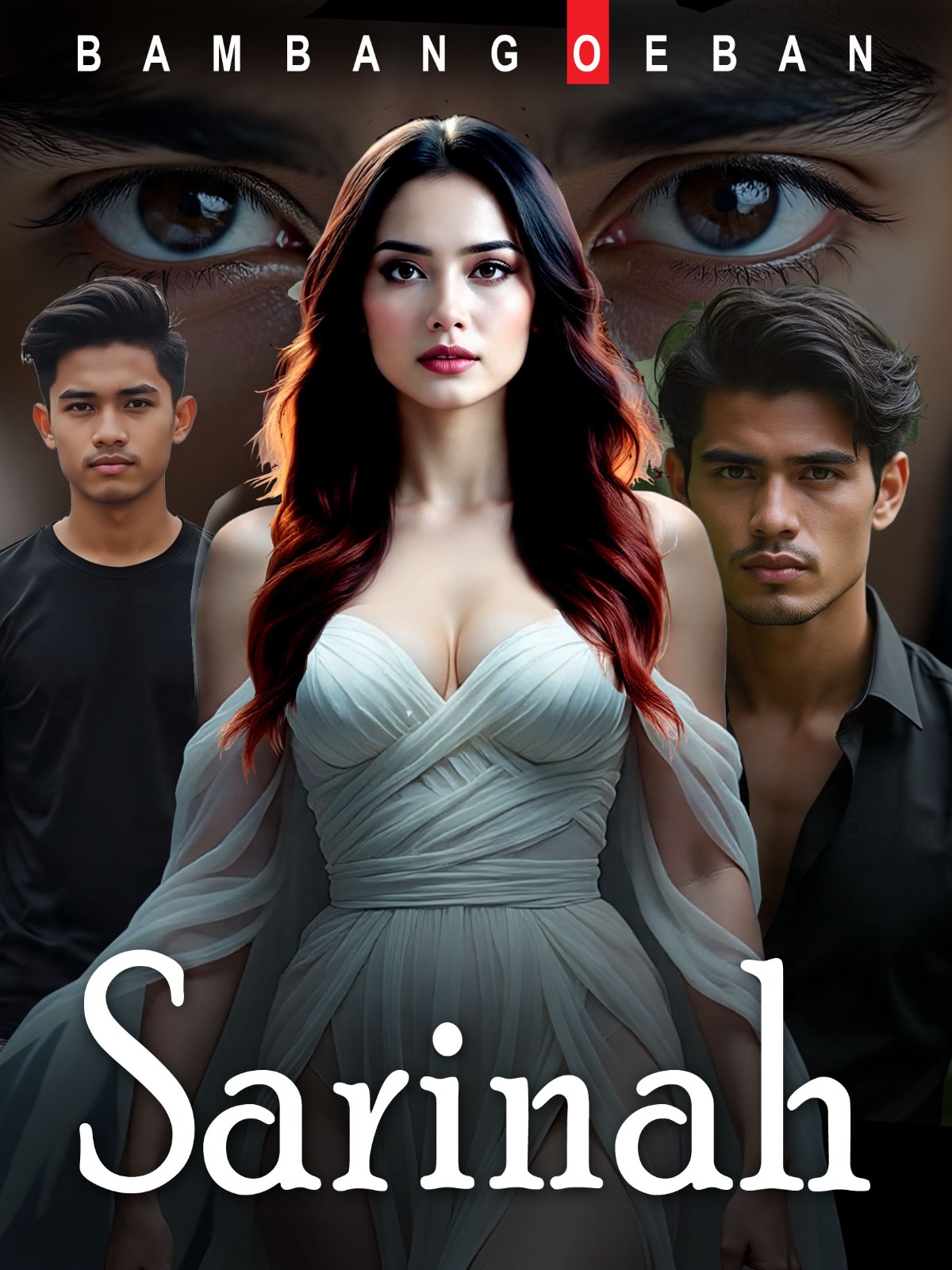Bagian 4
Sore itu hujan belum benar-benar reda, tapi aku sudah duduk di ruang tengah rumah panggungnya yang rendah di Tassipi, menunggu kopi yang ia panaskan ulang di tungku belakang. Bau arang menyusup pelan, seperti cerita yang sebentar lagi disuguhkan.
Ia menunjuk foto kecil tergantung di dinding: istrinya, anaknya, dan satu rumah yang kini tinggal rangka. Dari situlah, kisahnya mengalir.
Tentang satu keluarga Sri Lanka yang diselamatkan nelayan Rote, terdampar karena mesin mati, bertahan dengan air hujan dan sisa nasi kering. “Di laut, kepercayaan bisa lebih kuat daripada peta, ” katanya lirih.
Nelayan Rote tak bisa bantu lebih. Tapi ia tahu satu orang lelaki dari Tassipi. “Orang bilang dia pernah hilang tiga hari, pulang bawa tiga drum BBM dan dua ekor ikan.” Maka keluarga itu diserahkan padanya. Orang yang tahu cara menyelinap di laut, dan cara mendengar tanpa harus mengerti.
Mereka berangkat dini hari. Pulau yang dituju bukan pulau sebenarnya hanya bagian dari karang tua yang muncul sebentar lalu tenggelam. Tapi cukup untuk bernapas dua malam. Mungkin tiga, kalau laut sedang teduh.
Tak ada pohon. Tak ada naungan. Hanya pasir basah, ombak, dan sepi yang menempel di kulit seperti garam. Semua percakapan berlangsung dalam bisik. Bahkan api rokok pun ditutup telapak tangan.
Anak kecil itu duduk memeluk lutut, kepalanya bersandar di paha ibunya. Di lehernya tergantung plastik bening berisi foto kusut. Wajah perempuan, mungkin foto ibunya: tersenyum, tenang, seperti sedang membisikkan sesuatu yang tak bisa diterjemahkan. Di dalam plastik itu juga ada cangkang kerang, merah tua seperti darah mengering. Anak itu menggenggamnya saat tidur.
Lelaki dari Tassipi tak pernah bertanya. Tapi ia merasa, mungkin itu semacam pelindung atau penanda. Seperti jimat yang tak pernah dibuat, tapi selalu dibawa.
“Cuma kamu yang bisa bicara dengan mereka,” kata nelayan Rote sebelum keberangkatan. Lelaki dari Tassipi hanya tertawa. Dulu, katanya, pernah ada pekerja Sri Lanka tinggal sebentar di desanya. Mereka tak saling paham, tapi cukup untuk tahu arah angin, harga ikan, dan kata ‘terima kasih’.
Anak kecil itu tak bicara selain dalam bahasa ibunya. Pada malam pertama, saat hujan turun seperti bisikan, anak itu menatapnya dan bertanya, “Amma ko?”
Lelaki itu diam sebentar, lalu menjawab pelan dengan logat kasar yang lembut:
“Amma innava. Eya oyā samaga innavā.”
(Ibumu di sini. Ia bersamamu.)
Anak itu tertunduk, lalu duduk di sampingnya. Tidak lagi gemetar. Ia tak perlu tahu apakah dalam tata bahasa ucapannya benar. Yang penting, anak itu percaya. Itu cukup.
Laut tidak butuh banyak kata. Di sana, keheningan bisa menjelaskan segalanya.
Di tengah laut yang tak menyebut nama, sebuah kapal datang. Sunyi pecah. Waktu seperti dipaksa berhenti.
Ia tak sempat bicara. Tidak sempat menyembunyikan siapa pun.
Lelaki muda dari Sri Lanka, yang sejak malam pertama tampak paling tegang, berdiri. Tangannya gemetar. Ia menunjuk.
“Dia yang mengantar kami.”
Kata-katanya pelan, tapi cukup tajam untuk membelah pagi yang belum sempat bernapas.
Lelaki dari Tassipi tidak menyangkal. Ia hanya memejam, seperti sedang menyiapkan tubuhnya menjadi bagian dari laut.
“Aku tidak marah,” katanya padaku kemudian. “Mungkin dia takut. Mungkin dia kira itu bisa selamatkan keluarganya.”
Tapi ia tak sempat kembali ke Tassipi. Lama. Ia seperti lupa berapa lembar kalender yang lewat.
Setelah teriakan itu, laut membungkam. Yang tersisa hanyalah tangan-tangan asing dan langkah menuju gelap.
Ia ditahan. Malam-malam di sel tak punya nama. Hanya dinding lembap dan suara ombak yang datang dari ingatan. Ia menghitung hari dengan membayangkan anaknya duduk di depan rumah, menunggu ayahnya pulang membawa ikan.
Rasa bersalah adalah air asin yang tak pernah kering, bahkan saat ia tidur. Ia tidak menyalahkan siapa pun. Tapi ada luka yang tak bisa dijelaskan kepada hukum. Karena hukum tidak lahir dari tempat yang sama dengan laut.
Ia kembali beberapa tahun kemudian. Tapi Tassipi sudah berubah. Rumahnya masih berdiri, tapi sunyi seperti tubuh tanpa ruh. Anaknya jarang bertanya. Dan istrinya, katanya, mulai lupa bagaimana suara mesin perahu terdengar dari kejauhan.
“Aku cuma berharap anakku kelak tahu, bahwa ayahnya pernah memilih membantu, meski dihukum karena itu, ” katanya pelan.
Malam itu tak seorang pun bergerak. Bayangan kami tumpang tindih di dinding, digerakkan cahaya dari tungku yang sebentar lagi padam. Aku tak mencatat apa pun. Rasanya seperti mencatat suara hujan, selalu jatuh, tapi tak pernah bisa utuh.***
Tassipi, 2025