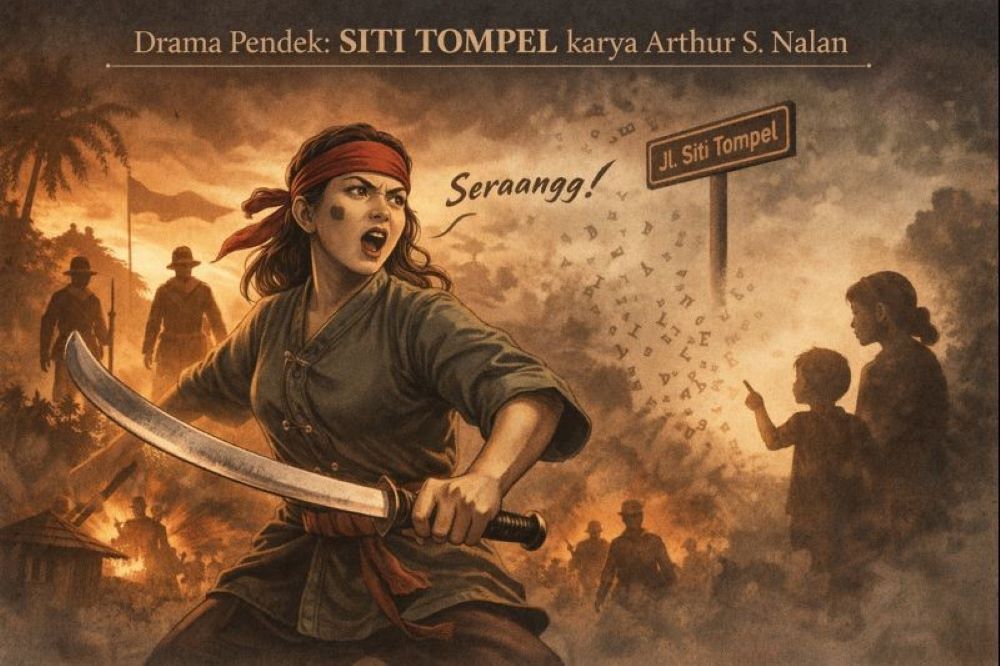Teater Tubuh ADUH karya Putu Wijaya sutradara Rachman Sabur. Produksi Teater Payung Hitam. Dok. Foto TPH
Pada akhir 2018, Teater Payung Hitam-Rachman Sabur, mementaskan lakuin ADUH di Pusat Kesenian Tasikmalaya. Pertunjukan digelar di Halaman Gedung dengan penonton nangkring di teras depan depan gedung. Kenapa posisi pertunjukan berkebalikan dari beberapa hari parade teater karya-karya Putu Wijaya dimainkan di dalam gedung semuanya, terkecuali pertunjukan ADUH, segera dapat dimaklumi penonton yang tumpah ruah menghadiri perhelatan. Karena setnya sebuah menara bambu tinggi yang tak mungkin tergambarkan dengan baik di panggung. Apalagi kemudian ada mobil ambulance berukuran besar yang menjadi setptop yang dominan selama tontonan berlangsung.
Saya tidak tahu apakah penonton juga sadar, itu sebuah introduksi untuk melihat, mengalami, merasakan dan kemudian menyimpulkan sesuatu(dalam hal ini lakon ADUH) dari sudut pandang lain. ADUH adalah lakon verbal yang cerewet. Berhamburan dialog bagai semrawut lalu-lintas di simpang sembilan yang traffic light nya tak berfungsi. Esensi keriuhan itu untuk menggambarkan adanya situasi tak masuk akal, tetapi nyata, dan bahkan dianggap wajar, bagi yang terlibat di dalam kehidupan normal/nyata sehari-hari (absurd/referensi barat).
Dalam ADUH ada cerita, sosok-sosok/tokoh dan dialog, sebagaimana lakon realis konvensional. Tetapi bukan untuk memindahkan realita ke pentas,tapi itu hanya “infrastruktur” mengantar penonton pada esensi tontonan, yakni refleksi kehidupan.
Seorang penonton yang tinggal di New York, yang sudah membaca lakon ADUH, sudah beberapa kali melihat lakon itu dimainkan oleh beberapa kelompok lain, kecewa. Ia menganggap tontonan teater payung Hitam itu hanya judulnya saja ADUH tapi bukan lakon ADUH.
Penonton yang lain, seorang sutradara teater dari Bali, berpendapat sebaliknya. Ia terpukau. Baginya ADUH Payung Hitam itu dahsyat. Dia tergerus hanyut dan tertusuk batinnya karena pertunjukannya hadir intens dan sangat terasa tangan sutradara begitu cermat dan kreatif mengarahkan laku dan peristiwa sehingga tontonan itu menyihir. Tak peduli apa pun artinya bagi orang lain. Tapi yang jelas bagi dia sebuah pengalaman batin.
Saya penulis lakon ADUH(1971). Saya ikut nangkring di teras gedung menikmati garapan Rachman Sabur bersama penonton yang lain. Di dalam kepala saya ada tiga “vacum cleaner”.
Semuanya ingin menyedot apa yang akan berlangsung. Sebagai penulis saya ingin ngecek bagaimana celotehan saya itu akan dituangkan. Sebagai sutradara saya ingin tahu seberapa jauh Rachman Sabur mampu menggoreng lakon. Dan sebagai penonton, saya ingin menikmati apapun yang akan terjadi. Setelah beberapa jurus, saya lepaskan kehadiran diri saya sebagai penulis. Karena itu bukan peragaan teks ADUH, tapi refleksi esensi ADUH, Sabur telah meminum seluruh teks lalu memutuskan hasil percakapannya dengan naskah, lewat bahasa ucapnya.
Jadi tontonan bukan fotokopi bukan replika, tapi bisa juga bukan apa yang ingin kita tonton, tapi apa nanti yang akan kita tonton.
Dalam pengertian seperti itu, tidak berarti lakon hanya embel-embel dan juga bukan wujud asli dari bayangan yang. Kita tonton tetapi asal-muasal, asal-usul, hulu, sumber, esensi tontonan. Alhasil tontonan bukan pengejawantahan, tapi refleksi lakon. Sebagaimana pernah diakuinya Rachman Sabur, di Payung Hitam, selama ini menggarap teater, berpijak di dua kutub. Kutub teater konvensional yang memainkan naskah verbal. Dan kubu teater visual/ kontemporer, yang mengandalkan kekuatan tubuh/teater tubuh.
Dedikasi Sabur pada teater verbal yang tak pernah goyah serta berkualitas membuat apresiasinya pada lakon verbal tak perlu diragukan.
Dalam mevacumcleaner/menyedot lakon, ia seorang Doktor penciptaan teater. Tapi karena bahasa ekspresi yang kini dipilihnya, ia mengandalkan tubuh, output garapannya, jadi bukan didominasi “bunyi” tapi bentuk/laku /kejadian/peristiwa.
Berbeda dengan pekerja teater tubuh yang tak menguasai ABC teater verbal, ketubuhan garapan Sabur, dalam “kebisu” annya kental oleh tuturan. Saya menikmati ADUH teater Payung Hitam. Karena saya tak ada masalah menikmati bahasa tubuh Sabur. Karena saya “membaca” di balik kebisuan nya, di balik ketubuhannya, bukan ketidakmampuan vokal. Bukan ketidakberdayaan bertutur secara verbal. Tapi karena konsep, niat, perhitungan dan konsekuensi logis sudut pandang lain/baru.
Tuturan tanpa harus bertutur, tanpa perlu berceloteh, adalah penyegaran lewat distorsi yang bukan tak ada agendanya. Di balik upaya itu ada ambisi untuk menangkap realita lebih komplit. Lebih mendalam. Lantaran banyak hal yang sudah hilang, susut, kelupaan, absen, tak kelihatan, karena tertutup oleh verbalisme, yang sering meningkat bablas jadi euforia. Di situlah yang telah ada sebelumnya, tak dirasa ada. Ternyata masih ada sepi dalam sepi, gelap dalam gelap. Kemilau dalam terang. Tiada dalam tak ada. Dan banyak hal yang luput, tak mampu lagi ditangkap, tak bisa diuraikan/dijelaskan dengan verbalisme, menuntut dijemput. Maka ketiadaan verbalisme, dalam sepi yang telanjang, tubuh jadi sakral. Dalam posisi begitu tubuh mengeluarkan cahaya batin yang terang, memaksa tampak apa yang sebelumnya tak kelihatan. Teater tubuh pun terus mencoba melangkah di depan gang buntu. Dan ternyata ada banyak hal, bahkan mungkin segalanya yang belum dipaparkan, terpaparkan
tuntas oleh verbalisme. Tapi tak berarti kebenaran yang dihormati, dipahami, dan terpakai sebelumnya batal. Semuanya masih komplit ada dan sama benar. Karena pada akhirnya semua hanya soal pilihan. Di sana bersaing menjadi tuntutan kehidupan kreatif.
Tak semua penonton siap menjalani pikiran dan pertimbangan kebenaran dalam eksistensi estetika teater tubuh. Dengan retrospeksi seperti yang dilakukan Teater Payung Hitam, ada kesempatan menyiapkan penonton tak hanya mau menonton apa yang ingin ditontonnya. Tapi juga siap menonton apa yang akan ditontonnya.
Satu langkah lagi, retrospeksi juga sebuah teropong ke jantung sendiri. Apakah teater tubuh adalah “doping” terbaik kini yang membuat tampak yang sebelumnya tak kelihatan. Atau hanya salah satu pilihan dari beberapa pilihan lain. Karena retorika, dalam teater verbal/konvensional, misalnya, juga sudah kian canggih, sehingga mampu menghapus apapun yang ada, tanpa menyentuhnya.
Apapun jawabannya, teater Payung Hitam di bawah Rachman Sabur yang menguasai kedua kutub, tetap aman.