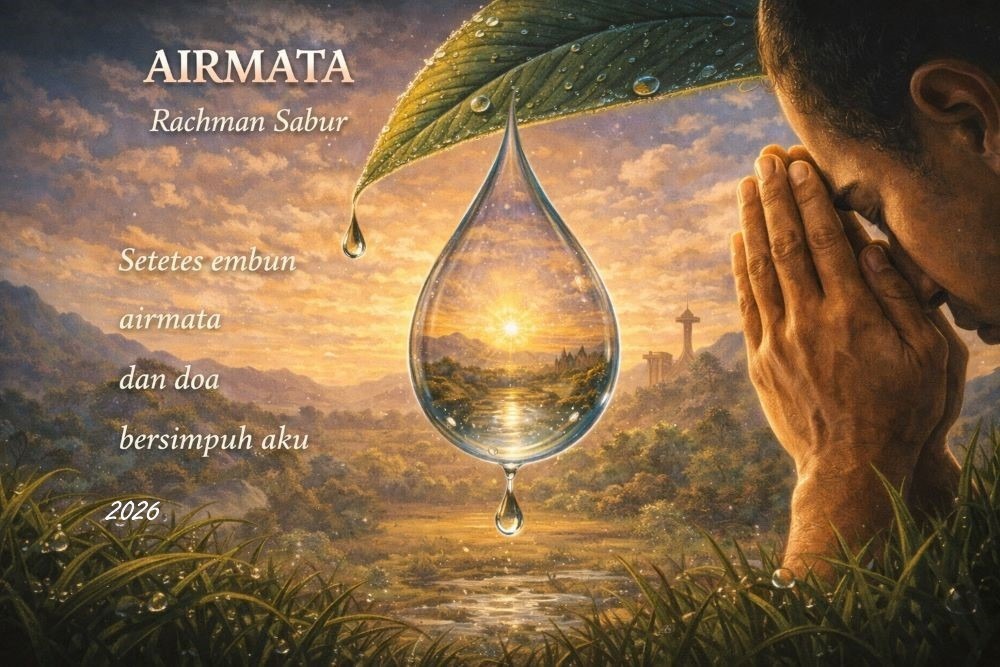Dua puluh enam purnama lewat. Hati Avieka kembali merasa hidup paska ia kembali dengan imam pilihannya.
“Hai, apa kabarnya drakula!”
“Baik. Saya pikir kau sudah labuh pati!”
“Semprul! Kenapa kau tak pernah menghubungiku?”
“Di saat engkau berhenti berkabar dan saya tidak mencarimu disitulah bentuk saya menghargaimu.”
“Bagaimana dengan media yang kalian rintis?”
“Media itu sudah ada yang membeli. Kini kami kembali merintis media baru.”
“Masih dengan komsep yang sama, banyak memuat berita-berita lembaga?”
“Tidak. Titik fokus utamanya pada sastra, seni dan budaya, ditambah sisipan berita,”
“Semakin absurd,”
“Hidup dan kehidupan sendiri absurd,”
“Absurd bagaimana?”
“Seperti adanya laku dirimu yang datang dan pergi sesuka hati,”
“Aku menyapamu malam ini sekadar untuk menyampaikan rasa terima kasih!”
“Untuk apa?”
“Atas sikapmu yang tak meladeniku di itu waktu,”
“Memangnya ada apa denganmu di itu waktu?”
“Panjang. Singkatnya, aku mengalami fase alzheimer pada perubahan perilaku: Depresi, apatis, perubahan suasana hati, curiga, dan disorientasi.”
“Saya pikir puber,”
“Hem … Ya, bisa dikata seperti itu juga, tapi untungnya suami mengerti. Selama ini aku kembali ke pondok,”
“Mesantren?”
“Ya, begini singkat kisahnya: Tuhan menyimak setiap jejak ketidakjujuran, sekecil apa pun bayangnya. Bila manusia tak melihat kejujuran atau kebohongan kita, bukan karena kita pandai menyembunyikan, melainkan karena Tuhan belum mengungkap tabirnya. Maka jangan pernah merasa aman di balik dusta dan kelicikan, sebab segala sesuatu sesungguhnya ditatap-Nya tanpa jeda. Dan pada waktunya, yang tersembunyi pun akan dibuka.”
“Sebaiknya kita fokus pada bahasan lain saja,”
“Kenapa?”
“Jujur harus dikata, saya tak ingin tahu lebih jauh kisah di sebalik layarmu itu!”
“Baiklah.”
“Satu hal lagi, kenapa kau kembali menghubungi saya?”
“Tadinya aku pikir, jalan kisah hidupku ini bisa dijadikan cerita fiksi olehmu. Siapa tahu meledak dan best seller,”
“Baiklah, tapi satu hal yang harus kau ingat; saya tidak pernah menyatakan bahwa hal ini merupakan kontradiksi yang prinsipiil,”
“Memang kau tak menegaskannya, tapi caramu bertutur telah menunjukan hal tersebut!”
Hening. Malam yang meruang jadi kubur-kubur terbuka. Suatu kontradiksi internal di antara dua bayang dari sistem sosial berbeda dan intinya ingin menghasilkan model produksi kapitalis dibuat cantik demi kosmetik. Seperti itulah ruang-ruang pribadi diangkat, seolah murni cerita fiksi. Dalam gemingnya, Dom menahan napas sejenak, sebelum benar-benar melepaskannya ke udara.
“Maafkan aku!”
“Hallo!”
“Dom!”
“Masih bangunkah?”
Tak ada jawaban. Tuhan, barangkali, sedang menyimak semua itu—ketulusan, keraguan, juga sisi-sisi yang tak ingin Dom tunjukkan pada siapa pun. Sebab apa pun yang tersembunyi, cepat atau lambat, selalu menagih untuk dibuka. Dan di pucuk malam itu, saat bulan sabit menipis di balik atap saung bonsai, cerita pun mulai bergerak dari keheningan. Dom hanya belum menyadarinya:
“Aku… tidak tahu lagi harus bercerita pada siapa. Dunia rasanya sempit sekali, tapi dada ini terlalu penuh untuk terus diam. Maka aku datang padamu—entah lewat kata, entah lewat jeda—karena hanya kaulah satu-satunya tempat yang terasa aman. Siapa tahu, dengan kau mengangkat kisah hidupku, beban yang menempel di balik rongga dada ini perlahan bisa terangkat… walau hanya sehelai.”
“Malam itu masih seperti bayang yang enggan pergi. Di sebuah hotel, jauh dari rumah, saat kami sedang menjalankan tugas kantor, tiba-tiba ia tersungkur oleh demam tinggi. Aku panik—entah sebagai rekan kerja, atau sesuatu yang lain yang mulai tumbuh diam-diam. Aku membawanya ke dokter, merawatnya beberapa hari di kamar hotel itu, karena perjalanan pulang lewat udara mustahil ia jalani dalam keadaan begitu.”
“Di situlah semuanya mulai retak, pelan-pelan… tanpa suara.”
“Sebelumnya kami sering makan siang satu meja. Percakapan kecil berubah menjadi kebiasaan, kemudian melebar ke ruang-ruang pribadi yang seharusnya tak kami sentuh. Lalu ia berkata satu kalimat yang sampai sekarang masih menusuk seperti serpihan kaca: Rumah tanggaku bahagia… tapi aku memerlukan kebahagiaan yang lain. Dan kebahagiaan itu… hanya ada padamu.“
“Kata-kata itu… membuatku runtuh sekaligus melayang. Dan di saat yang sama, aku sendiri jauh dari suamiku. Terpisah kota, terpisah provinsi, terpisah kabar. Kadang aku bertanya dalam hati—mengapa ia tak pernah cemburu? Apakah karena kami terlalu sibuk mengejar karier masing-masing? Dan pertanyaan yang paling menyiksa: di antara kami… siapa sebenarnya yang mandul? Siapa yang tak mampu memelihara rumah yang kami bangun?”
“Hari ketiga di hotel itu… aku merawatnya seperti merawat suamiku sendiri. Aku tidur di sampingnya. Memeluk tubuhnya yang panas. Dan sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi… terjadi. Padahal sebelum kami berangkat tugas, ia mengajakku menemui istrinya—istrinya yang manis dan percaya—untuk pamit tugas kerja selama tiga pekan.”
“Sampai sekarang aku merasa Tuhan sedang memperlihatkan sisi tergelapku sendiri.”
“Hubungan tak sehat itu makin menyudutkanku. Terutama ketika ia mengatakan: Hidup ini tak bisa lepas dari mengejar kebahagiaan. Dan kebahagiaanku di luar keluargaku… tidak hanya ada padamu. Kumohon mengerti makna bahagia. Kata-katanya membuatku serasa menjadi bunga yang baru belajar mekar, lalu dirabut begitu saja, akarnya dicabut sampai tuntas. Aku malu. Aku tak berani menatap diriku sendiri di cermin. Aku menjauh dari suamiku… karena aku tak merasa layak pulang.”
“Waktu berjalan seperti menertawakan aku. Aku mencoba mencari pengganti luka dengan hal-hal yang sia-sia. Lalu datang hari itu—suamiku tahu dari kabar angin. Dunia runtuh. Aku mengira itu tamatku.”
“Aku ingin menemuimu, Dom. Tidak hanya lewat pesan-pesan yang patah-patah. Apalagi setelah kau berkata tentang laki-laki yang sibuk mengejar zina demi cinta, sementara perempuan sibuk memikirkan kecantikan dan percintaan hingga lalai akan Tuhannya. Aku terkejut… seolah kau sedang membaca naskah kesalahanku sendiri. Padahal itu adalah tanda-tanda akhir zaman, kau bilang.”
“Dan entah kenapa, kata-katamu menamparku lebih keras dari apa pun.”
“Sejak malam itu, aku menutup diri dari dunia. Sampai akhirnya suamiku dipindahkan kerja—dan ia membaca seluruh kisahku, tapi ia… memaafkanku. Ia memintaku tinggal, ia memintaku pulang ke rumah yang pernah kubiarkan retak. Tuhan—entah bagaimana—memberiku kesempatan kedua.”
“Aku mulai hidup kembali… perlahan. Meski masih ada sisa sesak di ruang hati yang belum menemukan jalannya pulang.” []