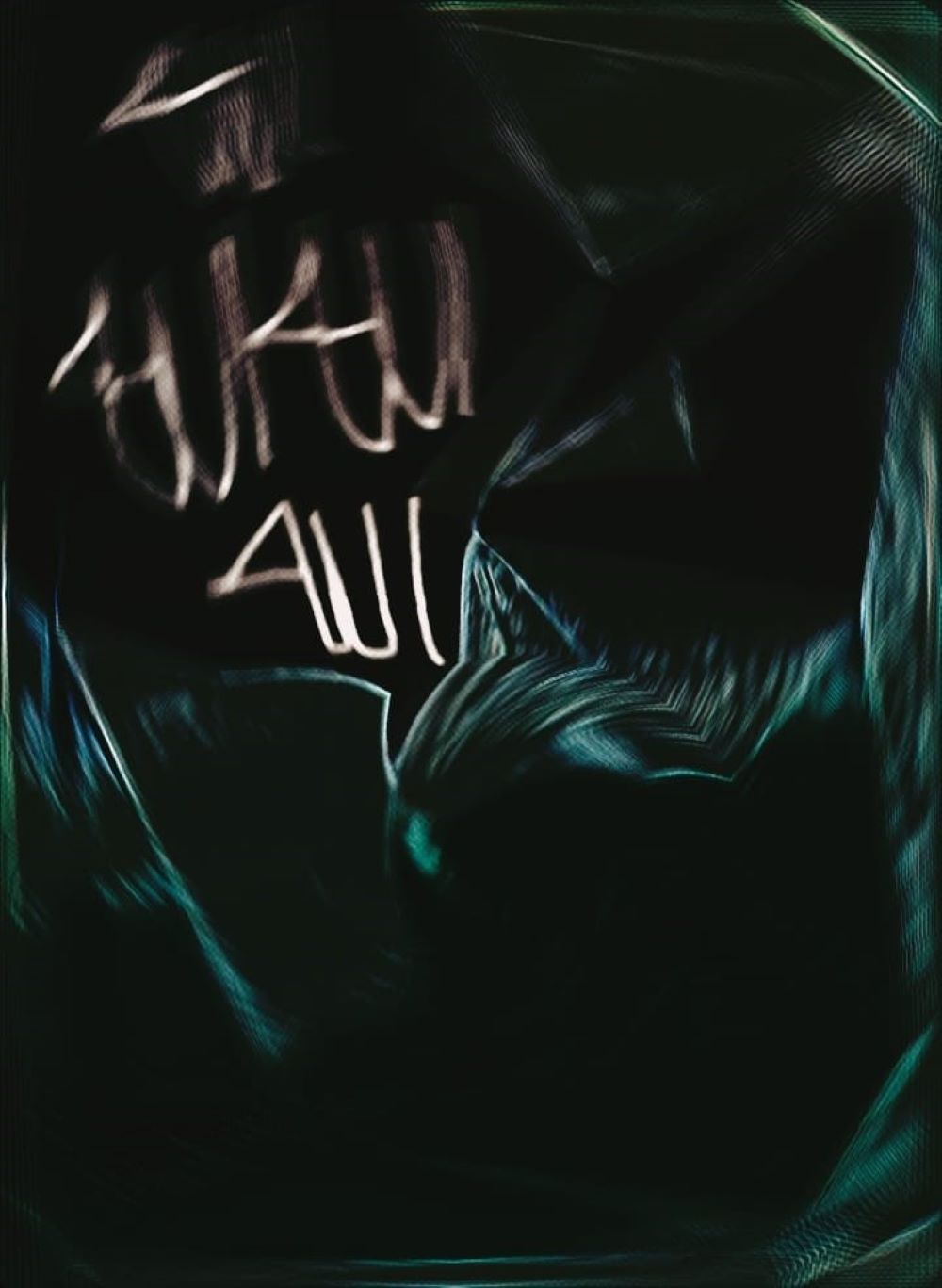Filsuf Brazil Paulo Freire dalam “Pedagogy of the Oppressed”, mengatakan; dunia pendidikan saat ini masih kerap terjebak pada kultur feodalistik akademik.
Dosen diposisikan sebagai “dewa kampus”, sementara mahasiswa jadi “makhluk penghuni” yang hidup bersama dalam strata, dengan rasa hormat berlebih, sulit dijangkau.
Hasilnya, komunikasi terputus, pertumbuhan intelektual lambat, hanya melahirkan generasi pintar di atas kertas, tapi miskin empati, minim keberanian berpikir, dan dangkal dalam logika.
Merujuk pada pandangan Paulo Freire; esensi pendidikan bukanlah “banking education” di mana dosen menyetor pengetahuan dan mahasiswa sebagai penerima, tapi membangun ruang kebebasan, memperpendek “gap”, untuk menghidupkan komunikasi. Perlu memperkuat konsep “inner humanity” , agar pendidikan tak hanya menjadi ritual tanpa makna.
Syauqi Rabbani, alumni Harvard yang kini jadi pegiat pendidikan, bilang: “Semakin “dewa” seorang dosen, semakin susah dijangkau nalar mahasiswanya. Di Harvard, semakin hebat profesornya, semakin gampang diajak berdebat. Cerita ini mengingatkan pada seorang profesor peraih Nobel bidang fisika, Wolfgang Ketterle. Ia memiliki kebiasaan membuka “office hours” bagi mahasiswa, tanpa janji, untuk mendiskusikan tentang apa saja.
Hasilnya luar biasa, seorang mahasiswa S1 bisa berdebat panjang tentang “laser cooling”, kadang profesornya gagap dalam argumen, sampai menemukan pencerahan baru.
“Itulah esensi pendidikan, menyalakan lentera menerangi kegelapan”.
Di Stanford, professor kondang seperti Carol Dweck, penemu “teori growth mindset”, sering mengadakan “coffee with Carol” di kafe kampus, tanpa sekat, tanpa protokol, dan kafe berubah menjadi kelas bebas.
Di Oxford, tutorial system melibatkan dosen dan mahasiswa 1 sampai 3 orang, bertemu seminggu sekali, ngobrol intens selama satu jam penuh. Itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter intelektual. Di kampus-kampus top dunia itu, dosen paling “hebat” justru yang paling “reachable”. Mereka paham: kehebatan intelektual tidak boleh jadi alasan untuk membuat jarak, melainkan menjadikannya sebagai magnet yang mendekatkan.
Dosen yang sulit dijangkau karena alasan simbol status, adalah kemalasan intelektual dan ketidakmampuan membangun relasi. Dosen yang tidak bisa dihubungi mahasiswa lewat WhatsApp di luar jam kuliah, atau yang reply e-mail seminggu kemudian, adalah mereka yang gagal memahami perannya. Akibatnya fatal, mahasiswa jadi takut berdiskusi, pertanyaan-pertanyaan kritis mati sebelum masuk kelas, pembelajaran jadi sekedar ritual formal, ujungnya penilaian bukan berdasar proses, bukan berdasar perkembangan pemikiran, bukan pula berdasar keberanian berdebat.
Padahal, jika dosen mau dekat, mau mendengar, mau ngobrol santai, dia akan tahu persis: siapa mahasiswa yang benar-benar berpikir, siapa yang hanya menghafal, siapa yang punya “api intelektual” tapi tak benar-benar menyala, sehingga mahasiswa tumbuh secara manusiawi, percaya diri, kritis, dan berani berkata beda, bukan asal beda.
John Dewey pernah bilang, “Education is not preparation for life; education is life itself.” Kalau pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, maka komunikasi dosen-mahasiswa adalah denyut nadinya. Kalau denyut nadi itu lemah, jangan salahkan mahasiswa kalau mereka lulus dengan otak penuh tapi nalar kosong.
Saatnya kita berhenti memuja “dewa-dewa kampus” yang angkuh dan sulit dijangkau. Menuntut dosen lebih hebat tetapi tetap hangat, kita perlu dosen jenius tetapi rendah hati, dan jadi sahabat diskusi. Karena pada akhirnya, kampus yang hebat bukan karena punya dosen paling banyak gelar, tapi yang mempunyai dosen paling dekat dengan mahasiswanya, yang paham bahwa kampus adalah komunitas bagi “learning together”,