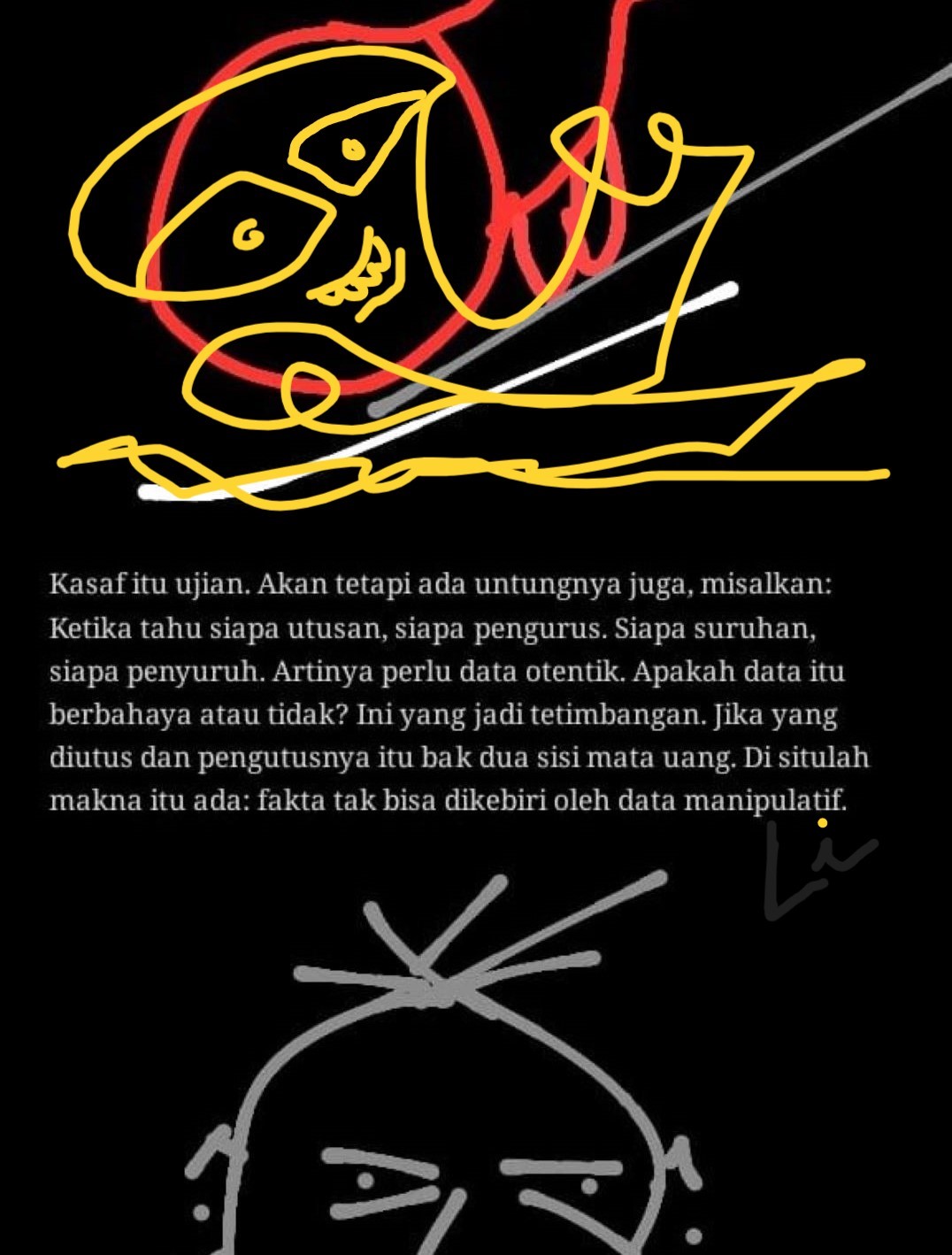Ketika uang menjadi alat kuasa dalam dunia sastra, di alas sepatu kaum ambisius, bukan niscaya akan lahir seribu bayi penyair cacat dari rahim kepalsuan kata-kata, kehilangan jiwa, menyubur budidaya, lupa pada kata malu.
Hari ini, aku bertandang ke sebuah pentas, bukan hendak membaca puisi-puisian, sekadar penyaksi kata-kata dijual di bawah meja juri, makna filsafat disembelih dengan angka,.dan nurani disewa untuk meriuhkan tepuk tangan.
Dunia sastra, abad kelam, serupa pasar malam, berpendar lampu gemerlap, meriah suara gaduh, sementara, di balik tenda, tercium bau anyir tipu daya, panitia yang menimbang kejujuran.dengan kurs mata uang.
Puisi pun kehilangan roh, menjadi brosur lomba, dihitung dengan nominal hadiah, jauh dari getar makna ke dada para pembaca yang tak mau terbius kamuflase, sastra kaleng-kaleng, kata orang seberang!
Betapa murahnya kemurnian, kejujuran pada keabadian kata-kata! Penyair yang dulu menulis dengan darah, kini menulis dengan rekening bank. Kalimat tak lagi ditimbang dari nilai rasa karsa,
tapi dari siapa yang menulis dan siapa yang membayar.
Di dunia sastra yang semestinya merdeka, kata “adil” dan “jujur” telah dilumuri sponsorship. Mereka bilang: “Begitulah peradaban sastra, ikut terlarut serba profesional.” Padahal yang mereka maksud: “Semua harus bisa ditukar dengan mata uang,” tandas lugas.
Penyair miskin yang menulis di pinggir tepian sungai sesampahan, menjadi penyaksi derita buruh, menulis dengan cahaya lampu tetangga, akan ditertawakan oleh panitia penghargaan karya sastra, sebab puisinya tak beraroma “nilai jual”, apalagi tak punya koneksi dengan para pencari proyek laba lewat dunia sastra.
Lihatlah, buku-buku pemenang lomba dicetak wangi di atas kertas impor, tapi isinya makanan gosong, seperti janji oknum pejabat untuk diserahkan kepada si buta menatap senja.
Para juri bertopeng akademika, memegang pena bak berpedang,
menebas siapa tak mau tunduk,
menulis penilaian tak lagi diperlukan rasa, melainkan berdasarkan kalkulasi manupulasi dikemas rapi.
Tanpa malu rasa pula, bahwa itu bentuk “etika sastra.” Padahal sejatinya—itu adalah sastrauang obralan!
Apa yang paling memilukan? Para pembaca sudah terbiasa dikelabuhi.
Mereka menelan puisi-puisi kosong
seperti menelan iklan sirup di bulan ramadhan. Manis di lidah, pahit di jiwa.
Kini, menjadi penyair bukan lagi urusan kejujuran dan kemurnian, melainkan siapa yang punya kumpulan uang di bank, di atas mobil menghamburkan uang, para pembaca puisi yang lapar, memuja tuan sastrauang!
Dan jika puisi mau dibacakan, uang titipkan para pembaca di atas pentas, padahal yang mereka baca lembaran koran tanpa berita yang bisa dijual.
Hai pembaca puisi wali dari rakyat miskin, datanglah kepada para penyair bermodal uang segudang, siapkan suaramu sebagai pembaca karya sastra amplop, sambil melupakan, kotoran kucing dirasa coklat!
Biar ambisi popularitas menari di atas perut keroncongan, tak apa pula, sebutlah sang juragan maestro sastra, Tuhan memberi jaminan halal, babi halal bila tersesat di rimba raya!
Ah, dunia sastra kini berdiri di atas panggung silau cahaya, tak peduli berlantai rapuh, dibangun sambil onani, bukan terlahir dari nurani.
Di pojok ruangan, ada seorang penyair tua, usianya lebih dari delapan puluh tahunan, menatap para “penyair kelapa muda” dengan getir, menulis puisi dengan tangan gemetar, sebab tinta idealis tersisa satu tetes. namun, masih percaya—bahwa suatu hari, puisi akan kembali seputih melati,.dan para pendusta akan terkubur dalam kesemuan makna kata.
Sementara itu, lomba karya sastra atau gelar baca sastra atau penghargaan sastra terus bersambung pat gulipat, plakat dan sertifikat diserahkan dengan meninggikan dada, diiringi tepuk tangan plastik. sambil berselfie-ria, mengangkat piala penghargaan atasnama proyek budidaya sastra.
Sementara di ujung jaman, penyair yang lahir dari kantung kemiskinan, menulis kepedihan, jauh dari sorot kamera, menghias halaman media kertas atau maya.
Para penyair yang menulis di kertas bekas nasi bungkus, tak berhenti bersaksi tentang buruh bergaji sore hari, besok berhutang lagi, atau tentang petani yang menangis di meja hukum, tentang anak-anak yang belajar di bawah kolong jembatan, menahan lapar dan telanjang, itulah karya sejati dan berbudi pekerti, meski terasi, tak berdasi, itu disebut bukan gizi bagi mafia sastra!
Sedangkan para penyair sambil bersalon, menenggak anggur di bawah rembulan, berdebat tentang metafora dan diksi, tapi lupa bahwa rakyat butuh makna, bukan asal bergaya, dan seorang pengusaha, sambil mabuk, menutup halaman buku kumpulan puisi, berjudul ‘Legenda Sastrauang dari Negeri Bualan’
Desa Singasari, Rabu, 29 Okt 2025., 04.05