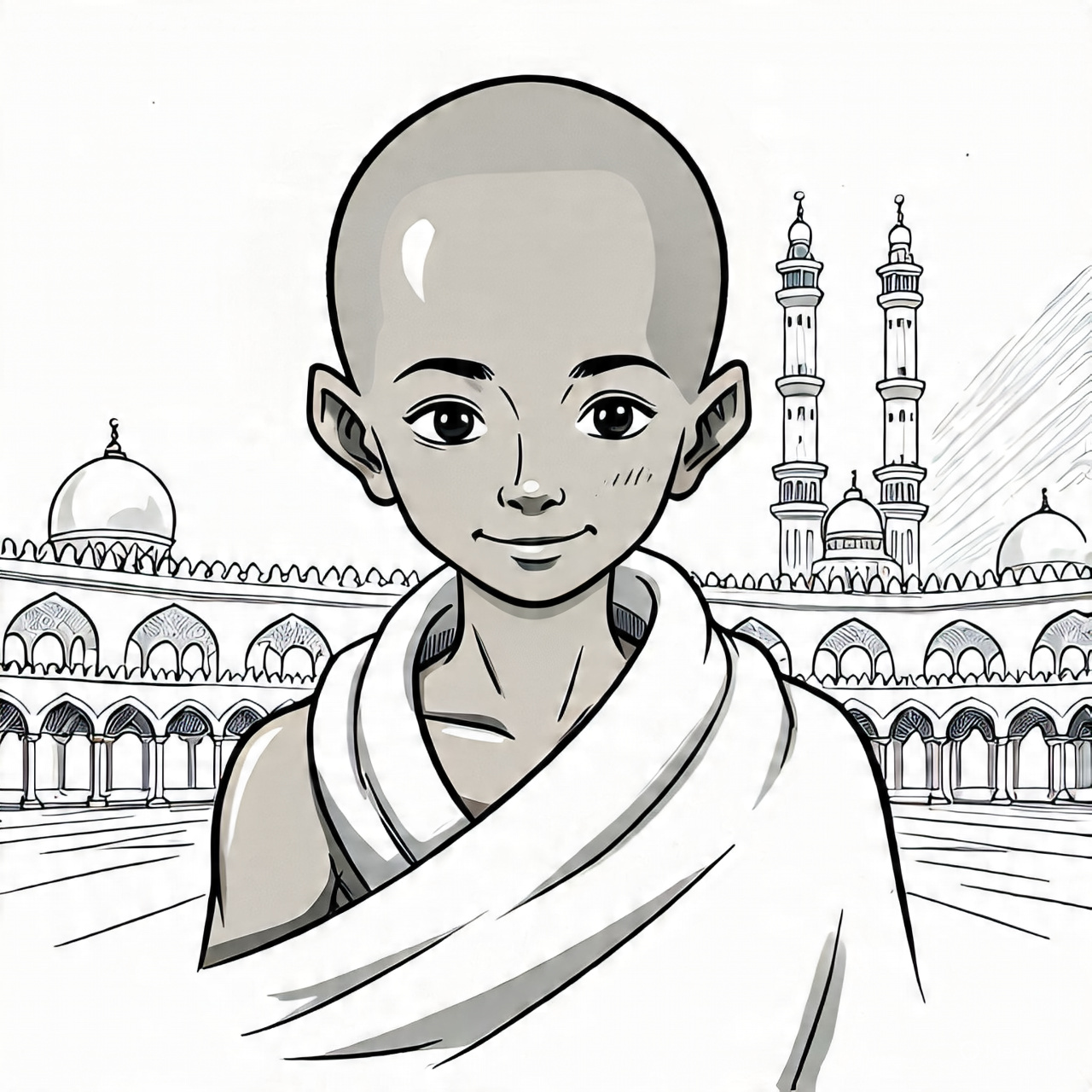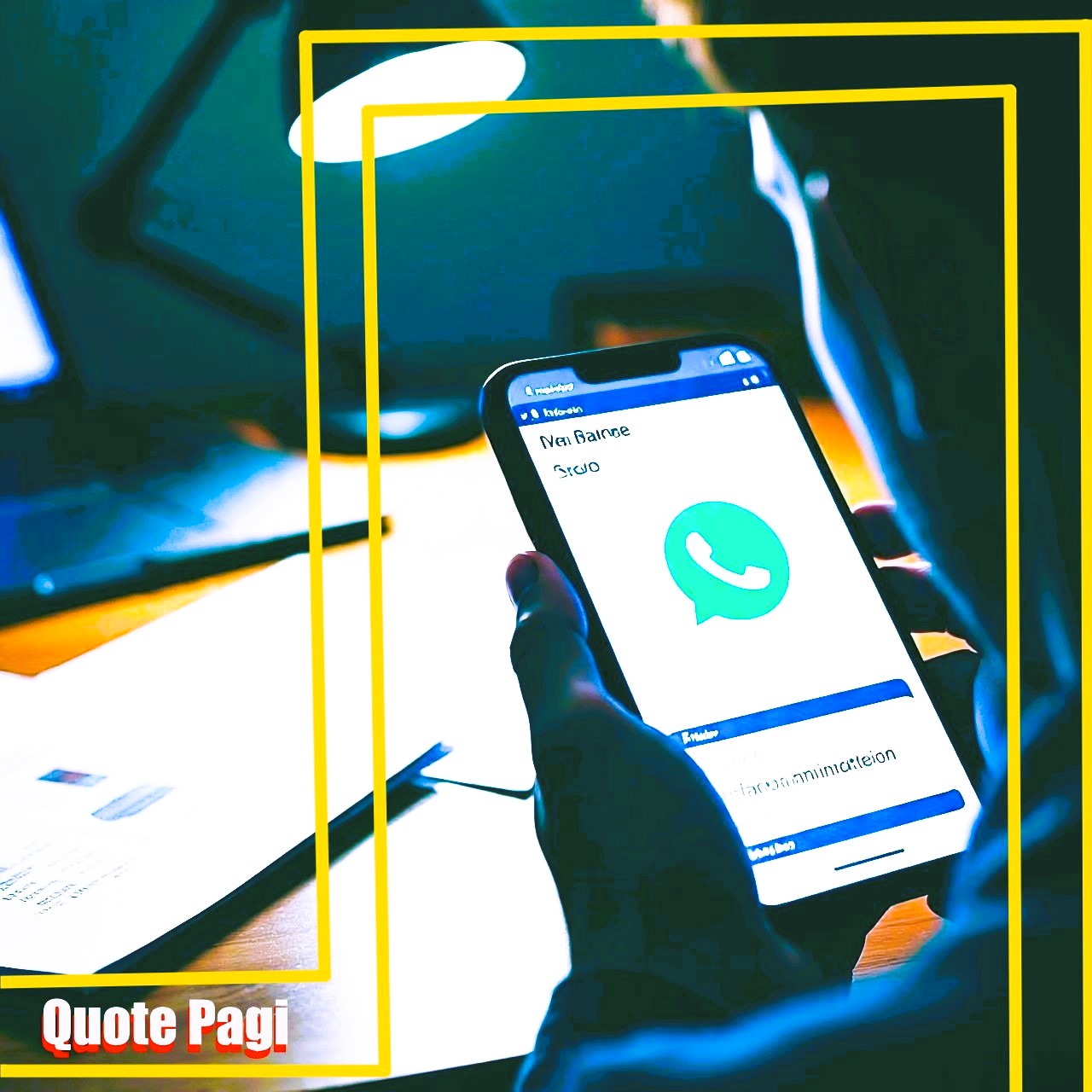“Apakah Undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Sidang Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).
“Setuju,” seru anggota DPR serentak.
Keputusan itu lahir setelah Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, membacakan laporan Panitia Kerja (Panja). Menurutnya, revisi UU ini didorong kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, mulai dari sektor akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga kesehatan, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Termasuk pula peningkatan layanan di Armuzna — Arafah, Muzdalifah, dan Mina — yang kerap menjadi titik kritis pelaksanaan ibadah haji.
Namun, yang paling menyita perhatian publik adalah keputusan Panja DPR bersama pemerintah yang menyepakati perubahan kelembagaan penyelenggara haji. Badan Pengelola Haji (BP Haji) akan ditingkatkan menjadi sebuah Kementerian Haji dan Umrah.
Dari sisi normatif, gagasan ini terkesan menjanjikan. Kementerian khusus diharapkan dapat fokus penuh mengelola ibadah haji dan umrah yang melibatkan jutaan jamaah setiap tahun. Apalagi, Indonesia adalah negara dengan kuota haji terbesar di dunia. Dengan adanya kementerian baru, diharapkan ada peningkatan layanan dan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi.
Tetapi, jika ditinjau dari perspektif efektivitas kelembagaan negara dan prinsip efisiensi birokrasi, pembentukan kementerian baru justru menyisakan pertanyaan serius. Pertama, penyelenggaraan haji dan umrah sejatinya sudah menjadi tugas Kementerian Agama (Kemenag). Di dalamnya bahkan ada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) yang secara spesifik menangani urusan ini. Artinya, dari sisi fungsi dan struktur, Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat kelembagaan.
Kedua, pembentukan kementerian baru akan menambah beban struktur birokrasi negara. Sejarah menunjukkan bahwa pembentukan lembaga baru kerap memperbesar beban anggaran, menambah lapisan koordinasi, dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Padahal, konstitusi dan undang-undang tentang kelembagaan negara (UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) menganut prinsip efisiensi, sehingga kementerian tidak boleh dibentuk sembarangan.
Ketiga, pelayanan haji lebih tepat dibenahi melalui perbaikan manajemen internal Kemenag ketimbang menambah kementerian baru. Problem klasik dalam penyelenggaraan haji biasanya bukan semata kelembagaan, melainkan persoalan teknis: pengadaan layanan, koordinasi dengan pihak Arab Saudi, transparansi biaya, dan integritas birokrasi. Semua ini bisa diperkuat dengan reformasi tata kelola di Kemenag tanpa harus membentuk kementerian khusus.
Dalam teori administrasi publik, pembentukan organisasi baru hanya layak dilakukan jika beban kerja tidak bisa lagi ditampung oleh struktur yang ada. Sementara pada konteks haji dan umrah, beban itu masih bisa diatur melalui optimalisasi Ditjen PHU, bahkan bisa diperkuat dengan model badan khusus di bawah Kemenag yang bersifat semi-otonom, mirip dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Model semacam ini lebih sejalan dengan prinsip efisiensi birokrasi.
Dengan demikian, gagasan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sesungguhnya lebih banyak menimbulkan persoalan ketimbang solusi. Alih-alih menambah kementerian baru, pemerintah seharusnya fokus memperkuat Kemenag yang selama ini sudah berpengalaman mengelola haji. Efektivitas pelayanan haji tidak ditentukan oleh label kelembagaan, melainkan oleh profesionalitas, transparansi, dan integritas penyelenggara.
Singkatnya, jika ditilik dari perspektif efektivitas kelembagaan dan efisiensi birokrasi, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebaiknya ditinjau ulang. Kemenag cukup diperkuat, bukan dipisahkan. Karena sejatinya, reformasi manajemen lebih urgen daripada menambah bangunan birokrasi baru. []