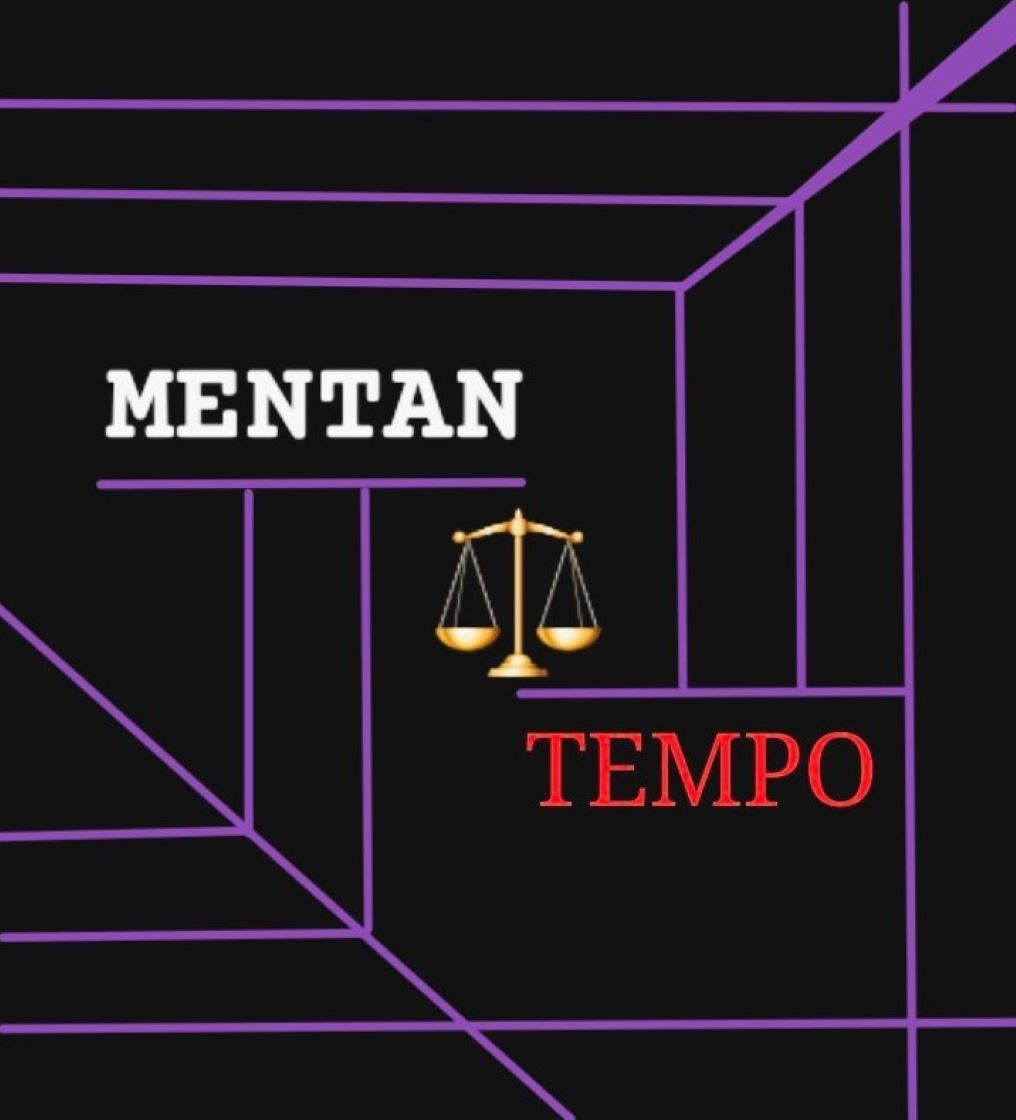Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan 128/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan hakim MK, bukan sekadar ketukan palu biasa. Tetapi semacam “autopsi dingin” atas anatomi kekuasaan yang telah lama dipertahankan publik: lebih dari 4.350 anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil di kementerian, lembaga, dan BUMN kini dipaksa memilih mundur dari seragam coklat atau melepaskan kursi di luar markas. Tidak ada lagi ruang abu-abu.
Yang membuat putusan ini mengguncang bukan hanya skalanya, melainkan asal-muasalnya: gugatan seorang advokat muda dari Mataram, Syamsul Jahidin, bersama Christian Adrianus Sihite. Dengan logika konstitusional yang lugas: bahwa mereka menganggap penempatan polisi aktif di jabatan sipil tanpa alih status melanggar kepastian hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) dan membahayakan supremasi sipil.
Kemenangan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi kemudian, dengan suara mayoritas delapan hakim (disertai dissenting Daniel Yusmic dan concurring Arsul Sani), menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tentang Kepolisian. Artinya: polisi aktif hanya boleh menjabat di luar struktur Polri jika sudah pensiun atau mengundurkan diri.
Demokrasi modern bukan sekadar kotak suara setiap lima tahun. Ia adalah sistem di mana kekuasaan sipil (civilian rule) mengendalikan sepenuhnya aparatus bersenjata dan koersif, termasuk polisi.
Ketika 4.351 polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa alih status, terjadi penetrasi militeristik ke dalam birokrasi sipil. Jika dibiarkan ini bukan hanya melanggaran konstitusi tapi juga merusak demokrasi.
Frasa penugasan khusus melanggar.
Kata sederhana penugasan “khusus” yang selama ini ditengarai menjadi pintu belakang kooptasi jabatan itu. Ini mengingatkan kita pada pernyataan sistemik Max Weber bahwa dalam supremasi sipil, mengacu pada teori birokrasi rasional-legalnya, legitimasi otoritas modern harus bertumpu pada kompetensi dan prosedur impersonal, bukan pada karisma seragam atau loyalitas hierarkis kepolisian. Ketika seragam coklat menduduki kursi sipil, terkesan bahwa kompetensi digantikan kooptasi, meritokrasi digantikan patronase. Sementara itu Montesquieu telah memperingatkan berabad lalu: jika kekuasaan eksekutif bercampur dengan aparatus koersif tanpa batas jelas, maka tirani akan lahir dalam wajah demokrasi.
Ingat,demokrasi modern bukan sekadar kotak suara setiap lima tahun, tetapi sistem dimana kekuasaan sipil (civilian rule) mengendalikan sepenuhnya aparatus bersenjata dan koersif, termasuk polisi.
Ketika lebih 4.350 polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa alih status, terjadi penetrasi militeristik ke dalam birokrasi sipil. Ini bukan demokrasi, ini semacam dwifungsi versi sipil, versi halus dari ABRI era Orde Baru.
Militerisasi birokrasi?
Dalam pandangan Michel Foucault, kondisi ini dapat dibaca sebagai fenomena “disciplinary power” yang meluber. Polisi tidak lagi hanya menegakkan hukum, melainkan mengelola kehidupan sipil melalui jabatan-jabatan strategis. Ada semacam ”hidden agenda” yang terselundup, netralitas institusi tercemar, dan akhirnya negara menjadi oligarki berbalut prosedur administratif.
Sejarah reformasi mencatat, bagaimana supremasi sipil dengan getol memperjuangkan pemisahan Polri dari militer pasca-Reformasi 1998. Makan Tidak salah jika mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyebut putusan ini sebagai “koreksi telat tapi tepat atas penyimpangan dwifungsi versi sipil”. Menurutnya, sejak Polri dipisah dari ABRI tahun 1999, seharusnya sudah tidak ada lagi “penugasan” yang membolehkan anggota aktif menduduki jabatan sipil tanpa alih status. “Supremasi sipil bukan slogan, tapi prinsip konstitusional yang harus dijaga dengan nyawa.”
Penempatan polisi aktif di jabatan sipil sebagai bentuk militerisasi birokrasi sipil yang terselubung. Ini dapat merusak prinsip “checks and balances” dan membuka celah korupsi kolusif karena rantai komando militeristik tetap hidup.” Publik berharap keputusan ini bisa jadi “trigger” bagi upaya menutup pintu bagi preseden serupa di tubuh TNI, yang kini sedang digugat terpisah oleh Syamsul Jahidin pula.
Disisi lain, putusan ini akan menjadi masukan konstruktif bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang sedang bekerja.s Sehingga kedepan tak ada lagi celah hukum yang dieksploitasi secara sistematis untuk praktek serupa.
Sistem yang salah bukan nasib.
Putusan ini memaksa kita bertanya: mengapa persoalan penting ini harus menunggu gugatan seorang advokat dari Mataram, sementara ribuan profesor hukum tata negara, aktivis, dan politisi senior memilih diam atau bahkan menikmati status quo? Apakah karena jabatan sipil itu terlalu menggiurkan? Apakah karena takut dipersoalkan balik oleh kekuasaan aparat? Atau jangan – jangan karena kita telah terbiasa hidup dalam rezim ketakutan akut? Masih ingat bukan, Filsuf Socrates pernah dihukum mati karena menggugat tirani mayoritas yang diam.
Syamsul Jahidin tidak akan dihukum mati, sementara ia telah melakukan hal yang sama: menggugat tirani kebiasaan yang sudah membusuk. Ia membuktikan bahwa konstitusi bukan dokumen mati di lemari arsip, melainkan senjata hidup yang bisa dipegang siapa saja yang masih punya keberanian moral. Sistem yang salah bukanlah “nasib sejarah”, melainkan rekayasa kolektif yang dipelihara karena menguntungkan. Selama ini kita membiarkan polisi aktif menjadi komisaris BUMN, kepala badan, bahkan pengelola program makan bergizi gratis, seolah negara ini kekurangan SDM sipil yang kompeten. Padahal yang kekurangan adalah “political will” untuk menegakkan prinsip.
Putusan MK kemarin adalah palu yang membelah abu-abu kekuasaan. Ia mengatakan: polisi harus kembali ke markas,menjadi menjadi polisi menjaga ketertiban, institusi sipil harus dikelola sipil. Tidak ada kompromi. Jika tidak, kita hanya sedang menunda kematian demokrasi konstitusional kita sendiri.
Dr. Eko Wahyuanto adalah Dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Yogyakarta