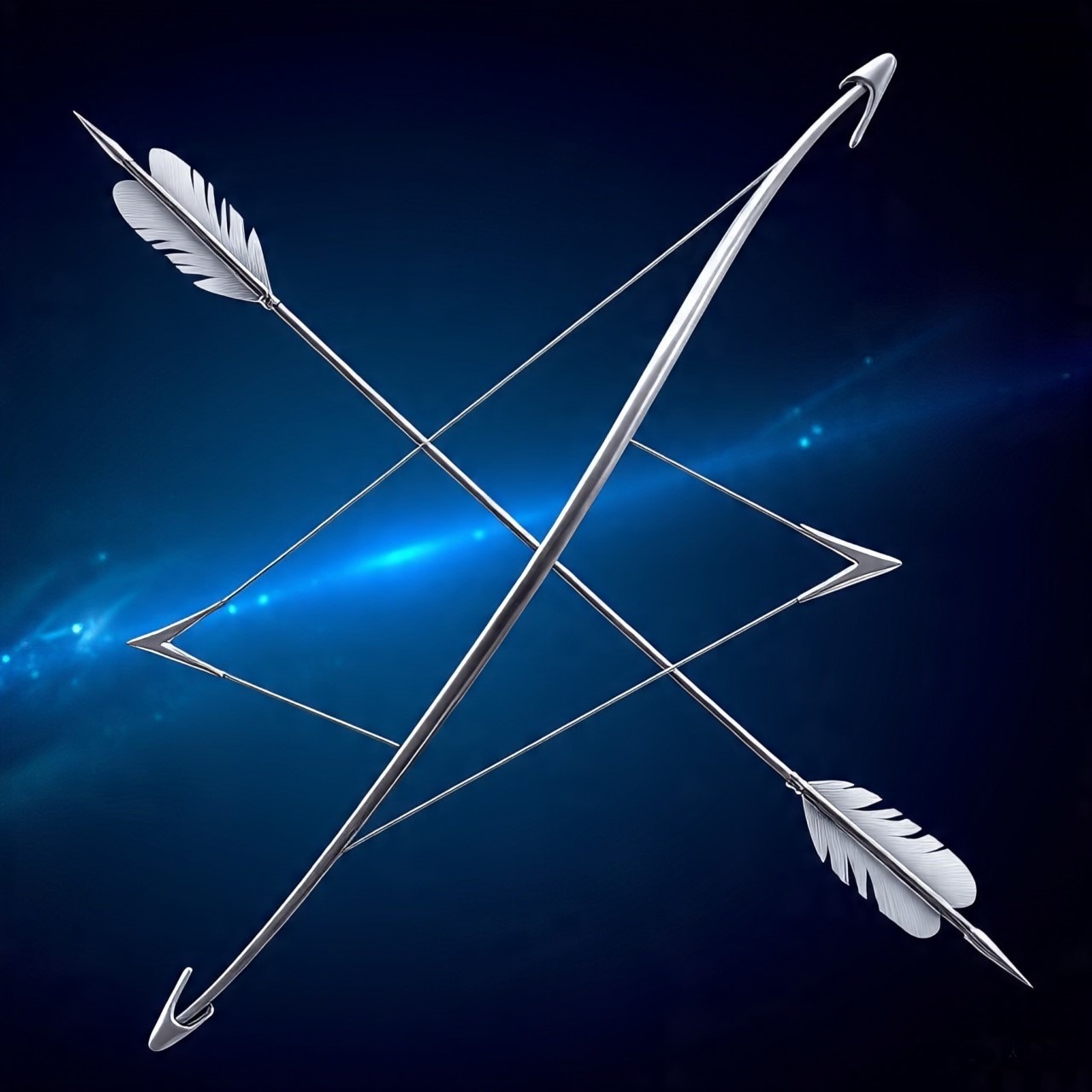Dalam beberapa hari terakhir, beredar narasi bahwa dunia sedang memasuki fase genting menuju perang besar. Salah satu yang sering dijadikan rujukan adalah langkah pemerintah Belanda yang menyebarkan panduan bertahan hidup 72 jam kepada seluruh warganya.
Di media sosial, informasi ini berkembang liar: disebut sebagai sinyal perang dunia, bahkan dikaitkan dengan Amerika Serikat sebagai pemicu konflik global. Di Indonesia sendiri, narasi semacam ini cepat menyebar karena publik kita masih sensitif terhadap isu geopolitik dan krisis global. Padahal, jika ditarik ke konteks yang sebenarnya, panduan tersebut bukan selebaran perang. Ini adalah bagian dari kebijakan kesiapsiagaan sipil.
Pemerintah Belanda mendorong warganya agar mampu bertahan secara mandiri dalam 72 jam pertama ketika terjadi krisis besar, saat bantuan negara belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk Indonesia, negara besar dengan wilayah luas dan tantangan distribusi bantuan yang tidak selalu bisa instan.
Kesiapsiagaan Sipil di Era Ketidakpastian Global
Dunia modern berdiri di atas sistem yang saling terhubung, seperti listrik, air bersih, jaringan komunikasi, dan distribusi logistik. Gangguan kecil saja dapat memicu efek berantai yang cepat melumpuhkan kehidupan sehari-hari.
Indonesia, dengan kondisi geografis kepulauan dan kerentanan bencana, sesungguhnya menghadapi risiko yang sama, bahkan dalam skala yang lebih kompleks. Dalam konteks inilah panduan 72 jam disusun. Warga diarahkan untuk menyiapkan kebutuhan dasar seperti air minum dan makanan tahan lama, alat penerangan dan baterai cadangan, radio yang tidak bergantung pada internet, obat-obatan pribadi, dokumen penting dalam bentuk fisik, uang tunai, serta rencana komunikasi keluarga.
Jika ditarik ke Indonesia, panduan semacam ini justru sangat relevan untuk menghadapi gempa, banjir besar, atau pemadaman listrik luas. Tidak ada narasi musuh, tidak ada ajakan perang, dan tidak ada instruksi militer. Yang ada hanyalah pendekatan realistis bahwa negara tidak selalu bisa hadir di menit pertama, sehingga warga perlu diberdayakan untuk bertahan sementara. Ini adalah pelajaran penting bagi Indonesia, di mana ekspektasi terhadap kehadiran negara sering kali lebih cepat daripada kapasitas di lapangan.
Analisa: Mengapa Isu Ini Mudah Dipelintir
Narasi perang mudah menyebar karena dunia memang sedang dipenuhi ketegangan geopolitik. Konflik regional, perang informasi, dan persaingan kekuatan besar membuat publik sangat sensitif terhadap simbol-simbol kesiapsiagaan.
Di Indonesia, situasi ini diperparah oleh arus informasi media sosial yang cepat, sering kali tanpa verifikasi, sehingga edukasi berubah menjadi kepanikan. Di sinilah letak kekeliruan. Kesiapsiagaan sering disalahartikan sebagai ketakutan, padahal justru sebaliknya: ia adalah bentuk rasionalitas negara dalam menghadapi ketidakpastian.
Seperti sabuk pengaman, ia disiapkan bukan karena berharap kecelakaan, tetapi karena memahami risiko selalu ada, sebuah logika yang seharusnya juga menjadi budaya publik di Indonesia.
Kaitannya dengan Indonesia: Kita Jauh dari Perang, Tapi Dekat dengan Krisis
Bagi Indonesia, isu ini seharusnya dibaca sebagai cermin, bukan peringatan perang dunia. Secara geopolitik, Indonesia relatif aman dan tidak berada di pusat konflik global. Namun pada saat yang sama, Indonesia sangat dekat dengan krisis non-militer, seperti: bencana alam, cuaca ekstrem, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga gangguan listrik dan distribusi logistik.
Kesiapsiagaan masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada negara. Ketika bencana terjadi, kepanikan sering muncul karena warga tidak terbiasa menyiapkan kebutuhan dasar untuk bertahan mandiri dalam beberapa hari pertama. Padahal, fase awal inilah yang paling menentukan keselamatan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau bantuan cepat.
Pelajaran Penting: Ketahanan Warga Adalah Kekuatan Negara
Apa yang dilakukan Belanda seharusnya dipahami sebagai pelajaran, bukan ancaman. Ketahanan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi dari seberapa siap warganya menghadapi krisis sehari-hari. Bagi Indonesia, ini berarti membangun budaya siap siaga yang membumi, bukan sekadar respons darurat ketika bencana sudah terjadi.
Negara yang kuat bukan negara yang menjanjikan “semuanya akan baik-baik saja”, melainkan yang jujur mempersiapkan warganya agar tetap tenang, tertib, dan selamat ketika keadaan darurat benar-benar terjadi.
Penutup: Dunia Tidak Baik-Baik Saja, dan Indonesia Harus Bersiap
Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja, dan mengabaikan kenyataan itu justru lebih berbahaya daripada menghadapinya dengan kepala dingin. Ketegangan global, krisis energi, perang informasi, perubahan iklim, hingga rapuhnya sistem digital menunjukkan bahwa ancaman masa depan tidak selalu datang dengan dentuman senjata, tetapi sering hadir diam-diam, melumpuhkan kehidupan sehari-hari tanpa aba-aba.
Dalam situasi seperti ini, kewaspadaan bukanlah kepanikan, dan kesiapsiagaan bukanlah paranoia. Ia adalah bentuk kesadaran kolektif bahwa negara, sekuat apa pun, memiliki batas. Indonesia, dengan segala potensi dan kerentanannya, perlu membaca pesan ini dengan serius. Belanda telah memilih untuk jujur kepada warganya bahwadunia penuh risiko dan setiap orang perlu bersiap.
Indonesia pun perlu mengambil pelajaran yang sama, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kedewasaan. Karena di era ketidakpastian global, bangsa yang bertahan adalah yang paling siap menghadapi kenyataan. Kewaspadaan hari ini adalah investasi untuk keselamatan esok hari. Dan bagi Indonesia, kesiapan bukan lagi pilihan, maka ia adalah keharusan.