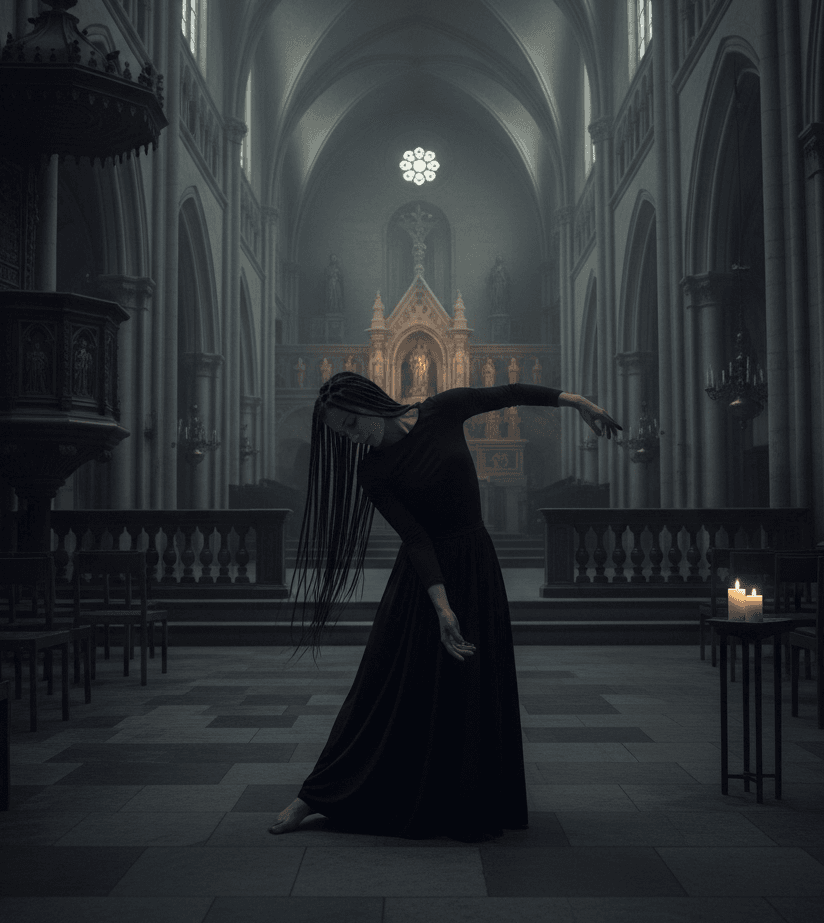ADA YANG HIDUP
ADA YANG MATI …
MATA PENCARIAN
Oh bumi merah putihku,
kami pernah hidup di layar lebar,
di gulungan seluloid berbau
cuka dan mimpi, di studio sempit,
lampu panas, dan honor yang
kadang datang belakangan
bersama janji madu …
“Tenang, nanti beres.”
Kami adalah wajah-wajah
yang pernah dipajang di poster
bioskop, nama yang dulu disebut
penonton sebelum lampu padam
dan doa dipanjatkan diam-diam:
semoga filmnya bagus, semoga hidup ikut membaik adanya.
Tahun tujuh puluhan, kamera belum canggih, tapi harapan tajam. Aktor berdiri gagah meski sepatu bolong, aktris tersenyum anggun meski dompet menipis. Crew bekerja seperti tentara tanpa pangkat: tukang lampu, penata suara, penulis skenario yang sering tak disebut, sutradara yang merangkap psikolog dan bendahara harapan.
Kami syuting siang malam, di rawa, di gunung, di laut, menantang nyamuk, hujan, dan sensor. Kami dikejar waktu, dikejar produser, dikejar mimpi yang katanya:
“Kalau film ini laku, hidup kita berubah.”
Ada yang berubah.
Ada yang benar-benar naik kelas.
Ada yang rumahnya kini bertingkat,
namanya disebut pejabat, dipanggil di karpet merah. Tapi lebih banyak yang tertinggal di lorong panjang bernama nanti.
Delapan puluhan datang dengan gemerlap baru. Genre beranak-pinak: laga, komedi, roman, dangdut, horor. Kami ikut arus, kadang tak sempat bertanya:
“Ini seni atau sekadar bertahan hidup?”
Aktor laga patah tulang betulan,
tanpa asuransi. Aktris menangis sungguhan, tanpa konselor. Crew jatuh dari rigging, lalu bangkit lagi karena besok masih syuting.
Kami menghibur bangsa yang sedang belajar tertawa di tengah pembangunan. Kami jadi pelarian
dari harga beras,
dari berita politik,
dari hidup yang makin mahal.
Lalu sembilan puluhan:
televisi merajalela.
Film layar lebar goyah.
Bioskop sepi,
kamera dijual,
studio disewakan untuk gudang. Sebagian dari kami pindah ke sinetron …
mengejar episode,
mengejar rating,
mengejar napas.
Sebagian lagi tercecer,
pulang ke kampung.dengan koper berisi foto lama dan cerita yang hanya laku di warung kopi.
Masuk dua ribuan, kami diajak bangkit. Katanya: film Indonesia bangun! Kami bersorak, tapi lupa bertanya: siapa yang diajak bangun, dan siapa yang dibiarkan tidur selamanya?
Teknologi melesat,
kamera makin kecil,
ego makin besar.
Festival digelar,
penghargaan dibagikan,
tepuk tangan menggema—
namun hanya untuk nama
yang itu-itu saja.
Yang muda dipuja sebagai masa depan. Yang lama dipandang sebagai masa lalu. Seolah pengalaman punya tanggal kedaluwarsa. Seolah dedikasi bisa diganti oleh algoritma dan jumlah pengikut.
Ada aktor senior menunggu panggilan syuting sambil menjaga cucu. Ada aktris legendaris menjual perhiasan untuk biaya berobat. Ada kru kamera yang dulu mengatur cahaya bintang, kini mengatur parkir
di gedung perkantoran.
Kami tidak minta dikasihani.
Kami hanya bertanya,
dengan nada satir,
dengan senyum pahit:
“Di mana negara saat kami menghibur negara?”
Kami bukan patung museum.
Kami bukan nostalgia murahan
untuk acara ulang tahun
stasiun TV.
Kami manusia,
dengan perut,
dengan sakit,
dengan hari tua
yang juga butuh kepastian.
Parodi ini nyata: film tentang kemiskinan menang penghargaan,
tapi kru pembuatnya pulang dengan rekening kosong. Film tentang keadilan sosial dipuji, tapi pekerja film tak punya jaminan sosial.
Humor segar tapi menohok: kami bisa bikin penonton tertawa dua jam, tapi tak bisa menertawakan
nasib sendiri yang digantung kontrak harian.
Kritik ini pedas seperti cabai rawit, bukan untuk membakar, tapi agar terasa. Agar lidah kebijakan tak kebas oleh pidato sendiri. Kami tidak menuntut istana. Kami hanya mengusulkan:
— Regulasi yang melindungi
pekerja film, bukan hanya investor.
— Dana abadi kebudayaan
yang benar-benar sampai ke
tangan insan film, bukan
berhenti di seminar.
— Arsip nasional yang hidup,
yang melibatkan para pelaku
lama sebagai guru, mentor,
saksi zaman.
— Jaminan kesehatan dan
hari tua bagi aktor, aktris, dan kru yang telah menyumbang umur untuk layar bangsa.
Ini bukan ratapan,
ini pamflet. Ditempel di dinding kesadaran. Dicoret dengan spidol satire, dibacakan dengan nada sengak, tapi niatnya bersih:
agar industri ini tidak memakan anaknya sendiri. Kami percaya pada regenerasi, tapi juga percaya pada ingatan. Bangsa tanpa ingatan mudah diulang kesalahannya. Industri tanpa penghormatan mudah kehilangan jiwanya.
Tahun dua ribu dua puluh lima,
kami masih di sini.
Sebagian masih shooting,
sebagian masih menunggu,
sebagian sudah pergi tanpa sempat berpamitan pada negara yang pernah mereka hibur.
“Hidup segan, mati tak mau,”
bukan takdir. Itu hasil kebijakan yang lupa bahwa seni bukan sekadar konten, dan insan film bukan angka statistik. Maka dengarlah pamflet ini,
wahai penentu arah.
Kami tidak berteriak,
kami berbicara.
Dengan satire
sebagai pelindung, solusi
sebagai tujuan. Jika bangsa ini
bangga pada cerita di layar,
maka jagalah para penceritanya. Karena film bisa diulang, namun
hidup manusia tidak punya
tombol replay.
Sanggar De Batavia
Minggu, 14 Des 2025
18.00