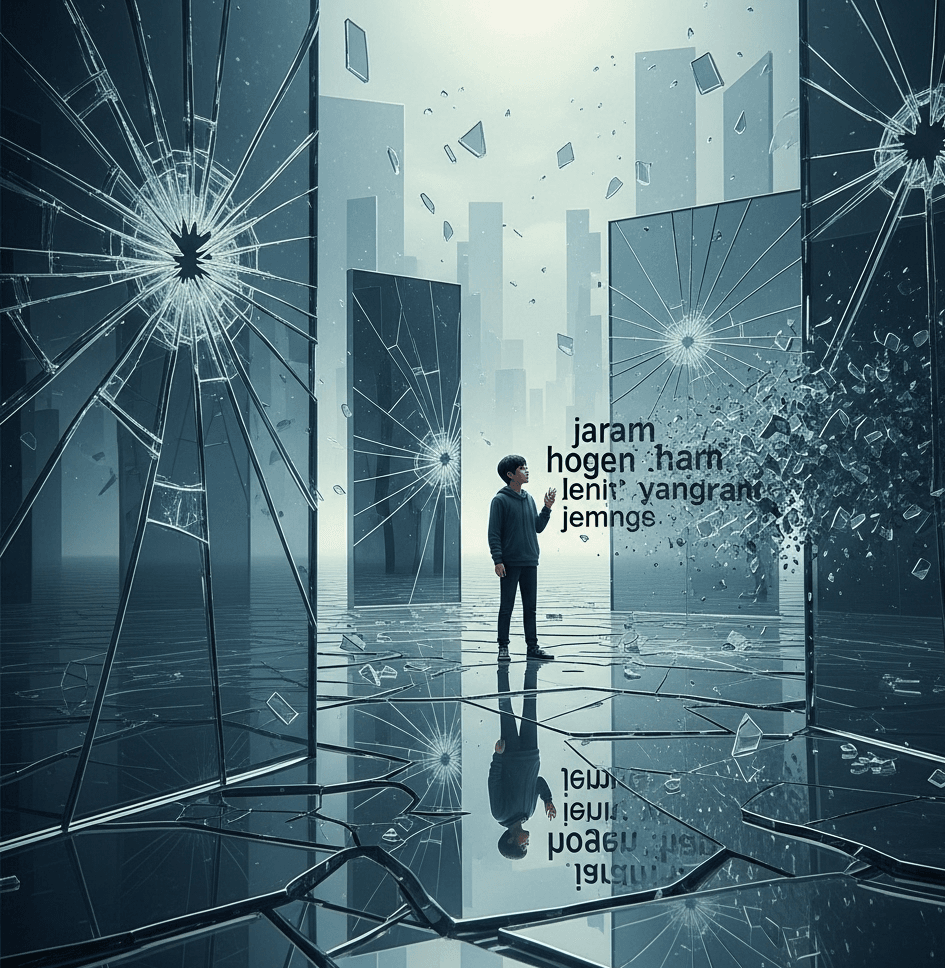RADEN SALEH,
ALI SADIKIN,
KEBUN BINTANG,
TAMAN ISMAIL MARZUKI:
RUMAH BESAR SENIMAN
YANG HILANG
Bang Ali Sadikin,
namamu bukan sekadar
tertera di papan jalan, atau
judul seminar setahun sekali
dengan spanduk belel dan
konsumsi ala kadarnya.
Namamu adalah keputusan,
yang diambil saat anggaran
lebih suka lari menjadi beton,
ke proyek yang bisa difoto
dari udara, bukan ke peluh
seniman yang hidup kerap
tak terdata di neraca
pembangunan.
Bang Ali,
engkau tahu benar bahwa bangsa tanpa seniman adalah bangsa yang gagap bicara, tak siap menertawakan diri sendiri, tak sanggup mengkritik kekuasaan tanpa berubah jadi teriakan kosong. Maka engkau bangun. Gelanggang Remaja, bukan satu, bukan dua,.tapi lima wilayah Jakarta, seolah berkata:
“Bakat tak boleh terpusat di satu gedung ber-AC, ia harus tumbuh
di sudut kota,
di pinggir lapangan,
di antara sepatu robek
dan gitar murah.”
Di sana anak-anak muda belajar berdebat tanpa baku hantam, belajar bermain peran tanpa jadi munafik, belajar musik tanpa harus kaya dulu.
Engkau paham, remaja yang diberi panggung tak akan mudah tergoda jadi figuran kejahatan. Lalu sejarah berputar pelan, Raden Saleh, maestro yang tak hanya melukis, tapi juga berpikir jauh ke depan menghibahkan tanah.untuk kebun binatang. Tempat di mana manusia
belajar rendah hati melihat makhluk lain hidup tanpa pidato, tanpa janji kampanye.
Ketika kebun binatang itu dipindahkan ke Ragunan, tanahnya tak kau jual pada spekulan berdasi, tak kau sulap jadi pusat belanja yang menjual diskon dan lupa.
Kau ubah namanya:
Taman Ismail Marzuki.
Bukan nama jenderal.
Bukan nama pejabat.
Bukan pula nama investor.
Nama seniman.
Itu pilihan politik paling sunyi
dan paling berani. Taman Ismail Marzuki menjadi rumah besar,
bukan istana. Tak ada singgasana, yang ada kursi kayu, kopi pahit, naskah yang direvisi tengah malam, lukisan yang ditolak galeri tapi dicintai zaman.
Di sana seniman miskin.tak dipermalukan. Di sana kritik tajam tak langsung dicap subversif. Di sana ide gila tak buru-buru dirawat di rumah sakit jiwa.
Bang Ali tahu,
seniman itu aneh,
keras kepala,
sering ribut soal hal sepele
tapi diam saat negeri dijarah.
Maka mereka perlu bapak,
bukan bos.
Bapak yang paham:
seni tak bisa disuruh cepat,
tak bisa ditargetkan seperti tender, tak bisa dipatok ROI per kuartal. Seni tumbuh dari kegelisahan, dan kegelisahan tak lahir di ruang rapat berpendingin udara.
Tahun-tahun berlalu,
lalu Taman Ismail Marzuki
melahirkan nama-nama besar,
yang kini fotonya terpajang di dinding museum dan halaman buku pelajaran, meski dulu mereka tak punya uang makan siang.
Jakarta menjadi kota.yang berani bicara, menertawakan diri sendiri, mengkritik penguasa tanpa harus sembunyi di lorong gelap. Lalu Bang Ali pergi.
Dan sejak itu,
ada yang terasa hilang
bukan di bangunan,
tapi di rasa aman.
Rumah masih berdiri,
tapi bapaknya tak lagi duduk
di beranda.
Setelah Bang Ali tiada,
seniman seperti anak yatim
yang diajak rapat tapi tak didengar.
Taman Ismail Marzuki mulai sering disebut sebagai aset, bukan rumah.
Anggaran mulai bicara lebih lantang daripada ide. Kurator mulai takut lebih dari pencipta.
Proposal lebih sakti daripada puisi. Gedung direnovasi, tapi jiwa sering tercecer
di balik dinding baru.
Seni mulai diminta sopan, ramah sponsor, aman bagi semua pihak,.kecuali bagi kebenaran. Humor masih ada, tapi tak lagi menggigit.
Satir masih tampil,.tapi sudah disterilkan. Seniman diminta kreatif, tapi jangan terlalu kritis. Diminta vokal, tapi jangan menyebut nama.
Bang Ali, di sinilah
kritik kami berdiri:
bukan untuk menghakimi,
tapi mengingatkan.
Negeri ini sering bangga
membangun gedung seni,
tapi lupa membangun
keberanian melindungi seniman.
Kita rajin merayakan Hari Seni,
tapi absen saat seniman
berurusan dengan sensor,
intimidasi, dan perut kosong.
Kita suka pidato soal budaya,
tapi alergi pada kritik yang lahir dari budaya itu sendiri. Parodi kami jadi senjata tumpul,
karena terlalu sering diminta menyenangkan semua orang. Padahal seni, bila menyenangkan semua pihak, biasanya sedang berbohong.
Bang Ali pernah mengajarkan lewat kebijakan, bukan ceramah: bahwa seniman
harus diberi ruang bahkan ketika mereka menyebalkan. Karena bangsa dewasa
tak anti terhadap
suara sumbang.
Kini,
solusi tak perlu muluk:
Kembalikan Taman Ismail Marzuki sebagai rumah,
bukan etalase. Kembalikan gelanggang sebagai tempat tumbuh, bukan sekadar bangunan serbaguna yang lebih sering dipakai acara seremonial.
Berikan keberpihakan nyata, bukan sekadar lomba proposal.yang hanya dimenangkan.oleh mereka
yang pandai menulis
bahasa birokrasi.
Biarkan seniman miskin tetap berkarya tanpa harus menjadi pengemis proposal.
Lindungi kritik, bahkan
yang pedas cabai rawit.
Karena cabai pedas.tanda masakan belum basi.
Humor jangan dimarahi,
satir jangan dicurigai,
parodi jangan
dipersekusi.
Bang Ali,
kau telah pergi,
tapi jejakmu masih jelas:
bahwa pemimpin besar tak takut pada seniman, karena ia tahu seni bukan musuh negara, melainkan cermin terkadang tak ingin kita tatap. Jika hari ini seniman terasa kehilangan bapak, itu bukan karena bapaknya tak meninggalkan warisan, melainkan karena kita
tak cukup berani
mewarisi sikapnya.
Maka pamflet ini
kami tempelkan di dinding
ingatan, agar generasi berikutnya tahu: pernah ada pemimpin yang mengerti bahwa bangsa besar tak hanya diukur dari jalan tol,.tapi dari seberapa jujur, ia mendengar
suara senimannya.
Dan Bang Ali Sadikin,
telah membuktikannya
tanpa perlu tepuk tangan
berlebihan.
Dari Timur Bekasi
Rabu, 17 Des 2025
13.23