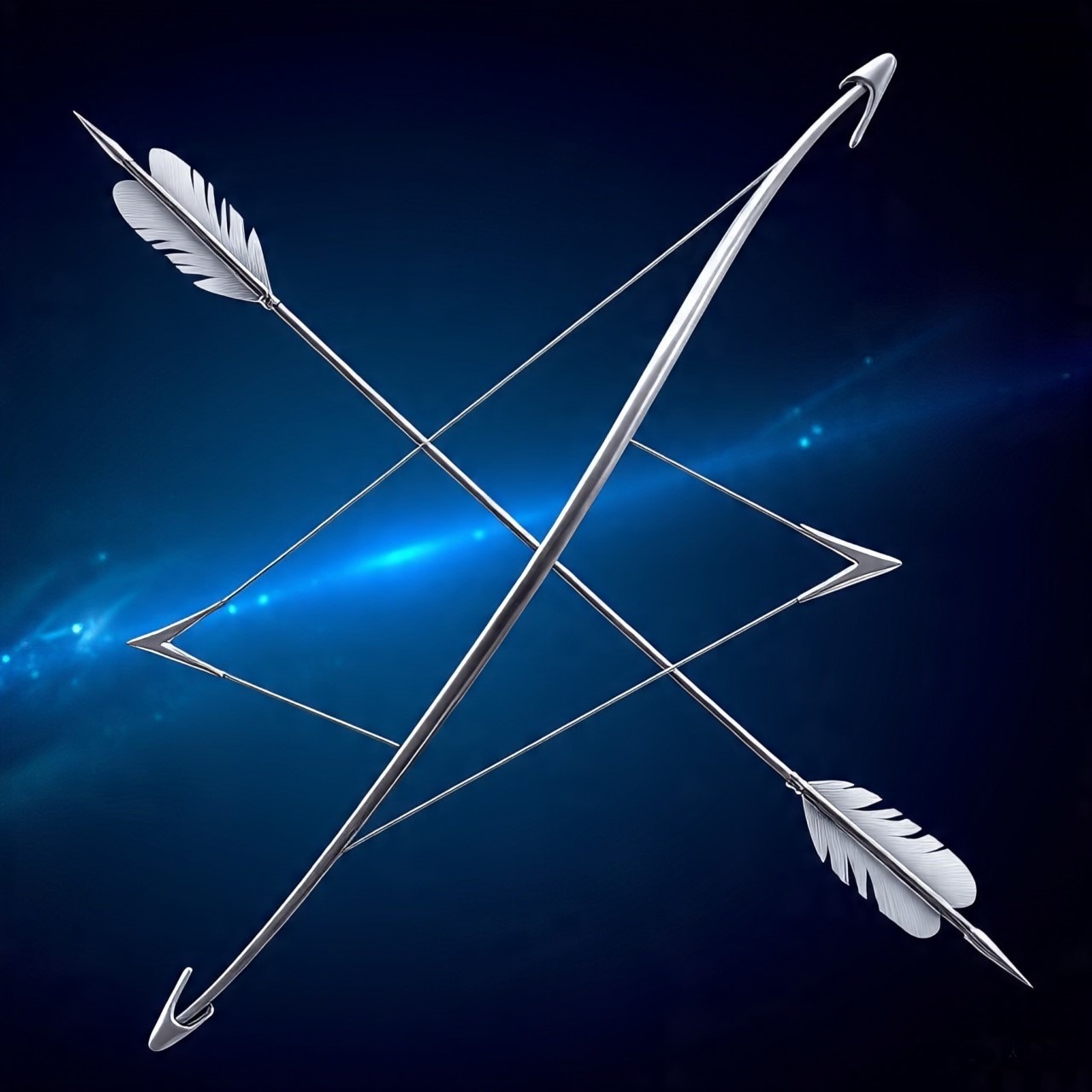Sikap Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menolak bantuan perusahaan yang diduga merusak hutan di daerahnya mendapat pujian. Sikap tegas di tengah krisis akibat bencana banjir dan longsor yang melanda daerahnya bukanlah mudah.
Vandiko mendapat sorotan publik karena Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2025 secara tegas minta seluruh perangkat daerah, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa, agar tidak menerima bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang diduga merusak lingkungan mereka.
Secara eksplisit, edaran tersebut menyebut PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) dan PT Aquafarm Nusantara, perusahaan yang sebelumnya diprotes agar dihentikan izin operasinya menyusul tuntutan masyarakat adat dan demonstrasi besar-besaran, atas masalah lingkungan dan perebutan lahan.
Keberanian Vandiko bukan soal respons impulsif terhadap bencana, tetapi demi merawat kontrak sosial antara dirinya dengan rakyat, sekaligus menjaga integritas pemerintahan dan menghindari persepsi keberpihakan pada kejahatan ekologi.
Belum lagi kemungkinan munculnya potensi konflik sosial, jika rakyat tahu pemerintah bergantung pada perusahaan musuh mereka.
Perusahaan yang memproduksi bubur kertas dan pengelola hutan tanaman industri dengan konsesi luas di Sumatera Utara itu, acap kali menjadi sasaran kritik masyarakat adat dan aktivis lingkungan. Mereka menuduh terlibat deforestasi, alih fungsi hutan alam, dan konflik agraria berlarut.
Langkah Vandiko itu selaras dengan seruan moral dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), yang memiliki 6,5 juta jemaat. Otoritas gereja juga menolak bantuan dari korporasi perusak lingkungan, termasuk TPL, sebagai bentuk kesadaran kolektif di masyarakat Batak bahwa bencana ekologis bukan semata musibah alam, melainkan ulah manusia melalui korporasi.
Fenomena ini merupakan dilema klasik pembangunan, antara pertumbuhan ekonomi melalui investasi korporasi dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Dalam konteks “land ethic”, menolak CSR merupakan etika moral dan “integritas biosfer” dalam merawat ekosistem.
Filsuf Norwegia Arne Naess, pendiri “Deep Ecology, pernah mengatakan, menolak paham “antroposentrisme” dimana manusia sebagai pusat segalanya dan mendorong “ecosophy” yang menekankan hubungan harmoni dengan lingkungan dapat digunakan melawan kekuatan destruktif. Di mana penolakan bantuan adalah bentuk perlawanan mendalam terhadap kejahatan eksploitasi.
Aktivis sosial Amerika Murray Bookchin, melalui “Social Ecology”, melihat masalah ekologis berakar pada hierarki sosial; sehingga penolakan terhadap CSR adalah upaya mengecam ketidakadilan struktural yang membiarkan korporasi mendominasi alam.
Sementara pakar politik internasional seperti Vandana Shiva getol mengkritik CSR sebagai “greenwashing” oleh korporasi multinasional di negara berkembang seperti Indonesia. Bantuan digunakan untuk penyamaran kerusakan ekosistem dan konflik perebutan lahan adat. Tindakan atas nama kerusakan lingkungan adalah kesalahan memahami keadilan distributif dan restitusi.
Noam Chomsky, kritikus korporatisme, melihat fenomena seperti ini sebagai perlawanan terhadap kekuasaan korporasi, yang menjadikan CSR sebagai benteng kejahatan eksploitasi. Karena itu perlu tindakan tegas seperti yang dilakukan Bupati Vandiko.
Ini teladan penting di saat banyak pejabat mudah tergoda “bantuan manis” dari korporasi, padahal ialah penyebab bencana itu. Penolakan semacam ini menjadi panggilan untuk prioritas ekologis, bahwa negara mendukung dengan tindakan tegas seperti itu
Dengan pesan segera dilakukan evaluasi izin konsesi, moratorium alih fungsi hutan, dan penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi. Hanya dengan itu, Sumatera, dan Indonesia bisa terhindar dari bencana berulang.
Vandiko telah menempuh jalan sulit, tapi benar, menolak bantuan yang bisa disebut sebagai “haram”, karena datang dari sumber kerusakan itu sendiri.
Semoga ini awal perubahan lebih luas menuju pembangunan lingkungan berkelanjutan untuk mencegah bencana lebih parah.